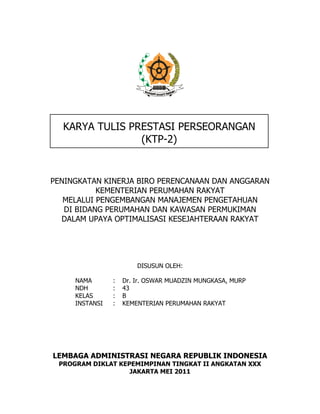
PENINGKATAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT MELALUI PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENGETAHUAN DI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DALAM UPAYA OPTIMALISASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
- 1. KARYA TULIS PRESTASI PERSEORANGAN (KTP-2) PENINGKATAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT MELALUI PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENGETAHUAN DI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DALAM UPAYA OPTIMALISASI KESEJAHTERAAN RAKYAT DISUSUN OLEH: NAMA : Dr. Ir. OSWAR MUADZIN MUNGKASA, MURP NDH : 43 KELAS : B INSTANSI : KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA PROGRAM DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT II ANGKATAN XXX JAKARTA MEI 2011
- 2. LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA PUSDIKLAT SPIMNAS BIDANG KEPEMIMPINAN PROGRAM DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT II PENGESAHAN KARYA TULIS PRESTASI PERORANGAN (KTP-2) JUDUL PENINGKATAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT MELALUI PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENGETAHUAN DI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DALAM UPAYA OPTIMALISASI KESEJAHTERAAN RAKYAT DISUSUN OLEH: NAMA : OSWAR MUADZIN MUNGKASA NDH : 43 KELAS : B DISAJIKAN PADA: HARI : KAMIS TANGGAL : 19 MEI 2011 DISAHKAN OLEH: Kapus DIKLAT SPIMNAS Bidang Kepemimpinan Drs. Makhdum Priyatno, MA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA PROGRAM DIKLATPIM TINGKAT II ANGKATAN XXX JAKARTA 2011
- 3. LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA PUSDIKLAT SPIMNAS BIDANG KEPEMIMPINAN PROGRAM DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT II PERSETUJUAN PENYAJIAN KARYA TULIS PRESTASI PERSEORANGAN (KTP-2) JUDUL PENINGKATAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT MELALUI PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENGETAHUAN DI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DALAM UPAYA OPTIMALISASI KESEJAHTERAAN RAKYAT DISUSUN OLEH: NAMA : OSWAR MUADZIN MUNGKASA NDH : 43 KELAS : B DISETUJUI OLEH: Kapus DIKLAT SPIMNAS Bidang Kepemimpinan Drs. Makhdum Priyatno, MA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA PROGRAM DIKLATPIM TINGKAT II ANGKATAN XXX JAKARTA 2011
- 4. kita mengetahui lebih banyak daripada yang bisa kita ceritakan (Michael Polanyi, 1966)
- 5. The study of public policy is very complex topic, and any attempt to force policy into any narrow theoretical frame should be considered with some skepticism (Peters and Pierre, 2006) Pengetahuan menuntun kita ke masa depan dan masa depan menuntun kita untuk mengambil tindakan (August Comte)
- 6. The oldest profession is not prostitution but administration (Kettl, 1996)
- 7. Every solution breeds new problems (Harvey Brightman ,1980)
- 8. Para analisis kebijakan lebih sering gagal karena mereka memecahkan masalah yang salah dibanding karena mereka menemukan solusi yang salah terhadap masalah yang benar (kesalahan tipe III) (Russell L. Ackoff, 1974)
- 9. A great many developing nations are in economic crises today, but not exactly because they are doing the wrong things. Rather, they are doing the right things for times they no longer live in (Michael Fairbanks dan Stacey Lindsay dalam Plowing the Sea, 1997)
- 10. RINGKASAN EKSEKUTIF Tujuan kajian ini adalah mengembangkan manajemen pengetahuan sebagai pengungkit terhadap peningkatan kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Ke- menterian Perumahan Rakyat. Untuk itu, terdapat dua sasaran yang ingin dica- pai, yaitu (i) terformulasikannya strateji pengembangan manajemen pengeta- huan dalam meningkatkan kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Perumahan Rakyat; dan (ii) terformulasikannya rencana tindak/aksi pengem- bangan manajemen pengetahuan dalam meningkatkan kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Perumahan Rakyat; Kondisi pembangunan perumahan di Indonesia masih belum optimal terlihat dari masih besarnya backlog (kekurangan) rumah layak huni yang mencapai jumlah 7,4 juta unit, yang setiap tahun bertambah sebesar 300-400 ribu unit. Ditengarai salah satu faktor penyebabnya adalah belum mantapnya kelemba- gaan penyelenggaraan pembangunan perumahan, yang ditandai oleh masih belum memadainya kualitas produk perencanaan yang dihasilkan oleh Kemen- terian Perumahan Rakyat cq. Biro Perencanaan dan Anggaran, sebagai unit yang diberi tanggungjawab untuk itu. Selanjutnya kualitas produk perencanaan tersebut ditentukan oleh kualitas proses perencanaan. Salah satu faktor yang menentukan kualitas dari proses perencanaan adalah ketersediaan data dan informasi. Berdasarkan pengalaman keseharian pelaksanaan tugas di Biro Perencanaan dan Anggaran, dapat disim- pulkan bahwa ketersediaan data dan informasi masih jauh dari memadai, yang ditandai dari (i) tidak tersedianya standar, operasi dan prosedur penyediaan data dan informasi; (ii) tidak tersedianya pangkalan data yang memadai; (iii) tidak tersedianya staf yang mempunyai kompetensi pendataan; dan (iv) belum ber- kembangnya manajemen pengetahuan. Fokus pada pengembangan manajemen pengetahuan (dan tidak berhenti hanya pada data dan informasi) sebagai sebuah isu didasari pada pemahaman bahwa data dan informasi akan menjadi lebih optimal dan mempunyai daya
- 11. ungkit bagi peningkatan kualitas perencanaan ketika data dan informasi dapat ditransformasikan menjadi sebuah pengetahuan. Hasil transformasi ini kemudian menjadikan data dan informasi tersebut menjadi sebuah kekuatan bagi masing- masing staf Biro Perencanaan dan Anggaran dalam keterlibatannya pada proses penyusunan produk perencanaan. Bertitiktolak dari deskripsi masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, rumusan masalah adalah ”bagaimana pengembangan manajemen pengetahuan dapat meningkatkan kualitas produk perencanaan yang berujung pada pening- katan kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Perumahan Rakyat”. Pendekatan yang dipergunakan adalah pengembangan perencanaan stra- tejik yang meliputi pengembangan visi, misi, tujuan, sasaran dan strateji. Untuk itu, dalam kajian ini dipergunakan 2 (dua) alat analisis yang merupakan alat ana- lisis linier, yaitu (i) SWOT sebagai alat analisis untuk menghasilkan tujuan stra- tegis; (ii) Balanced Scorecard sebagai alat untuk menghasilkan strateji yang di- tindaklanjuti dengan rencana tindak/aksi. Visi dan misi Biro Perencanaan dan Anggaran (BPA) Kementerian Perumah- an Rakyat adalah “Terwujud sistem perencanaan dan penganggaran yang akun- tabel dan didukung data dan informasi yang akurat”. Sementara misinya adalah (i) meningkatkan kualitas sistem perencanaan yang berkesinambungan; (ii) me- ningkatkan kualitas sistem penganggaran berbasis kinerja; (iii) meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang akurat. Berdasar analisis menggunakan SWOT dihasilkan 2 (dua) tujuan yaitu (a) mengembangkan manajemen pengetahuan melalui kemitraan dengan ITB dalam rangka meningkatkan kualitas sistem perencanaan; (b) meningkatkan kualitas data dan informasi melalui kemitraan dengan BPS. Pada akhirnya dengan mem- pertimbangkan kebutuhan pengembangan manajemen pengetahuan, dipilih tuju- an (a). Berdasar pada pilihan tujuan (a) tersebut di atas, sasaran stratejik adalah (i) perspektif pelanggan yaitu tersedianya manajemen pengetahuan, (ii) pers- pektif proses internal yaitu mengembangkan manajemen pengetahuan (cetak
- 12. biru, peta jalan, dan SOP), menginisiasi dan mengembangkan jejaring data dan informasi, dan mengembangkan sarana dan prasarana TIK berbasis manajemen pengetahuan; (iii) perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yaitu melakukan pelatihan teknologi informasi dan komunikasi, melakukan pelatihan dan sosial- isasi manajemen pengetahuan, melakukan pelatihan pola kemitraan dan CSR, (iv) perspektif keuangan yaitu menyediakan dana APBN, dan mencari dana hi- bah/kemitraan/CSR. Untuk mengukur pencapaian sasaran stratejik tersebut, ditetapkan suatu tolok ukur kinerja, yang terdiri dari indikator kinerja utama (IKU) dan target ki- nerja. Indikator kinerja utama adalah (i) dana APBN yang terserap, (ii) terbitnya Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat terkait pengembangan manajemen pengetahuan di lingkup Kemenpera, (iii) tersedianya pangkalan data on-line ber- basis manajemen pengetahuan, (iv) jumlah pelatihan, (v) terlaksananya perte- muan koordinasi jejaring data dan informasi, (vi) dana APBN dan dana hibah/ke- mitraan/CSR yang tersedia. Sebagai kelanjutan dari penetapan sasaran stratejik dan tolok ukurnya, be- berapa inisiatif stratejik yang akan dilaksanakan adalah (i) pengembangan sistem pemantauan pelaksanaan manajemen pengetahuan, (ii) peluncuran permenpera tentang pengembangan manajemen pengetahuan di lingkungan Kemenpera, (iii) pengembangan sarana dan prasarana TIK berbasis manajemen pengetahuan; (iv) pembentukan jejaring data dan informasi, (v) serangkaian pelatihan TIK, pe- latihan manajemen pengetahuan, dan pelatihan pola kemitraan dan CSR; (v) penyusunan proposal pendanaan. Beberapa rekomendasi terkait hasil kajian ini adalah (i) manajemen pengetahuan merupakan konsep yang relatif belum banyak di- kenal di Indonesia termasuk juga di Kementerian Perumahan Rakyat. Un- tuk itu, dibutuhkan bantuan teknis atau kerjasama dengan pihak yang mempunyai pengalaman dan kapabilitas mengembangkan manajemen pe- ngetahuan. Dalam kaitan ini, kerjasama dengan perguruan tinggi menjadi salah satu pilihan. Rintisan kerjasama dengan ITB (saat ini dalam proses)
- 13. dapat ditindaklanjuti dengan perguruan tinggi lainnya yang berasal dari wi- layah yang berbeda; (ii) pengetahuan berasal dari pengembangan data dan informasi, sehingga ke- tersediaan data dan informasi yang akurat menjadi suatu keniscayaan. Ter- kait hal ini, data dan informasi dapat dikategorikan ke dalam dua kategori utama yaitu data statistik, dan data teknis. Khusus ketersediaan data dan informasi statistik, kemitraan dengan BPS Pusat maupun BPS daerah men- jadi suatu keniscayaan. Pola kemitraan ini dapat berupa kerjasama antara Kemenpera dengan BPS Pusat, maupun kerjasama pemda dengan BPS daerah, ataupun kerjasama antara pemda dengan BPS daerah yang difa- silitasi bersama oleh Kemenpera dan BPS Pusat. Sementara kerjasama de- ngan mitra non pemerintah dapat dilakukan melalui forum jejaring data dan informasi; (iii) pengembangan manajemen pengetahuan pada organisasi publik, berdasar catatan yang ada, belum pernah dilakukan di Indonesia, kecuali pada or- ganisasi semi publik seperti BUMN (PLN), BUMD (PDAM). Untuk itu, kunjungan atau studi banding ke institusi tersebut layak dipertimbangkan; (iv) pengembangan manajemen pengetahuan tidak terlepas dari kendala ko- mitmen pimpinan dan karyawan. Pada kasus Kemenpera, komitmen pim- pinan tinggi namun belum diketahui sejauh mana komitmen dari karyawan. Untuk itu, kegiatan advokasi dan sosialisasi menjadi suatu keniscayaan; (v) komitmen pimpinan dan karyawan saja tidak akan memadai untuk me- ngembangkan manajemen pengetahuan. Dibutuhkan suatu panduan yang jelas. Walaupun pengembangan manajemen pengetahuan ini dimaksudkan sebagai upaya internal BPA Kemenpera tetapi pengembangan manajemen ini sebaiknya berlaku untuk seluruh Kemenpera. Untuk itu dibutuhkan se- gera suatu cetak biru, peta jalan, dan standar operasi dan prosedur (SOP) pengembangan manajemen pengetahuan Kemenpera. Keseluruhan pan- duan, petunjuk dan konsep manajemen pengetahuan sebaiknya terinter-
- 14. nalisasi dalam rencana strategis Kemenpera, sehingga rencana tindaknya dapat dialokasikan anggarannya; (vi) pengetahuan bersifat terbuka sehingga tidak dapat dibatasi hanya di ling- kup kemenpera. Menjadi suatu ide yang baik jika terdapat suatu jejaring data dan informasi (pengetahuan) perumahan dan kawasan permukiman yang akan membantu optimalisasi pemanfaatan pengetahuan yang ada. Jejaring ini merupakan forum pemangku kepentingan perumahan yang terdiri dari berbagai pihak baik pemerintah maupun non pemerintah. Perlu disadari bahwa keberadaan data, informasi, dan pengetahuan di luar Kemenpera bahkan mungkin jauh lebih banyak dan kompleks yang kebe- radaannya dapat membantu pemerintah dalam penyusunan kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
- 15. PENGANTAR Pertama-tama saya ucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, karena dengan perkenanNya Karya Tulis Prestasi Perorangan (KTP-2) yang ber- judul ”Peningkatan Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Peru- mahan Rakyat melalui Pengembangan Manajemen Pengetahuan di Bidang Peru- mahan dan Kawasan Permukiman dalam Upaya Optimalisasi Kesejahteraan Rak- yat” dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Inspirasi tulisan ini berasal dari pengalaman keseharian penulis selama bekerja di Biro Perencanaan dan Anggaran (BPA) Kementerian Perumahan Rak- yat. Isu yang mengemuka selama ini adalah terkait masih belum memadainya kualitas produk perencanaan yang dihasilkan oleh unit BPA. Ditengarai terdapat beberapa faktor penyebab dari timbulnya isu ini, diantaranya kondisi sumber da- ya manusia baik kuantitas maupun kualitas, belum tersedianya standar operasi dan prosedur (SOP), serta ketersediaan data dan informasi. Terkait faktor keter- sediaan data dan informasi ini, kemudian dipandang perlu mengembangkannya menjadi pengetahuan yang dikelola melalui konsep manajemen pengetahuan yang memungkinkan data, informasi dan pengetahuan lebih berdaya guna dalam proses perencanaan. Untuk itu, hasil dari KTP-2 ini diharapkan dapat memberi masukan bagi penanganan isu belum memadainya kualitas produk perencanaan di BPA Kemenpera sehingga terwujud peningkatan kinerja BPA Kemenpera. KTP-2 merupakan aktualisasi dari pembelajaran Diklatpim Tingkat II Ang- katan XXX Tahun 2011 dengan tema ”Akselerasi Sinergi Instansi Pemerintah da- lam Pembangunan Berkeadilan”. KTP-2 diharapkan dapat menjadi media imple- mentasi hasil pembelajaran Diklatpim Tingkat II. Untuk itu, alat analisis yang dipergunakan merupakan hasil pembelajaran selama ini.
- 16. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak hal yang perlu disempurnakan dalam KTP-2 ini. Walaupun demikian, penulis menyampaikan terima kasih atas bantuan berbagai pihak sehingga KTP-2 ini terselesaikan. Per- tama-tama ucapan terima kasih penulis sampaikan pada Bapak Dargono Danoe Prawiro selaku Widyaiswara Pembimbing KTP-2 atas bimbingan dan masukannya terhadap rancangan KTP-2 ini. Tidak terlupakan juga terima kasih atas bimbing- an para Widyaswara dalam sesi Kajian Paradigma, Kajian Kebijakan Publik, Kaji- an Manajemen Stratejik, dan Kertas Kerja Tematik (KKT), yang pada intinya te- lah membantu meningkatkan pemahaman penulis terhadap berbagai hal sehing- ga tulisan ini terwujud. Selain itu, fasilitasi pihak penyelenggara, terlepas dari ke- kurangan yang ada, tentunya patut diberi apresiasi pula pada kesempatan ini. Akhirnya, terima kasih juga atas dorongan dan keleluasaan yang diberikan oleh atasan dan keluarga penulis. Jakarta, Mei 2011 Oswar Mungkasa
- 17. LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA PUSAT DIKLAT SPIMNAS BIDANG KEPEMIMPINAN PAKTA INTEGRITAS Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Karya Tulis Prestasi Perseorangan (KTP-2) saya susun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Diklatpim Tingkat II yang seluruhnya merupakan hasil karya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan KTP-2 yang saya kutip secara langsung atau tidak langsung dari hasil karya orang lain telah saya tuliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah. Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian KTP-2 ini bukan karya tulis sendiri, atau ada indikasi adanya plagiat di bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pakta integritas ini dibuat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari siapapun. Pakta integritas ini digunakan seperlunya. Jakarta, 18 Mei 2011 Oswar Muadzin Mungkasa NDH 43
- 18. DAFTAR ISTILAH Visi keadaan organisasi yang diinginkan untuk terwujud di masa depan Misi alasan keberadaan suatu organisasi. Ketika misi terlaksana maka suatu organisasi menjadi dihargai keberaqdaannya Nilai prinsip yang menjadi dasar bertindak bagi semua orang di dalam organisasi Tujuan pernyataan secara formal dan luas tentang apa yang akan dicapai di masa depan Sasaran pernyataan yang lebih konkrit dan fokus tentang tujuan yang hendak dicapai, dilengkapi dimensi waktu dan target populasi. Kriteria pernyataan khusus tentang dimensi sasaran yang akan digunakan untuk untuk mengevaluasi alternatif kebijakan atau program. Ukuran kriteria definisi yang operasional dan tampak yang seringkali berbentuk kuantitatif. Kebijakan keputusan yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintahan atau organisasi dan bersifat mengikat pada pihak yang terkait dengan lembaga tersebut Publik hal ihwal yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak Kebijakan publik keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga peme- rintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak. Formulasi kebijakan suatu kegiatan yang bertujuan merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan publik tertentu Implementasi kebijakan suatu kegiatan atau proses pelaksanaan atau penerapan kebijakan publik yang telah ditetapkan Evaluasi kinerja kebijakan suatu kegiatan atau proses yang mencakup penilaian suatu kebijakan publik yang telah berjalan dalam kurun waktu tertentu, yang mencakup evaluasi pada kinerja formulasi kebijakan, kinerja implementasi kebijakan, kinerja manfaat yang dirasakan publik.
- 19. Revisi kebijakan publik suatu kegiatan atau proses perbaikan suatu kebijakan publik tertentu, baik karena kebutuhan publik, maupun antisipasi kondisi di masa depan. Strategi kombinasi kegiatan yang dilaksanakan secara terpisah sebagai upaya memenuhi kebutuhan pelanggan Manajemen stratejik seni dan ilmu dalam memformulasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan keputusan dalam suatu organisasi yang bersifat lintas fungsi seperti pemasaran, keuangan, produksi, riset dan pengembangan, sistem informasi, dan sebagainya untuk menunjang pencapaian tujuan organisasi. Sasaran stratejik sebuah pernyataan yang terpadu yang menjelaskan hal yang harus dilakukan oleh organisasi dalam kerangka pelaksanaan strategi Peta stratejik sebuah grafik yang menggambarkan keterkaitan dari seluruh sasaran obyektif, dalam bentuk hubungan sebab akibat. Inisiatif kegiatan tertentu yang harus dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran stratejik. Kekuatan situasi dan kemampuan internal yang bersifat positip yang me- mungkinkan organisasi memenuhi keuntungan stratejik dalam mencapai visi dan misi Kelemahan situasi dan faktor-faktor dalam organisasi yang bersifat negatif, yang menghambat organisasi mencapai atau mampu melampaui pencapaian misi dan visi Peluang situasi dan faktor luar organisasi yang bersifat positip, yang membantu organisasi mencapai atau mampu melampaui pencapaian visi dan misi Tantangan/ancaman faktor luar organisasi yang bersifat negatif yang dapat meng- akibatkan organisasi gagal mencapai visi dan misinya. Data fakta tentang suatu kejadian Informasi data yang membuat sebuah pembedaan Pengetahuan campuran dari pengalaman, nilai, informasi kontekstual, dan pandangan ahli yang memberikan kerangka bagi evaluasi dan penyatuan pengalaman baru dan informasi Manajemen pengetahuan suatu rangkaian kegiatan yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan,
- 20. dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui, dan dipelajari di dalam organisasi.
- 21. DAFTAR SINGKATAN BSC Balanced Scorecard BPA Biro Perencanaan dan Anggaran BPS Biro Pusat Statistik FAA Federal Aviation Administration FKK Faktor Kunci Keberhasilan HAM Hak Asasi Manusia IKU Indikator Kriteria Utama ITB Institut Teknologi Bandung KAFE Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal KAFI Kesimpulan Analisis Faktor Internal Kemenpera Kementerian Perumahan Rakyat LAKIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah MDGs Millenium Development Goals MenegPAN Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara MOU Memorandum of Understanding PKP Perumahan dan Kawasan Permukiman PLE Pencermatan Lingkungan Eksternal PLI Pencermatan Lingkungan Internal Renstra Rencana Strategis RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional SDM Sumber Daya Manusia SMART Specific, Measurable, Agreed, Realistic, Time bound. SO Strengths Opportunities SOP Standar Operasi dan Prosedur ST Strengths Threats SWOT Strengths Weakneses Opportunities Threats TIK Teknologi Informasi dan Komunikasi UU Undang-Undang UUD Undang-Undang Dasar WO Weakneses Opportunities WT Weakneses Threats
- 22. DAFTAR ISI Halaman Ringkasan Eksekutif ............................................................................. i Kata Pengantar ................................................................................... vi Pakta Integritas ................................................................................... viii Daftar Istilah ....................................................................................... ix Daftar Singkatan .................................................................................. xi Daftar Isi ............................................................................................ xiii Daftar Tabel ........................................................................................ xv Daftar Gambar .................................................................................... xvi BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ................................................................ 1 B. Deskripsi Masalah ............................................................ 5 C. Rumusan Masalah ............................................................ 6 D. Tujuan dan Sasaran Penulisan .......................................... 6 1. Tujuan ....................................................................... 6 2. Sasaran ..................................................................... 6 3. Indikator Hasil ........................................................... 6 BAB II KERANGKA KONSEPTUAL A. Kebijakan Publik .............................................................. 8 1. Pemahaman Umum .................................................... 8 2. Prinsip Penyusunan Kebijakan Publik ............................ 9 3. Siklus Kebijakan Publik ................................................ 9 4. Analisis Kebijakan Publik ............................................. 11 B. Manajemen Stratejik ........................................................ 14 1. Pemahaman Umum .................................................... 14 2. Tujuan dan Sasaran..................................................... 15 3. Aspek Penting ............................................................ 15 4. Manajemen Stratejik pada Organisasi Publik ................. 19 C. Manajemen Pengetahuan ................................................. 20 1. Pemahaman Data, Informasi dan Pengetahuan ............. 20 2. Jenis Pengetahuan ....................................................... 22 3. Pentingnya Pengetahuan .............................................. 23
- 23. Halaman 4. Pemahaman Manajemen Pengetahuan ......................... 23 5. Tahapan dan Kegiatan Manajemen Pengetahuan .......... 24 6. Strategi Mengelola Pengetahuan .................................. 26 7. Strategi Penerapan Manajemen Pengetahuan .............. 27 8. Langkah Stratejik Penerapan Manajemen Pengetahuan 28 9. Penerapan pada Organisasi Publik .............................. 30 BAB III INSTRUMEN ANALISIS A. Pemilihan Alat Analisis .................................................... 33 B. SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) ... 34 C. Balanced Scorecard (BSC).............................................. 36 1. Pengertian ............................................................... 36 2. Perkembangan BSC .................................................. 38 3. Tahapan .................................................................. 38 4. BSC pada Ranah Publik ............................................. 41 BAB IV ANALISIS A. Tahapan Analisis ........................................................... 43 B. Formulasi Strateji............................................................ 45 1. Perumusan Visi, Misi dan Nilai-Nilai ............................ 45 2. Pencermatan Lingkungan Stratejik ............................. 47 3. Asumsi Strategis ....................................................... 49 4. Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) ................................ 52 5. Penetapan Tujuan ..................................................... 54 C. Formulasi Implementasi Strateji....................................... 55 1. Sasaran Stratejik ...................................................... 55 2. Tolok Ukur Kinerja .................................................... 56 BAB V REKOMENDASI DAN RENCANA AKSI A. Rekomendasi ................................................................ 59 B. Rencana Aksi ................................................................ 61 BAB VI PENUTUP .......................................................................... 64 DAFTAR PUSTAKA ............................................................................ 66 LAMPIRAN A. TOR KTP-2 ............................................................................ 69 B. Lembar Konsultasi KTP-2 ........................................................ 77
- 24. DAFTAR TABEL Halaman Tabel II.1 Evaluasi Kebijakan ....................................................... 14 Tabel IV.1 Daftar Periksa Pernyataan Visi ...................................... 46 Tabel IV.2 Daftar Periksa Pernyataan Misi ...................................... 47 Tabel IV.3 Matriks Identifikasi Lingkungan Stratejik ........................ 48 Tabel IV.4 Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI) ..................... 50 Tabel IV.5 Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KAFE) .................. 51 Tabel IV.6 Asumsi Stratejik (Analisis TOWS/KAFI vs KAFE) ............ 52 Tabel IV.7 Urutan Asumsi Stratejik ............................................... 53 Tabel IV.8 Tujuan Stratejik .......................................................... 54 Tabel IV.9 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran ........................ 58 Tabel V.1 Rencana Aksi/Tindak .................................................. 61 Tabel V.2 Penyusunan Rencana Aksi Berdasarkan Kriteria SMART.. 62 Tabel V.3 Jadwal Pelaksanaan Rencana Aksi ................................ 63
- 25. DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 2.1 Kuadran Kebijakan Publik ................................................... 8 Gambar 2.2 Proses Kebijakan Secara Umum .......................................... 10 Gambar 2.3 Proses Kebijakan Publik ...................................................... 11 Gambar 2.4 Mode Konversi Pengetahuan ............................................... 22 Gambar 3.1 Empat Perspektif Balance Scorecard .................................... 37 Gambar 4.1 Tahapan Analisis ............................................................... 44 Gambar 4.2 Peta Strategi Biro Perencanaan dan Anggaran ...................... 57
- 26. BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Hunian yang layak merupakan merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang pemenuhannya diamanatkan dalam Amandemen Undang‐Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat 1, dan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 40, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pasal 109. Sementara pada skala global, penyediaan perumahan dan permukiman yang memenuhi prinsip layak dan terjangkau bagi semua orang juga menjadi ko- mitmen global sebagaimana dituangkan dalam Agenda Habitat (The Habitat Agenda, Istanbul Declaration on Human Settlements) dan Tujuan Pemba- ngunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs). Selain sebagai hak asasi, perumahan dan permukiman juga terkait lang- sung dengan upaya peningkatan kualitas keluarga yang pada akhirnya diha- rapkan mampu memberikan kontribusi dalam pembangunan komunitas dan memperkokoh kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai konsekuensi logis, pemerintah wajib menghormati, melin- dungi, menegakkan, dan memajukan perumahan dengan menciptakan iklim yang kondusif bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya bagi masyarakat ber- penghasilan rendah secara berkelanjutan. Tujuan ini selaras dengan amanat pembukaan UUD 1945 dan telah ditetapkan sebagai bagian dari sasaran pemba- ngunan nasional sebagaimana tercantum dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005‐2025 (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005‐ 2025).
- 27. Walaupun hunian merupakan hak asasi dan kebutuhan dasar manusia, dan pembangunan perumahan telah menjadi bagian penting dari target pem- bangunan di Indionesia sejak awal kemerdekaan, namun hasilnya masih belum seperti yang diharapkan. Sampai saat ini, masih terdapat sejumlah sekitar 7,4 juta rumah tangga yang belum menempati hunian yang layak. Jumlah ini me- ningkat dari sebelumnya yaitu sejumlah 5,8 juta unit pada tahun 2004 (RPJMN 2010-2014). Selain itu, masih terdapat sekitar 4,8 juta unit rumah yang diperki- rakan menurun kualitasnya dan cenderung rusak. Sementara itu, permukiman kumuh pun semakin meluas yang diperkirakan telah mencapai 57.800 ha (Renstra Kemenpera 2010-2014). Secara garis besar, permasalahan yang ha- rus dihadapi tersebut kemudian dapat dikelompokkan menjadi tiga perma- salahan pokok, yaitu: (i) keterbatasan penyediaan rumah; (ii) meningkatnya jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni dan tidak di- dukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai; serta (iii) permukiman kumuh yang semakin meluas. Beragam faktor yang menjadi penyebab permasalahan tersebut, yai- tu: (i) regulasi dan kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung terciptanya iklim yang kondusif dalam pembangunan perumahan dan permukiman; (ii) keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan menengah‐bawah terha- dap lahan; (iii) lemahnya kepastian bermukim (secure tenure); (iv) Belum tersedia dana murah jangka panjang untuk meningkatkan akses dan daya beli masyarakat berpenghasilan menengah‐bawah; (v) belum efisiennya pa- sar primer dan belum berkembangnya pasar sekunder perumahan; (vi) be- lum mantapnya kelembagaan penyelenggaraan pembangunan peru-mahan dan permukiman; dan (vii) belum optimalnya pemanfaatan sumber daya perumahan dan permukiman. Faktor penyebab terkait belum mantapnya kelembagaan diterjemahkan sebagai masih belum optimalnya kinerja kementerian sehingga kualitas proses perencanaan yang meliputi penyusunan rencana, pelaksanaan, pemantauan dan
- 28. evaluasi masih belum optimal. Hal ini ditengarai disebabkan oleh dukungan data dan informasi yang masih belum memadai. Dalam Kabinet Indonesia Bersatu II, Kementerian Perumahan Rakyat mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Or- ganisasi dan Tata Kerja Kementerian Republik Indonesia, yaitu membantu Presiden Republik Indonesia dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat. Kemudian terkait dengan isu data dan informasi, didalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Peru- mahan Rakyat ditetapkan bahwa Biro Perencanaan dan Anggaran yang diberi tanggungjawab melaksanakan pengolahan data (pasal 9). Hal ini kemudian tercermin dalam visi Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2010-2014 yang dirumuskan sebagai berikut “Terwujudnya sistem perencanaan dan pengang- garan Kementerian Perumahan Rakyat yang akuntabel dan didukung data dan informasi yang akurat” Namun demikian, keberadaan data dan informasi akan lebih optimal jika kemudian dapat ditingkatkan menjadi pengetahuan. Ketika data ditransformasi menjadi informasi, yang kemudian oleh masing-masing individu melalui proses internalisasi berubah menjadi pengetahuan. Keberadaan pengetahuan ini yang kemudian perlu dikelola. Upaya mengelola pengetahuan ini yang dikenal sebagai manajemen pengetahuan. Tidak terdapat satu definisi yang disepakati oleh para ahli terkait manajemen pengetahuan, namun Frappaolo (2006) meringkas ber- bagai konsep dan praktik manajemen pengetahuan dalam suatu pernyataan sebagai berikut knowledge management is the leveraging collective wisdom to increase responsiveness and inovation (Manajemen pengetahuan adalah pe- ngungkitan kearifan kolektif untuk meningkatkan daya tanggap dan inovasi) (Kuswartojo, 2011). Manajemen pengetahuan juga dikembangkan untuk sektor publik atau pe- nyelenggaraan pemerintahan. Adopsi manajemen pengetahuan dalam pemerin-
- 29. tahan sipil dianggap lambat. Ada yang berpendapat hal ini disebabkan karena pada umumnya pemerintah tidak menyukai pengetahuan dan perubahan. Pen- dapat ini tentu saja tidak sepenuhnya benar. Pengetahuan merupakan suatu modal nirwujud yang dapat terus dikembangkan, yang tidak akan habis, tidak akan hilang dicuri atau dialihkan. Pengetahuan akan dapat mendorong inovasi dan meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Kesulitan pemerintah dalam mengadopsi manajemen pengetahuan antara lain tidak terlalu mudah untuk mendeliniasi dan mengisolasi suatu satuan organ- isasi. Pemerintah merupakan organisasi dengan jejaring yang sangat luas, yang geraknya dikerangkakan dalam suatu peraturan perundangan. Sehingga bagai- manapun inovasi dan efektifivitas yang menjadi maksud dikembangkannya ma- najemen pengetahuan suatu organisasi pemerintah, juga akan ditentukan oleh keterkaitannya dengan aneka organisasi pemerintah yang lain. Untuk menghindari hambatan oleh adanya saling keterkaitan tersebut, diciptakanlah suatu aturan dan kerangka kerja yang di satu sisi memang dapat mencegah kondisi kaostik (ketidakteraturan) tetapi disisi lain sering menghambat inovasi dan efektifitas gerak. Dinding penyekat berupa tugas pokok dan fungsi sering menjadi penghalang kreativitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di manapun di dunia. Pembahasan manajemen pengetahuan pada umumnya ditujukan untuk kepentingan suatu organisasi usaha, tentara atau pemerintah. Manajemen pe- ngetahuan ditempatkan sebagai elemen dan instrumen organisasi untuk men- dorong inovasi, meningkatkan kreativitas, meningkatkan kapasitas dan efek- tifitas gerak, produk dan aktivitas organisasi. Artinya manajemen memang ditu- jukan untuk kepentingan internal organisasi. Walaupun sesungguhnya juga da- pat ditemukan manajemen pengetahuan untuk tujuan yang lebih luas. Memahami semua tantangan, kendala, peluang yang dihadapi Kemente- rian Perumahan Rakyat dalam pelaksanaan tugas-tugas pokoknya, ditengarai perlunya untuk fokus pada peningkatan kinerja kelembagaan yang berujung pa- da peningkatan kualitas proses perencanaan. Proses perencanaan hanya dapat
- 30. dioptimalkan ketika data, dan informasi yang tersedia secara memadai. Terkait hal itu, mengemuka isu pengembangan manajemen pengetahuan di Biro Peren- canaan dan Anggaran Kemenpera. Manajemen pengetahuan akan menjadi daya ungkit bagi peningkatan kualitas proses perencanaan yang bermuara pada peningkatan kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenpera. B. Deskripsi Masalah Kondisi pembangunan perumahan di Indonesia masih belum optimal terlihat dari masih besarnya backlog (kekurangan) rumah layak huni yang mencapai jumlah 7,4 juta unit, yang setiap tahun bertambah sebesar 300-400 ribu unit. Ditengarai salah satu faktor penyebabnya adalah belum mantapnya kelemba- gaan penyelenggaraan pembangunan perumahan, yang ditandai oleh masih belum memadainya kualitas produk perencanaan yang dihasilkan oleh Kemen- terian Perumahan Rakyat cq. Biro Perencanaan dan Anggaran, sebagai lembaga yang diberi tanggungjawab untuk itu. Selanjutnya kualitas produk perencanaan tersebut ditentukan oleh kualitas proses perencanaan. Salah satu faktor yang menentukan kualitas dari proses perencanaan adalah ketersediaan data dan informasi. Berdasarkan pengalaman keseharian pelaksanaan tugas di Biro Perencanaan dan Anggaran, dapat disim- pulkan bahwa ketersediaan data dan informasi masih jauh dari memadai, yang ditandai dari (i) tidak tersedianya standar, operasi dan prosedur penyediaan data dan informasi; (ii) tidak tersedianya pangkalan data yang memadai; (iii) belum memadainya kuantitas dan kualitas staf yang mempunyai kompetensi pendata- an; dan (iv) belum berkembangnya manajemen pengetahuan. Fokus pada pengembangan manajemen pengetahuan (yang tidak berhenti hanya pada data dan informasi) sebagai sebuah isu, didasari pada pemahaman bahwa data dan informasi akan menjadi lebih optimal dan mempunyai daya ung- kit bagi peningkatan kualitas perencanaan ketika data dan informasi dapat di- transformasikan menjadi sebuah pengetahuan. Hasil transformasi ini kemudian menjadikan data dan informasi tersebut sebuah kekuatan bagi masing-masing
- 31. staf Biro Perencanaan dan Anggaran dalam keterlibatannya pada proses penyu- sunan produk perencanaan. C. Rumusan Masalah Bertitiktolak dari deskripsi masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, rumusan masalah adalah ”bagaimana pengembangan manajemen pengetahuan dapat meningkatkan kualitas produk perencanaan yang berujung pada pening- katan kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Perumahan Rakyat”. D. Tujuan dan Sasaran Penulisan 1. Tujuan Tujuan penulisan ini adalah pengembangan manajemen pengetahuan se- bagai pengungkit terhadap peningkatan kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Perumahan Rakyat. 2. Sasaran Terdapat dua sasaran yang ingin dicapai sebagai hasil kajian ini dalam meningkatkan kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Perumahan Rakyat, yaitu: a. Terformulasikannya strateji pengembangan manajemen pengetahuan; b. Terformulasikannya rencana tindak/aksi pengembangan manajemen pe- ngetahuan; 3. Indikator Hasil Yang Diharapkan Beberapa indikator hasil yang diharapkan adalah: a. Terlembagakannya manajemen pengetahuan yang mampu mening- katkan kualitas produk perencanaan pada Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Perumahan Rakyat; b. Tersedianya standar operasional dan prosedur (SOP) penyelengga- raan manajemen pengetahuan
- 32. c. Tersedianya dan meningkatnya kompetensi sumber daya manusia perencana perumahan dan kawasan permukiman khususnya terkait manajemen pengetahuan; d. Meningkatnya kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Perumahan Rakyat.
- 33. BAB II KERANGKA KONSEPTUAL A. Kebijakan Publik Pembahasan kebijakan publik akan terfokus pada pemahaman umum, prinsip, siklus dan analisis kebijakan publik. 1. Pemahaman Umum Thomas Birkland dalam An Introduction to the Policy Process (2001) me- ngemukakan bahwa terdapat ketidaksepakatan tentang definisi kebijakan publik. Namun demikian, Thomas R. Dye (1995) mengajukan definisi seder- hana bahwa kebijakan publik diartikan sebagai hal yang diputuskan pemerin- tah untuk dikerjakan dan hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak diker- jakan atau dibiarkan. Sebagian pihak menyatakan kebijakan publik sebagai kebijakan dalam bentuk peraturan perundangan dan peraturan tidak tertulis namun disepakati yang disebut konvensi. Sementara Riant Nugroho men- definisikan sebagai setiap keputusan yang dibuat oleh negara, sebagai stra- tegi untuk merealisasikan tujuan dari negara (Nugroho, 2011). Gambar 2.1 Kuadran Kebijakan Publik Lingkup isu/masalah Pribadi dan/atau golongan Masyarakat/bersama masyarakat Organisasi KUADRAN I KUADRAN II Penanggungjawab Perekrutan pegawai Gotong royong perusahaan pertama Organisasi publik KUADRAN III KUADRAN IV Pengadilan kejahatan Kebijakan publik Sumber: Nugroho, 2011.
- 34. Untuk melengkapi definisi di atas, terdapat ciri dari kebijakan publik yaitu (i) kebijakan dibuat oleh organisasi publik, (ii) mengatur kehidupan bersama, dan bukan mengatur kehidupan pribadi; (iii) manfaat yang diperoleh masyarakat yang bukan pengguna langsung produk yang dihasilkan jauh lebih banyak atau lebih besar dari pengguna langsungnya. 2. Prinsip Penyusunan Kebijakan Publik Prinsip penyusunan kebijakan publik sesuai yang tercantum dalam PermenPAN Nomor: PER/04/M.PAN/4/2007 tanggal 16 April 2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebi- jakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah adalah (i) benar dalam proses, yaitu prosesnya harus transparan, dapat dipertang- gungjawabkan dan melibatkan pihak terkait; (ii) benar secara isi, yaitu bah- wa isi kebijakan (a) fokus pada isu kebijakan; (b) bukan merupakan kom- promi politik atau ekonomi; (c) langsung pada masalah yang diatur; (d) tidak saling bertentangan dengan kebijakan yang lebih tinggi atau setara; (iii) benar secara politik-etik, yaitu menerapkan prinsip kepemerintahan yang ba- ik; (iv) benar secara hukum, yaitu merupakan kaidah hukum, memberikan aturan secara tegas dan sanksinya; (v) benar secara manajemen, yaitu isi kebijakan sistematis, dapat dilaksanakan, dan dampaknya terukur; (vi) benar secara bahasa, yaitu dipahami publik dalam satu makna, dan tidak terdapat penyimpangan logika bahasa. 3. Siklus Kebijakan Publik Secara sederhana, terdapat 4 (empat) tahapan utama dari siklus kebi- jakan publik, yaitu (i) isu kebijakan, (ii) perumusan kebijakan; (iii) imple- mentasi kebijakan; (iv) evaluasi kebijakan. (i) Isu kebijakan. Penyebutan isu ketika suatu gejala/kondisi bersifat strategis, yang menyangkut orang banyak, dan berjangka panjang. Isu kebijakan terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu masalah dan tujuan. Ke-
- 35. bijakan publik dapat berorientasi masalah pada kehidupan publik, atau tujuan yang hendak dicapai pada kehidupan publik. (ii) Perumusan kebijakan. Keberadaan isu menggerakkan pemerintah merumuskan kebijakan publik sebagai upaya menyelesaikan masa- lah. (iii) Pelaksanaan kebijakan publik. Kebijakan publik dilaksanakan oleh pe- merintah maupun bersama-sama dengan masyarakat. (iv) Evaluasi kebijakan. Langkah evaluasi dilakukan untuk menilai apa- kah kebijakan telah dirumuskan dan diimplementasikan dengan baik (Nugroho, 2011) Evaluasi kebijakan Monitoring kebijakan isu perumusan Implementasi kinerja pelanjutan kebijakan kebijakan kebijakan kebijakan kebijakan revisi kebijakan isu kebijakan (baru) penghentian lingkungan kebijakan kebijakan Sumber: Nugroho, 2011. Gambar 2.2 Proses Kebijakan Secara Umum
- 36. Sementara dalam PermenPAN Nomor: PER/04/M.PAN/4/2007 Tanggal 16 April 2007, ditambahkan satu tahapan yaitu revisi kebijakan, yang dimak- sudkan sebagai upaya menyikapi kedinamisan lingkungan kebijakan. Proses revisi ini merupakan gabungan antara evaluasi dan formulasi kebijakan (Gam- bar 2.3) 4 1 2 3 5 Evaluasi isu perumusan Implementasi kinerja Revisi kebijakan kebijakan kebijakan kebijakan kebijakan Gambar 2.3 Proses Kebijakan Publik (PermenPAN Nomor: PER/04/M.PAN/4/2007 Tanggal 16 April 2007) 4. Analisis Kebijakan Publik Analisis berasal dari bahasa Yunani yang berarti memecah-mecah. Analisis kebijakan adalah kegiatan yang dilakukan sebelum perumusan kebijakan, atau merupakan proses inisiasi perumusan kebijakan, dengan produk berupa rekomendasi kebijakan. Analisis kebijakan berdasar pendekatan model rasionalis mempunyai ba- gian-bagian (i) mendefinisikan permasalahan, (ii) menetapkan kriteria evalu- asi, (iii) mengidentifikasi alternatif kebijakan, (iv) memaparkan alternatif-al- ternatif dan memilih salah satu, dan (v) memantau dan mengevaluasi man- faat kebijakan. Berdasarkan tahapan di atas dapat disimpulkan bahwa analisis kebijakan terdiri atas dua tahap utama yaitu analisis masalah dan analisis solusi. Adapun analisis masalah terdiri dari (i) mendefinisikan masalah yang terdiri dari tahapan (a) menelusuri masalah, (b) framing the problem, (c) memo- delkan masalah yaitu identifikasi variabel kebijakan; (ii) memilih dan men- jelaskan tujuan dan tantangan yang bersesuaian (relevan); (iii) memilih me- tode pemilihan solusi. Sementara analisis solusi terdiri dari tahapan (i) memi- lih kriteria evaluasi; (ii) mengidentifikasi alternatif kebijakan; (iii) mengeva-
- 37. luasi menggunakan kriteria evaluasi dan memilih salah satu; (iv) mereko- mendasikan tindakan. Edi Soeharto (2005) menetapkan masalah kebijakan berdasar 4 (empat) parameter yaitu (i) faktor penentu dalam mengatasi masalah lain yang lebih luas dan dapat diukur; (ii) dampaknya pada masyarakat; (iii) kecenderung- an, yaitu apakah masalah seiring dengan kecenderungan global; (iv) sesuai dengan nilai dan harapan masyarakat (Nugroho, 2011). Menurut Patton dan Savicy, tidak ada formula baku dalam membuat kri- teria evaluasi. Namun demikian, disarankan memerhatikan beberapa hal yaitu kriteria harus jelas, konsisten, mengukur informasi penting, mengungkap ke- unikan, valid, akurat, dapat diperoleh tanpa merugikan privasi dan kerahasi- aan, masuk dalam anggaran biaya dan mampu mengungkap secara lengkap (Nugroho, 2011). Selanjutnya, kriteria alternatif yang baik menurut Patton dan Savicky yang menggunakan kriteria Warren E. Walker adalah (i) Biaya. Apakah ter- jangkau dan efektif?; (ii) stabilitas. Apakah tetap berkesinambungan meski- pun menghadapi guncangan dalam pelaksanaannya; (iii) reliabilitas. Bagai- mana kemungkinan dapat dijalankan pada waktu yang ditetapkan?; (iv) ke- kokohan (invulnerability). Akankah tetap dapat dijalankan ketika salah satu bagian tidak berfungsi?; (v) fleksibilitas. Dapatkan melayani lebih dari satu tu- juan?; (vi) keresikoan (riskiness). Apakah terdapat resiko gagal yang besar?; (vii) dapat dikomunikasikan. Apakah mudah dipahami bagi mereka yang tidak terlibat dalam proses?; (viii) merit. Apakah dapat menyelesaikan masalah?; (ix) kesesuaian. Apakah berkesesuaian dengan norma dan prosedur yang ada?; (x) reversibility. Seberapa sulit kembali ke kondisi awal ketika terjadi kegagalan?; (xi) kesederhanaan. Apakah mudah dilaksanakan?; (xii) robust- ness. Pada tingkatan seperti apa alternatif berhasil di dalam kondisi ling- kungan masa depan yang berbeda?. Alternatif kebijakan yang ada perlu dievaluasi. Langkah ini digunakan untuk memilih kebijakan yang akan diambil, yang disebut ex-ante evaluation.
- 38. Patton dan Savicky (1993) memperkenalkan dua metode menentukan alter- natif kebijakan yaitu peramalan dan evaluasi. Peramalan dilakukan melalui langkah (i) ekstrapolasi, yaitu membuat proyeksi masa depan; (ii) memo- delkan secara teoritis, yaitu peramalan dengan mempergunakan teori terten- tu; (iii) intuitif, atau Dunn menyebutnya sebagai retroductive, yaitu melalui interviu pakar. Implementasi dipandang sebagai bagian dari proses kebijakan, sehingga dipandang perlu melakukan analisis implementasi. Steiss dan Danekee (1980) menyatakan bahwa analisis implementasi dalam analisis kebijakan perlu fokus pada 2 (dua) hal yaitu (i) tingkat kesepakatan diantara aktor pembuat kebi- jakan, pelaksana kebijakan dan target kebijakan; (ii) besarnya perubahan dari alternatif kebijakan yang dipilih. Soren Winter (1990) mengidentifikasi 4 (empat) variabel kunci yang memengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu (i) proses pembentukan kebijakan; (ii) perilaku organisasi pelaku implemen- tasi; (iii) perilaku birokrat di tingkat bawah; (iv) tanggapan kelompok target kebijakan dan perubahan dalam masyarakat. Selain itu, ditambahkan juga analisis ketidakpastian dalam analisis implementasi, berupa informasi tentang perubahan yang mungkin terjadi dan resiko kebijakan (Nugroho, 2011). Impementasi sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri. Kegagalan implementasi dianggap juga sebagai kegagalan kebijakan. Carol H. Weiss (1989) mengelompokkan kegagalan kebijakan menjadi 2 (dua), yaitu (i) ke- gagalan program, yaitu kebijakan tidak dapat diimplementasikan sesuai de- ngan desain; (iii) kegagalan teori, yaitu kebijakan dapat diimplementasikan sesuai desain tetapi tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan. Evalusi kebijakan dilaksanakan secara berkesinambungan, yang dike- lompokkan menjadi 4 (empat) kegiatan yang berurutan yaitu ex-ante, main- tenance, monitoring, dan ex-post. Selengkapnya pada Tabel II.1. Sementara Patton dan Savicky (1993) menambahkan kriteria untuk men- jadi analis kebijakan yang unggul yaitu (i) fokus pada kriteria utama dari ma- salah; (ii) pikirkan tipe kebijakan yang dapat diambil; (iii) hindari pendekatan
- 39. ‟toolbox‟ dalam menganalisis kebijakan. Gunakan metode pendekatan seder- hana menggunakan akal sehat; (iv) pahami ketidakpastian (uncerta-inty); (v) gunakan angka; (vi) buat analisis secara transparan; (vii) cek kebenaran fak- ta; (viii) berikan analisis bukan keputusan; (ix) hasilkan tidak sekedar kebi- jakan tetapi juga alat kebijakan; (x) tidak ada kebenaran absolut atau analisis sempurna. Tabel II.1 Evaluasi Kebijakan Analisis ex-ante (sebelum pelaksanaan) dari Ex-ante policy analysis masalah, kriteria keputusan, alternatif, pro- kontra, hasil yang diperkirakan, langkah im- plementasi dan evaluasi. Analisis kebijakan atau program untuk me- Policy maintenance mastikan diimplementasikan sebagaimana di- desain dan tidak berubah diluar skenario Policy monitoring Catatan perubahan setelah kebijakan atau program diimplementasikan Analisis keberhasilan pencapaian sasaran dan Ex-post policy evaluation keberlanjutan kebijakan, modifikasi atau penghentian kebijakan Sumber: Nugroho, 2011. B. Manajemen Stratejik Pembahasan manajemen stratejik akan fokus pada pemahaman umum, tujuan dan sasaran, aspek penting, dan penerapan pada sektor publik. 1. Pemahaman Umum Manajemen stratejik secara sederhana diartikan sebagai hubungan an- tara organisasi dengan lingkungannya baik internal maupun eksternal, men- cakup bagaimana menghadapi dan menanggulangi perubahan lingkungan, serta mempengaruhi dan mengendalikan lingkungan (LAN, 2011 (c)).
- 40. Manajemen stratejik merupakan suatu cara untuk mengendalikan orga- nisasi secara efektif dan efisien, sampai pada garis terdepan sedemikian rupa sehingga tujuan dan sasaran tercapai. Konsep manajemen stratejik berasal dari sistem perencanaan stratejik, yang diperlukan karena 2 (dua) alasan yaitu (i) menanggapi perubahan ling- kungan eksternal; (ii) mengorganisir sumber daya bagi peningkatan kinerja. 2. Tujuan dan Sasaran Tujuan utama manajemen stratejik adalah pengembangan nilai orga- nisasi, kapasitas manjerial, pertanggungjawaban organisasi, dan sistem ad- ministrasi yang dihubungkan dengan pengambilan keputusan operasional dan stratejik pada semua tingkatan dan lini dalam organisasi (Hax dan Majluf, 1984). Bahkan perkembangan terbaru menunjukkan bahwa mana- jemen stratejik juga mencakup pengukuran kinerja, penetapan indikator. Selain itu juga telah menerapkan prinsip kepemerintahan yang baik. Sasaran manajemen stratejik adalah meningkatkan (i) kualitas organi- sasi, (ii) efisiensi penganggaran; (iii) optimalisasi sumber daya; (iv) kualitas evaluasi program dan pemantauan kinerja; (v) kualitas pelaporan. 3. Aspek Penting Terdapat 3 (tiga) isu penting yang perlu diperhatikan yaitu (i) penting- nya integrasi sistem administrasi dan struktur organisasi; (ii) pentingnya me- lakukan integrasi antara strateji dan operasi; (iii) pentingnya infrastruktur manajerial dan budaya organisasi. Aspek terpenting dalam manajemen stratejik (LAN, 2011) adalah (i) for- mulasi strateji, yang mencerminkan keinginan dan tujuan organisasi yang se- sungguhnya; (ii) implementasi strateji, yang menggambarkan cara mencapai tujuan dan secara teknis mencerminkan kemampuan organisasi dalam meng- alokasikan sumber daya yang tersedia; (iii) evaluasi strateji, yang mampu mengukur, mengevaluasi dan memberikan umpan balik bagi perbaikan stra-
- 41. teji, dan (iv) pengintegrasian fungsi manajemen dan penataan sumber daya yang dibutuhkan. - Formulasi strateji Tujuan utama kegiatan formulasi strateji adalah penetapan tujuan yang rasional. Sementara terdapat 3 (tiga) pertanyaan dalam formulasi strateji yang harus dijawab yaitu (i) dimana kita berada saat ini?. Jawaban diperoleh dari proses pencermatan lingkungan (PLI dan PLE) serta mengakomodasi harapan masyarakat; (ii) kemana tujuan kita?. Jawaban diperoleh dari visi, misi, nilai, tujuan dan tentunya sasaran yang berciri SMART (Specific, Measurable, Aggressive and attainable, Result oriented, Timebound); bagai- mana kita mengukur kemajuan, yaitu dengan membandingkan capaian de- ngan rencana aksi (LAN, 2011 (c)). Kegiatan formulasi strateji meliputi empat tahapan utama yaitu: (i) perumusan visi, misi dan nilai-nilai. Visi merupakan gambaran tentang masa depan ideal yang realistik, dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Visi menjawab per- tanyaan ”kita ingin menjadi apa?”. Sementara kriteria penyusunan visi antara lain (i) visi bukan fakta, tetapi gambaran ideal masa depan; (ii) dapat menimbulkan inspirasi; (iii) menjadi jembatan masa kini dan masa datang; (iv) bersifat tidak statis. Misi adalah pernyataan mengenai hal yang harus dicapai organ- isasi, yang dapat menjawab pertanyaan ”apa tugas utama kita?” atau ”mengapa organisasi dibentuk?”. Misi harus jelas menyatakan kepedulian organisasi terhadap kepentingan masyarakat. (ii) pencermatan lingkungan stratejik, baik pencermatan lingkungan internal (PLI), maupun pencermatan lingkungan eksternal (PLE), disertai kesim- pulan analisis faktor internal dan kesimpulan analisis faktor eksternal (KAFI dan KAFE). Tujuan kegiatan pencermatan lingkungan stratejik adalah untuk mengenali kekuatan dan kelemahan internal organisasi dan memahami
- 42. peluang dan tantangan eksternal organisasi sehingga organisasi dapat mengantisipasi perubahan yang akan terjadi. (iii) analisis pilihan strateji dan faktor kunci keberhasilan (FKK). Secara umum strateji diartikan sebagai pedoman atau aturan me- manfaatkan sumber daya yang terbatas secara terus menerus dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dalam kurun waktu tertentu, dengan memperhatikan faktor lingkungan internal dan eksternal. FKK adalah faktor yang sangat berpengaruh dan berfungsi untuk lebih memokuskan strateji organisasi dalam rangka pencapaian misi dan visi secara efektif dan efisien. (iv) penetapan tujuan, sasaran dan strateji organisasi (kebijakan, program dan kegiatan). Dalam kerangka pikir manajemen stratejik, perumusan tujuan me- rupakan bagian integral dari proses manajemen stratejik sebagai upaya untuk menunjang keberhasilan pencapaian visi dan misi organisasi. Un- tuk itu, tujuan harus spesifik dan dalam kurun waktu yang jelas. Tujuan menyatakan kegiatan khusus (what) yang akan diselesaikan dan kapan (when) dilakukannya. Pencapaian tujuan dapat menjadi tolok ukur menilai kinerja orga- nisasi, walaupun tujuan tidak harus merupakan tujuan organisasi se- hingga dimungkinkan berubah. Sasaran merupakan penggambaran hal yang ingin diwujudkan me- lalui tindakan yang diambil organisasi guna mencapai tujuan. Sasaran harus jelas sumber dananya. Sasaran harus bersifat spesifik, terinci, da- pat diukur dan mudah terwujud. Strateji merupakan cara mewujudkan sasaran dalam rangka men- capai tujuan, yang berkaitan dengan (i) bagaimana target kinerja dipe- nuhi; (ii) bagaimana organisasi akan memberikan fokus (pada masyara- kat); (iii) bagaimana organisasi memperbaiki kinerja pelayanan; (iv) ba- gaimana organisasi melaksanakan misinya (LAN, 2011 (c)).
- 43. - Implementasi Strateji Kegiatan implementasi strateji terdiri dari (i) rencana program dan kegiatan, (b) penganggaran, (iii) sistem pelaksanaan, pemantauan dan pe- ngawasan. Implementasi strateji menjelaskan bagaimana kita mencapai outcomes. Secara teknis, peertanyaan penting yang harus dijawab adalah bagaimana kita sampai ke tujuan?. Jawabannya diperoleh dalam rencana aksi, yang kemudian diterjemahkan dalam rencana kinerja tahunan. Rencana kinerja ini merupakan tolok ukur yang digunakan dalam menilai keberhasilan/ kegagalan penyelenggaraan kegiatan dalam suatu periode tertentu. Komponen rencana kinerja adalah (i) sasaran, indikator kinerja, dan target yang akan dicapai pada periode bersangkutan; (ii) program yang akan dilaksanakan; (iii) kegiatan, indikator kinerja dan target yang diharapkan da- lam suatu kegiatan (LAN, 2011(c)). Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif untuk dapat menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran, baik pada tahap pe- rencanaan, pelaksanaan, dan paska. Syarat sebuah indikator kinerja adalah (i) spesifik dan jelas; (ii) terukur; (iii) menangani aspek yang relevan; (iv) ha- rus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran, hasil, man- faat maupun dampak; (v) fleksibel dan sensitif; (vi) efektif. Terdapat 5 (lima) indikator kinerja yang digunakan yaitu indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Target kinerja adalah ukuran tingkat kinerja secara kuantitatif yang diharapkan tercapai. Penetapan kinerja sebaiknya memperhatikan siapa penerima manfaat dan kebutuhannya, dan standar pelayanan. Target kinerja yang baik dicirikan oleh dapat terwujud, mudah dipahami, terukur, dapat diadaptasi dalam berbagai kondisi, didukung peraturan, terfokus pada masyarakat, dan dapat dibandingkan.
- 44. - Evaluasi strateji Kegiatan evaluasi strateji terdiri dari (i) pengukuran dan evaluasi kinerja, dan (ii) pelaporan dan pertanggungjawaban. Pertanyaan mendasar adalah bagaimana cara mengikuti kemajuan setiap saat?, bagaimana mengukur dan menganalisis kinerja, dan bagaimana mekanisme pelaporan dan akuntabilitas? 4. Manajemen Stratejik pada Sektor Publik Menurut Bozemen dan Straussman (dalam Hughes, 1998) terdapat 4 (empat) prinsip penerapan manajemen stratejik pada sektor publik, yaitu (i) perhatian pada jangka panjang, (ii) pengintegrasian tujuan dan sasaran da- lam hirarki yang jelas, (iii) kesadaran bahwa manajemen stratejik dan peren- canaan stratejik membutuhkan kedisiplinan dan komitmen untuk dapat dilak- sanakan dan bukan self implementing; (iv) perspektif eksternal tidak diartikan sebagai adaptasi total terhadap lingkungan, tetapi merupakan antisipasi ter- hadap perubahan lingkungan (LAN, 2011 (c)). Selain hal tersebut, faktor politik juga perlu mendapat pertimbangan. Hal ini terutama karena faktor politik menimbulkan kendala dalam penerapan manajemen stratejik di sektor publik. Akibatnya obyektifitas dan rasionalitas menjadi berkurang. Kesulitan lainnya adalah menentukan tujuan dan sasaran. Sektor publik menjangkau spektrum yang sangat luas, yang berakibat isu yang ditangani juga menjadi sangat luas. Hal lain yang juga terkendala adalah berkaitan dengan pengukuran ki- nerja. Salah satu faktor yang berpengaruh adalah keberadaan data dan in- formasi berkualitas sebagai masukan bagi pengukuran kinerja. Keakuratan data dan informasi menjadi suatu keniscayaan. Sementara di sektor publik, ketersediaan data dan informasi berkualitas masih menjadi kendala utama. Keberhasilan penerapan manajemen stratejik di sektor publik sangat di- tunjang oleh keterlibatan pemangku kepentingan, tidak kaku, dan bukan me- rupakan tujuan sektor publik.
- 45. C. Manajemen Pengetahuan Pembahasan manajemen pengetahuan terfokus pada pemahaman tentang data, informasi, pengetahuan dan manajemen pengetahuan, tahapan, kegiatan, strategi manajemen pengetahuan, dan penerapannya pada organisasi publik. 1. Pemahaman tentang Data, Informasi dan Pengetahuan Berbicara tentang manajemen pengetahuan, terdapat 3 (tiga) termi- nologi yang harus dipahami secara benar, yaitu data, informasi dan penge- tahuan. Davenport dan Prusak (1998) membedakan pengertian antara data, informasi dan pengetahuan yaitu : “knowledge is neither data nor informa- tion, though it related to both, and the differences between these terms are often a matter of degree”. Jadi pengetahuan bukan data maupun informasi, walaupun terkait kepada keduanya, dan perbedaannya antara istilah ini se- ringkali tergantung pada tingkat pembedaannya (Setiarso, 2006). Lebih lanjut, data adalah fakta tentang suatu kejadian. Seperti yang di- contohkan oleh Davenport dan Prusak, bila seseorang pelanggan datang un- tuk mengisi tanki mobilnya ke pompa bensin, maka transaksi yang terjadi da- pat digambarkan sebagian oleh data, yaitu berapa uang yang harus diba- yarkan, berapa liter bensin yang diisikan, namun tidak menjelaskan mengapa pelanggan itu datang ke pompa bensin, kualitas pelayanan pompa bensin, dan tidak dapat meramalkan kapan lagi pelanggan tersebut akan kembali ke pompa bensin. Dalam organisasi, data terdapat dalam catatan-catatan (re- cords) atau transaksi-transaksi. Sementara informasi adalah data yang membuat sebuah pembedaan. Kata inform sejatinya berarti to give shape atau untuk memberi bentuk, dan informasi ditujukan untuk membentuk orang yang mendapatkannya, yaitu untuk membuat agar pandangan atau wawasan orang tersebut berbeda (dibandingkan sebelum memperoleh informasi). Sebagai contoh pelanggan mengisi tanki mobilnya dengan bensin premix, bukan premium, pernyataaan tersebut merupakan informasi. Menurut Peter Drucker, tidak seperti data, in-
- 46. formasi mempunyai makna (meaning) yang ditimbulkan oleh relevansi dan tujuan yang diberikan oleh penciptanya. Misalnya pemberi informasi me- nyampaikan bahwa pelanggan mengisi tanki mobilnya dengan bensin premix, bukan premium, mengandung tujuan tertentu yang dikaitkan dengan lawan bicara, atau mengandung relevansi tertentu yang dikaitkan dengan lawan bicara, atau mengandung relevansi tertentu yang dikaitkan dengan topik pembicaraan. Davenport dan Prusak memberikan metode mengubah data menjadi informasi melalui kegiatan yang dimulai dengan huruf C: contextu- alized, calculated, corrected, dan condensed. Dalam organisasi, infomasi ter- dapat dalam pesan (messages). Pengetahuan adalah campuran dari pengalaman, nilai, informasi konteks- tual, dan pandangan ahli yang memberikan kerangka bagi evaluasi dan pe- nyatuan pengalaman baru dan informasi. Dimulai dan diterapkan di benak se- seorang (yang mempunyai pengetahuan). Dalam sebuah organisasi, penge- tahuan seringkali melekat tidak hanya pada dokumen tetapi juga dalam rutin- itas, proses, praktek, dan norma organisasi (Davenport, 1998). Sebagian ahli merujuk informasi sebagai data yang terkait deskripsi, definisi atau perspektif (what, who, when, where). Sementara pengetahuan terdiri dari strategi, praktek, metode atau pendekatan (how) Penjelasan yang lebih rinci tentang pemahaman pengetahuan terdapat dalam buku yang ditulis oleh Von Krogh, Ichiyo, serta Nonaka 2000 (disarikan dari Setiarso, 2006), dituliskan ringkasan gagasan yang mendasari pengertian mengenai pengetahuan. Pengetahuan merupakan justified true believe. Seo- rang individu membenarkan (justifies) kebenaran atas kepercayaannya ber- dasarkan observasinya mengenai dunia. Jadi bila seseorang menciptakan pe- ngetahuan, ia menciptakan pemahaman atas suatu situasi baru dengan cara berpegang pada kepercayaan yang telah dibenarkan. Dalam definisi ini, pe- ngetahuan merupakan konstruksi dari kenyataan, dibandingkan sesuatu yang benar secara abstrak. Penciptaan pengetahuan tidak hanya merupakan kom- pilasi dari fakta-fakta, namun suatu proses yang unik pada manusia yang sulit
- 47. disederhanakan atau ditiru. Penciptaaan pengetahuan melibatkan perasaan dan sistem kepercayaan (belief systems) dimana perasaan atau sistem keper- cayaan itu bisa tidak disadari. Jadi dapat disimpulkan bahwa data pada dasarnya berupa simbol, fakta, angka, grafik, peta atau hasil observasi. Informasi adalah data yang telah di- tambahkan makna tertentu. Informasi merupakan kumpulan data yang terka- it dengan penjelasan, interpretasi, yang ada hubungannya dengan materi atau obyek, peristiwa atau proses tertentu. Data berubah menjadi informasi ketika data tersebut telah melalui pengategorisasian, penyaringan, atau pe- nyusunan. Adapun pengetahuan, yaitu informasi yang telah di evaluasi, disu- sun dan dikelola serta telah diberi tujuan (Sangkala, 2007). 2. Jenis Pengetahuan Pengetahuan dapat dibagi dalam 2 (dua) kategori yaitu pengetahuan imp- lisit (tacit knowledge) dan pengetahuan eksplisit (explicit knowledge). Pe- ngetahuan implisit lebih sulit dikomunikasikan dan ditransfer ke pihak lain ka- rena melekat dalam pengetahuan seseorang, dan kebenarannya masih bersi- fat subyektif. Sementara itu, pengetahuan eksplisit merupakan pengetahuan yang lebih mudah ditransfer. Proses transfernya dapat dilakukan melalui kata, formula ilmu pengetahuan, spesifikasi produk, manual, dan prinsip universal (Sangkala, 2007). Diantara kedua jenis pengetahuan tersebut, dapat terjadi saling pengaruh yang menghasilkan 4 (empat) macam mode konvensi seba- gaimana pada Gambar 2.4. Gambar 2.4 Mode Konversi Pengetahuan ke Tacit Knowledge Explicit knowledge Tacit Sosialisasi Eksternalisasi knowledge Dari Explicit Internalisasi Kombinasi knowledge Sumber: Ikijiro Nonaka dan Hirotaka Takeuchi, 1995
- 48. 3. Pentingnya Pengetahuan Berdasar hasil studi yang dilakukan oleh John Kendrick (1999), ditemukan bahwa (i) pada tahun 1920, rasio modal tangible terhadap modal intangible berkisar antara 30:70 persen; (ii) pada tahun 1990 rasio tersebut berbalik menjadi 63:37 persen. Sementara Margaret Blair (1999) menemukan hasil yang relatif sama bahwa (i) pada tahun 1978, sekitar 80 persen nilai perusa- haan berasal dari aset tangible; (ii) pada tahun 1988, rasio menjadi berubah 45:55 persen; (iii) pada tahun 1998, ternyata tinggal 30 persen nilai perusa- haan berupa aset tangible. Kedua studi ini memberi pemahaman kepada kita bahwa telah terjadi pergeseran kesadaran akan pentingnya sumber daya pe- ngetahuan (aset intangible) (Sangkala, 2007). Disadari juga bahwa pengetahuan mempunyai beberapa keunggulan sebagaimana dikemukakan Stewart (1997), diantaranya (i) non-subtractive, artinya ketika seseorang berbagi pengetahuan dengan orang lain, pengeta- huan orang tersebut tidak akan berkurang; (ii) pengetahuan dapat dimiliki secara bersama-sama tanpa mengurangi kemanfaatan pengetahuan tersebut; (iii) dapat dimiliki oleh banyak pihak, yang berarti dapat disebarkan ke ber- bagai tempat dalam waktu bersamaan; (iv) memiliki struktur pembiayaan berbeda dari produk lainnya. Sebagai ilustrasi, catatan perkuliahan dapat di fotokopi sehingga biayanya menjadi sangat murah; (v) jarang memiliki skala ekonomi. Biaya yang dikeluarkan relatif tidak jauh berbeda walaupun dipro- duksi dalam skala yang banyak (Sangkala, 2007). 4. Pemahaman Manajemen Pengetahuan Tidak terdapat satu definisi yang disepakati oleh para ahli terkait manajemen pengetahuan, namun definisi berikut setidaknya bisa sedikit men- jelaskan. Manajemen pengetahuan (knowledge management) adalah suatu rangkaian kegiatan yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan penge- tahuan untuk digunakan kembali, diketahui, dan dipelajari di dalam organ-
- 49. isasi. Kegiatan ini biasanya terkait dengan sasaran organisasi dan ditujukan untuk mencapai suatu hasil tertentu seperti pengetahuan bersama, pe- ningkatan kinerja, keunggulan kompetitif, atau tingkat inovasi yang lebih tinggi (Kuswartojo, 2011) Bagaimanapun dan dengan pendekatan manapun manajemen penge- tahuan didefinisikan sesungguhnya terdapat pandangan yang sama bahwa pengetahuan adalah harta (aset) yang tak ternilai. Bahkan bisa menjadi mo- dal yang lebih berharga dari pada dana dan berbagai modal fisik lain. Dipa- hami pula bahwa manajemen pengetahuan: bukan kegiatan yang berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan pemantauan, pengawasan dan pengambilan keputusan berbagai kebijakan, rencana ataupun program aksi. bukan hanya mendokumentasi atau mengumpulkan hasil kajian atau pengalaman, tetapi mengorganisasikan dan menyerap pengetahuan dan pengalaman yang lekat pada pikiran dan diri perorangan. bukan hanya mengumpulkan, mendokumentasi serta mendiseminasikan data dan informasi tetapi mengolah dan menggarapnya sehingga menjadi pengetahuan yang menyatu pada organisasi dan diri para pemegang pe- ranan, untuk mendorong inovasi dan meningkatkan kualitas keputusan bukan hanya penggunaan teknologi informasi dan dokumentasi, dan juga bukan hanya membangun jejaring digital, tetapi menggunakan teknologi tersebut untuk meningkatkan kapasitas perorangan dan organisasi (Kus- wartojo, 2011). 5. Tahapan dan Kegiatan Manajemen Pengetahuan Menurut Davenport (1988), terdapat enam tahap dalam siklus pengeta- huan yaitu (i) menciptakan pengetahuan. Pengetahuan diciptakan begitu ma- nusia menentukan cara baru untuk melakukan sesuatu atau menciptakan know-how. Kadang-kadang pengetahuan eksternal dibawa ke dalam organi- sasi/institusi; (ii) menangkap pengetahuan. Pengetahuan baru diidentifikasikan
- 50. sebagai bernilai dan direpresentasikan dalam suatu cara yang masuk akal; (iii) menjaring pengetahuan. Pengetahuan baru harus ditempatkan dalam konteks agar dapat ditindaklanjuti. Hal ini menunjukkan kedalaman manusia (kualitas tacit) yang harus ditangkap bersamaan dengan fakta eksplisit; (iv) menyim- pan pengetahuan. Pengetahuan yang bermanfaat harus disimpan dalam for- mat yang baik dalam penyimpanan pengetahuan, sehingga orang lain dalam organisasi dapat mengaksesnya; (v) mengolah pengetahuan. Pengetahuan harus selalu terbarukan, (vi) mendiseminasikan pengetahuan. Pengetahuan harus tersedia dalam format yang bermanfaat untuk semua orang dalam or- ganisasi yang memerlukan, dimanapun dan tersedia setiap saat, (vii) mencip- takan pengetahuan lagi, dan seterusnya. Penciptaan pengetahuan secara efektif bergantung pada konteks yang memungkinkan terjadinya penciptaan tersebut. Apa yang dimaksud dengan konteks yang memungkinkan terjadinya penciptaan pengetahuan adalah ru- ang bersama yang dapat memicu hubungan-hubungan yang muncul. Dalam konteks organisasional, bisa berupa fisik, maya, mental atau ketiganya. Pe- ngetahuan bersifat dinamis, relasional dan berdasarkan tindakan manusia, jadi pengetahuan berbeda dengan data dan informasi, bergantung pada konteksnya. Penciptaan pengetahuan melibatkan lima langkah utama menurut Von Krogh, Ichiyo serta Nonaka (2000), yaitu (i) berbagi pengetahuan terbatin- kan, (ii) menciptakan konsep, (iii) membenarkan konsep, (iv) membangun prototipe; dan (v) melakukan penyebaran pengetahuan di berbagai fungsi dan tingkat di organisasi. Dalam organisasi, pengetahuan diperoleh dari individu-individu atau ke- lompok orang-orang yang mempunyai pengetahuan, atau kadang kala dalam rutinitas organisasi. Pengetahuan diperoleh melalui media yang terstruktur seperti: buku dan dokumen, hubungan orang-ke-orang yang berkisar dari pembicaraan ringan hingga ilmiah (Davenport, 1998). Dalam praktiknya manajemen pengetahuan itu mencakup kegiatan:
- 51. Mendokumentasikan dan menyimpan data, informasi dan pengetahuan eksplisit. Memanfaatkan pengetahuan dalam proses produksi dan pelayanan, me- malihkan pengetahuan menjadi kebijakan, rencana atau program Mendorong perkembangan pengetahuan melalui budaya kerja organisasi dan berbagai insentif Mengalihkan dan membagi pengetahuan kepada keseluruhan unsur or- ganisasi. Menelaah dan menilai kekayaan pengetahuan dan efeknya secara regu- ler. Mengakomodasikan dan memfasilitasi pengetahuan yang bersumber dari luar organisasi (Kuswartojo, 2011). 6. Strategi Mengelola Pengetahuan Riset Delphi Group menunjukkan bahwa pengetahuan dalam organisasi tersimpan dalam struktur (i) di pikiran (otak) karyawan 42%, (ii) dokumen kertas 26%, (iii) dokumen elektronik 20%, (iv) knowledge based elektronik 12% (Setiarso, 2006). Fakta ini menunjukkan bahwa keberadaan pengeta- huan tersebar pada beberapa lokasi sehingga dibutuhkan suatu strategi un- tuk mengelolanya. Hansen, Nohria dan Tierney (1999) mengemukakan strategi organisasi mengelola pengetahuan yang terbagi atas dua ekstrim: strategi kodifikasi (codification strategy) dan strategi personalisasi (personalization strategy). Bila pengetahuan diterjemahkan dalam bentuk eksplisit secara berhati-hati (codified) dan disimpan dalam basis data sehingga para pencari penge- tahuan yang membutuhkannya dapat mengakses pengetahuan tersebut, maka cara mengelola seperti ini dikatakan menganut strategi kodifikasi. Na- mun pengetahuan tidak terdiri dari hanya eksplisit saja, melainkan juga pe- ngetahuan terbatinkan. Pengetahuan terbatinkan amat sangat sulit diterje- mahkan ke dalam bentuk eksplisit. Oleh sebab itu, pengetahuan dialihkan
- 52. dari satu pihak ke pihak lain melalui hubungan personal yang intensif, jadi fungsi utama jaringan komputer (intranet atau internet) bukan saja untuk menyimpan pengetahuan melainkan juga untuk memfasilitasi lalu lintas atau komunikasi di antara individu atau peneliti dalam organisasi yang sedang melakukan kegiatan penelitian baik mencari informasi atau memanfaatkan pengetahuan baru untuk menunjang kegiatan penelitiannya. Birkinsaw (2001) juga menggarisbawahi tiga kenyataan yang sangat mempengaruhi berhasil-tidaknya manajemen pengetahuan. Pertama, pene- rapannya tidak hanya menghasilkan pengetahuan baru tetapi juga menda- ur-ulang pengetahuan yang sudah ada. Kedua, teknologi informasi belum se- penuhnya bisa menggantikan fungsi jaringan sosial antar anggota organi- sasi. Ketiga, sebagian besar organisasi tidak pernah tahu apa yang sesung- guhnya mereka ketahui, banyak pengetahuan penting yang harus ditemu- kan lewat upaya-upaya khusus, padahal pengetahuan itu sudah dimiliki se- buah organisasi sejak lama. 7. Strategi Penerapan Manajemen Pengetahuan Beberapa perubahan dan persiapan matang harus dilakukan sehingga penerapan manajemen pengetahuan dapat berlangsung dengan baik, seba- gai berikut (i) Dimensi konseptual, yaitu agar organisasi mampu mengem- bangkan suatu konsep yang terintegrasi, dan multi dimensi; (ii) Perubahan. Manajemen pengetahuan dirancang untuk mengubah organisasi sehingga di- butuhkan konsep manajemen perubahan, terutama perpindahan dari ben- tuk aktifitas lama kepada bentuk yang baru; (iii) Pengukuran. Hal ini me- mungkinkan kita untuk mengetahui sejauh mana kita telah bergerak menuju sasaran; (iv) struktur organisasi. Struktur organisasi memungkinkan kita un- tuk berbagi peran dan tanggungjawab yang diperlukan agar efektifitas ma- najemen pengetahuan dapat terlaksana; (v) isi pengetahuan. Jika pengeta- huan dianggap sebagai produk, pengetahuan dapat diklasifikasikan dengan berbagai cara. Untuk mengelola isi pengetahuan dapat dikembangkan direk-
- 53. tori keahlian, sistem (i) pengelolaan keterampilan, peta pengetahuan, atau model isi pengetahuan; (vi) alat. Dimensi ini terkait erat dengan keterse- diaan sarana untuk memperoleh pengetahuan. Selain itu, agar penciptaan pengetahuan berjalan sebagaimana mesti- nya, kondisi sosial juga perlu diperhatikan dengan cara (i) perhatian. Pembe- rian perhatian akan mendorong timbulnya keterbukaan diantara karyawan maupun karyawan dan atasan; (ii) penilaian. Menurut Senge (1990), manu- sia harus didesain ulang model mentalnya agar berkeinginan mendukung ak- tifitas berbagi pengetahuan serta pengalaman. Selain itu, dibutuhkan juga insentif; (iii) pemberdayaan, yang dimaksudkan sebagai keterlibatan orang dalam perubahan yang memengaruhi mereka. Pemberdayaan akan mening- katkan motivasi karyawan dalam menciptakan pengetahuan; (iv) keperca- yaan. Kepercayaan menjadi syarat utama dalam berbagi ide, informasi dan pengetahuan; (v) otonomi, yang diartikan sebagai kebebasan bergerak bagi setiap orang sepanjang memungkinkan. Hal ini berujung pada penciptaan pengetahuan; (vi) pengungkitan kompetensi. Kompetensi diartikan sebagai kemampuan seseorang menjalankan tugasnya. Pengungkitan kompetensi dapat merangsang terjadinya berbagi pengetahuan (Sangkala, 2007). 8. Langkah Stratejik Penerapan Manajemen Pengetahuan Tiwana (2000) menyatakan bahwa paling tidak terdapat sepuluh lang- kah stratejik yang dapat dilakukan oleh suatu organisasi dalam menerapkan manajemen pengetahuan sebagai berikut (i) Analisis infrastruktur. Langkah ini berupa audit infrastruktur teknolo- gi yang tersedia dalam organisasi sehingga dapat dikenali kebutuh- annya. (ii) Mengaitkan manajemen pengetahuan dengan strategi bisnis. Pene- rapan manajemen pengetahuan dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja suatu organisasi, sehingga harus sejalan dengan strategi bis- nis yang telah ada.
- 54. (iii) Mendesain infrastruktur manajemen pengetahuan. Pada tahap ini, pengambil keputusan sudah menetapkan jenis teknologi yang dibu- tuhkan (iv) Mengaudit aset dan sistem pengetahuan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui pengetahuan yang telah ada dalam organisasi dan menentukan fokus aktifitas manajemen pengetahuan. (v) Mendesain tim manajemen pengetahuan. Dibutuhkan suatu tim yang solid yang dapat terdiri dari pengambil keputusan, dan tenaga ahli internal dan eksternal. (vi) Menciptakan cetak biru manajemen pengetahuan. Tim manajemen pengetahuan yang telah terbentuk sebaiknya mulai menyusun cetak biru manajemen pengetahuan, yang berfungsi sebagai pedoman pe- nerapan manajemen pengetahuan di suatu organisasi. (vii) Pengembangan sistem manajemen pengetahuan. Pada tahap ini tim yang telah terbentuk mulai menggabungkan sistem manajemen pe- ngetahuan yang telah dibangun pada enam tahap sebelumnya. (viii) Prototipe dan uji coba. Manajemen pengetahuan yang telah dikem- bangkan mulai diujicobakan untuk melihat seberapa jauh dapat dite- rapkan. (ix) Pengelola perubahan, kultur dan struktur penghargaan. Manajemen pengetahuan tidak hanya terkait teknologi tetapi juga perubahan kultur. Dianggap perlu untuk menyiapkan sistem penghargaan. (x) Evaluasi kinerja, dan perbaikan sistem manajemen pengetahuan. Tahap ini yang relatif sulit karena belum tersedia alat evaluasi kiner- ja yang baku. Tiwana mencoba mengadopsi metode Balance Score- card dalam menilai kinerja. Adapun bentuknya sebagai berikut (i) perspektif keuangan. Apakah investasi dalam manajemen penge- tahuan memperoleh keuntungan keuangan?; (ii) perspektif modal manusia. Apakah kinerja karyawan lebih baik dan lebih berbagi?; (iii) perspektif modal pelanggan. Sudah baikkah hubungan kita
- 55. dengan pelanggan, dan mendatangkan banyak pelanggan?; (iv) perspektif modal organisasi. Apakah saat ini kita memiliki proses paling baik, kapabilitas sangat berbeda, kemampuan sangat hebat untuk melakukan inovasi melalui manajemen pengetahuan diban- ding organisasi lain? (Sangkala, 2007). 9. Penerapan pada Organisasi Publik Manajemen pengetahuan juga dikembangkan untuk sektor publik atau penyelenggaraan pemerintahan, walaupun adopsi manajemen pengetahuan dalam pemerintahan sipil dianggap lambat. Ada yang berpendapat hal ini di- sebabkan karena pada umumnya pemerintah tidak menyukai pengetahuan dan perubahan. Pendapat ini tentu saja tidak sepenuhnya benar. Di Indone- sia, Sekretariat Kabinet melalui ITCP telah mengembangkan informasi inter- aktif terkait kemajuan pelaksanaan proyek besar di seluruh Indonesia. Hal ini dianggap sebagai penerapan manajemen pengetahuan yang berhasil, wala- upun sebatas untuk pelaksanaan proyek. Selain itu, di kalangan pemerintah pasti ada pihak atau elemen yang mempunyai pemahaman penuh bahwa pengetahuan adalah modal yang tiada tara. Suatu modal nirwujud yang da- pat terus dikembangkan, yang tidak akan habis, tidak akan hilang dicuri atau dialihkan. Pengetahuan akan dapat mendorong inovasi dan meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Kesulitan pemerintah dalam mengadopsi manajemen pengetahuan an- tara lain adalah tidak terlalu mudah untuk mendeliniasi dan mengisolasi su- atu satuan organisasi. Pemerintah merupakan organisasi dengan jejaring yang sangat luas, yang geraknya dikerangkakan dalam suatu peraturan per- undangan. Sehingga bagaimanapun inovasi dan efektifivitas yang menjadi maksud dikembangkannya manajemen pengetahuan suatu organisasi pe- merintah, juga akan ditentukan oleh keterkaitannya dengan aneka organ- isasi pemerintah yang lain. Untuk menghindari hambatan oleh karena ada- nya saling keterkaitan tersebut, diciptakanlah suatu aturan dan kerangka
- 56. kerja yang di satu sisi memang dapat mencegah kondisi kaostik tetapi di sisi lain sering menghambat inovasi dan efektifitas gerak. Dinding penyekat be- rupa tugas pokok dan fungsi sering menjadi penghalang kreativitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di manapun di dunia. Walapun demikian beberapa contoh seperti FAA (Federal Aviation Administration) di Amerika, berbagai pemerintah daerah di Inggris (London Borough of Camden, Wiltshire County Council), Kantor Statistik Australia, menunjukkan keberhasilannya mengembangkan manajemen pengetahuan. Tentu saja apa yang dimaksud dengan inovasi dan peningkatan efektifitas dalam pemerintahan jelas tidak sama ukurannya dengan apa yang dilaku- kan di dunia bisnis. Pembahasan manajemen pengetahuan pada umumnya ditujukan untuk kepentingan suatu organisasi usaha, tentara atau pemerintah. Manajemen pengetahuan pada umumnya ditempatkan sebagai elemen dan instrumen organisasi untuk mendorong inovasi, meningkatkan kreativitas, meningkat- kan kapasitas dan efektifitas gerak, produk dan aktivitas organisasi. Artinya manajemen memang ditujukan untuk kepentingan internal organisasi. Wala- upun sesungguhnya juga dapat ditemukan manajemen pengetahuan untuk tujuan yang lebih luas. Berdasarkan uraian dan telaah yang telah dilakukan dapat dipertim- bangkan agar manajemen pengetahuan di lingkungan Kemenpera lebih di- tujukan bagi kepentingan kementerian untuk melaksanakan kegiatan seba- gai berikut: a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman tahun 2015-2020. b. Mengefektifkan dan mengefisienkan pelaksanaan RPJMN 2010-2014 dan menjadikan kegiatan ini pembelajaran (lesson learned) untuk perumus- an kebijakan, perencanaan dan pelaksanaannya masa datang. c. Meningkatkan daya tanggap Kemenpera atas berbagai permasalahan pe- rumahan dan permukiman yang muncul.
- 57. d. Mengefektifkan pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman oleh pemerintah daerah. e. Meningkatkan kualitas kebijakan, rencana dan program fasilitasi masyara- kat berpenghasilan rendah. f. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas kebijakan, rencana dan program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh. g. Meningkatkan efektifitas instrumen penunjang penyelenggaraan peru- mahan dan kawasan permukiman seperti pertanahan, pendanaan dan pembiayaan (Kuswartojo, 2011).
- 58. BAB III INSTRUMEN ANALISIS Dalam upaya menghasilkan kebijakan dan strateji yang baik, dibutuhkan alat analisis yang sesuai dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan isu yang dihadapi, dan mudah dilaksanakan. Pada bagian ini, disajikan penjelasan tentang alasan pemilihan alat analisis, disertai penjelasan rinci dari masing-masing alat analisis tersebut. A. Pemilihan Alat Analisis Pada kajian ini dipergunakan Strength, Weakness, Opportunity, Threat (SWOT) dan Balanced Scorecard (BSC). Alasan utama pemilihan SWOT adalah kekuatannya dalam melakukan penyaringan faktor berpengaruh dengan merinci kedalam empat kategori yaitu kekuatan dan kelemahan (internal), dan peluang dan ancaman (eksternal) sehingga outputnya yang berupa tujuan strategis menjadi lebih bermakna. Sementara pemilihan BSC dengan mempertimbangkan kekuatannya dalam menghasilkan rencana aksi. Terdapat paling tidak 5 (lima) manfaat utama dari BSC yaitu (i) merupakan sebuah alat untuk mengomunikasikan strategi kepada pemangku kepentingan termasuk pengelola, pekerja, pelanggan/masyarakat. Melalui BSC, pemangku kepentingan dapat mereview strategi dan pencapaiannya menggunakan ‟bahasa‟ yang sama; (ii) memungkinkan sebuah organisasi meme- takan seluruh faktor utama dalam organisasi baik aset fisik maupun non fisik; (iii) mengaitkan strategi organisasi terhadap kinerjanya. BSC membantu organisasi mengembangkan tidak hanya strategi tetapi juga memantau pencapaian stra- tegi; (iv) mengenali konsep sebab dan akibat; (v) membantu menghitung ang- garan (Luis, 2011). Selain itu, BSC telah mulai diimplementasikan oleh organisasi publik baik di Indonesia maupun di mancanegara. Di Indonesia, BSC telah diadopsi walaupun
- 59. hanya sebagian saja melalui kewajiban instansi pemerintah sampai eselon II menyusun LAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah), dan menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU). Diharapkan dengan gabungan kedua alat analisis ini, dapat dihasilkan suatu keluaran yang terpadu dari suatu proses formulasi kebijakan dan formulasi rencana aksi, mulai dari visi sampai ke rencana aksi. B. SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) Alat analisis SWOT merupakan suatu alat yang dapat membantu mengenali kekuatan dan kelemahan internal organisasi dan memahami peluang dan tan- tangan eksternal organisasi. Langkah analisis yang dilakukan dengan menggu- nakan SWOT adalah (i) Pencermatan lingkungan, yang meliputi pencermatan lingkungan internal (PLI) dan pencermatan lingkungan eksternal (PLE). a. Lingkungan internal meliputi (i) kekuatan, yaitu situasi dan kemam- puan internal yang bersifat positip yang memungkinkan organisasi me- menuhi keuntungan stratejik dalam mencapai visi dan misi; dan (ii) ke- lemahan, yaitu situasi dan faktor-faktor dalam organisasi yang bersifat negatif, yang menghambat organisasi mencapai atau mampu melam- paui pencapaian visi dan misi. b. Lingkungan eksternal meliputi (i) peluang, yaitu situasi dan faktor-fak- tor luar organisasi yang bersifat positif, yang membantu organisasi mencapai visi dan misi; dan (ii) ancaman, yaitu faktor luar organisasi yang bersifat negatif, yang dapat mengakibatkan organisasi gagal mencapai visi dan misinya. PLI merupakan upaya mencermati kekuatan dan kelemahan di lingkung- an internal organisasi yang dapat dikelola manajemen, sementara PLE merupakan upaya mencermati peluang dan tantangan yang ada di ling- kungan eksternal organisasi.
- 60. (ii) Menyimpulkan analisis, yang meliputi kesimpulan analisis faktor internal (KAFI), dan kesimpulan analisis faktor eksternal (KAFE). Faktor internal dan eksternal yang telah diidentifikasi kemudian dite- tapkan urutan prioritasnya melalui pembobotan, penetapan rating, dan penghitungan skor. Adapun besarnya bobot ditetapkan berdasarkan ke- mungkinan dampak dari faktor internal dan eksternal terhadap keber- hasilan organisasi. Bobot tinggi diberi kepada faktor yang berdampak besar, dan sebaliknya kepada faktor yang kurang berdampak (skalanya 0- 100). Rating adalah tanggapan manajemen organisasi terhadap faktor ter- sebut. Jika menonjol diberi rating besar dan sebaliknya (skalanya 0-1). Sementara skor merupakan hasil perkalian antara bobot dan rating dari masing-masing faktor. Besarnya skor akan menentukan urutan prioritas. Semakin besar skor maka semakin besar urutan prioritas (prioritas 1 me- rupakan prioritas tertinggi). (iii) Memilih asumsi strateji. Tahapan ini merupakan kelanjutan tahapan sebelumnya. Pada tahap- an ini dilakukan penetapan asumsi strateji melalui penggabungan antara hasil KAFI dan KAFE. Terdapat empat kategori asumsi strateji yaitu (a) SO (kekuatan vs peluang), yang diartikan sebagai pemanfaatan kekuatan un- tuk memanfaatkan peluang; (b) WO (kelemahan vs peluang), yang diar- tikan sebagai menanggulangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang; (c) ST (kekuatan vs ancaman), yang diartikan sebagai memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman bahkan mengubahnya menjadi pe- luang; (d) WT (kelemahan vs ancaman), yang diartikan sebagai memper- kecil kelemahan dan menghindari ancaman. (iv) Menetapkan Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) Pada tahapan ini, setiap asumsi strateji ditetapkan keterkaitannya de- ngan visi, misi, dan nilai-nilai melalui penetapan rating (1-4). Semakin be- sar rating semakin besar keterkaitan. Asumsi strateji dengan skor terbe-
- 61. sar mempunyai peluang yang lebih besar terpilih sebagai faktor kunci ke- berhasilan (FKK). (v) Menetapkan tujuan. Tujuan ditetapkan dengan menggabungkan misi dan FKK. C. BSC (Balanced Scorecard) 1. Pengertian BSC adalah sebuah alat pengelolaan kinerja yang membantu sebuah organisasi menterjemahkan visi dan strateginya ke rencana aksi, meman- faatkan sekelompok indikator keuangan dan non keuangan yang terkait da- lam hubungan sebab akibat. Namun, BSC tidak hanya sampai pada rencana aksi tetapi berlanjut pada pemantauan pelaksanaan strateji. Ukuran yang digunakan tidak untuk mengendalikan perilaku tetapi untuk mengartikulasikan strateji organisasi, mengomunikasikan strateji organisasi, dan membantu menyinergikan inisiatif individu, lintas-departemen, organ- isasi, demi mencapai sasaran bersama (Gaspersz, 2002). Pemahaman ‟berimbang‟ (balanced) dalam BSC adalah keseimbangan an- tara (i) aspek keuangan dan non keuangan; (ii) indikator masa lalu, seka- rang dan masa depan; (iii) indikator internal dan eksternal; (iv) indikator pe- nyebab dan indikator dampak/terpengaruh. Sementara ‟kartu skor‟ (score- card) mengacu sebagai kartu laporan atau kartu nilai (Luis, 2011). Terdapat empat perspektif dalam BSC berdasar pemanfaatan di sektor publik yaitu (a) Perspektif keuangan dimaksudkan sebagai konsekuensi ke- uangan dari suatu kebijakan. Namun berbeda dengan perusahaan, orga- nisasi publik menjadikan perspektif keuangan bukan sebagai tujuan akhir tetapi sebagai pijakan awal. Pejabat pemerintah harus berfokus pada peme- nuhan kebutuhan pelayanan publik dengan cara yang efisien. Mereka harus menjawab pertanyaan “apakah pelayanan publik yang diberikan pada tingkat biaya yang kompetitif dan efisien?”; (b) Perspektif pelanggan dimaksudkan sebagai tingkat penerimaan masyarakat (dalam organisasi publik) terhadap
