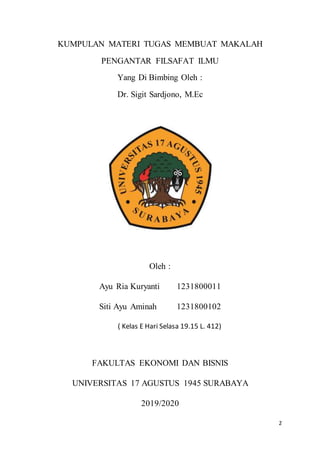
KUMPULAN MAKALAH FILSAFAT ILMU oleh Dr. Sigit Sardjono, M.Ec
- 1. 2 KUMPULAN MATERI TUGAS MEMBUAT MAKALAH PENGANTAR FILSAFAT ILMU Yang Di Bimbing Oleh : Dr. Sigit Sardjono, M.Ec Oleh : Ayu Ria Kuryanti 1231800011 Siti Ayu Aminah 1231800102 ( Kelas E Hari Selasa 19.15 L. 412) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA 2019/2020
- 2. 3 DAFTAR ISI A. Makalah Manfaat Belajar Filsafat Ilmu Bagi Mahasiswa ....................... 2 B. Makalah Sejarah Perkembangan Filsafat Ilmu ......................................12 C. Makalah Teori Kebenaran....................................................................28 D. Makalah Filsafat Manusia....................................................................35 E. Makalah Filsafat Pengetahuan dan Ilmu ..............................................46 F. Makalah Filsafat Etika dan Moral ........................................................57 G. Makalah Filsafat Pancasila...................................................................72 H. Makalah Karya Ilmiah.........................................................................79 I. Kumpulan Soal Tanya Jawab ...............................................................92
- 3. 4 A. MAKALAH MANFAAT FILSAFAT ILMU BAGI MAHASISWA PEMBAHASAN Kata falsafah atau filsafat dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan daribahasa Arab, yang juga diambil dari bahasa Yunani(philosophia). Dalam bahasa ini, kata ini merupakan kata majemuk dan berasal dari kata-kata philia (= persahabatan, cinta dsb.) dan sophia (= “kebijaksanaan”). Sehingga arti lughowinya (secara bahasa) adalah seorang “pencinta kebijaksanaan”. Ada juga yang mengurainya dengan kata philare atau philo yang berarti cinta dalam arti yang luas yaitu “ingin” dan karena itu lalu berusaha untuk mencapai yang diinginkan itu. Kemudian dirangkai dengan kata Sophia artinya kebijakan, pandai dan pengertian yang mendalam. Dengan mengacu pada konsepsi ini maka dipahami bahwa filsafat dapat diartikan sebagai sebuah perwujudan dari keinginan untuk mencapai pandai dan cinta pada kebijakan. Filsafat dalam khazanah Islam menggunakan rujukan kata yakni falsafah. Istilah filsafat berasal dari bahasa Arab oleh karena orang Arab lebih dulu datang dan sekaligus mempengaruhi bahasa Indonesia dibanding dengan bahasa-bahasa lain ke tanah air Indonesia. Oleh karenanya konsistensi yang patut dibangun adalah penyebutan filsafat dengan kata falsafat. Pada sisi yang lain kajian filsafat dalam wacana muslim juga sering menggunakan kalimat padanan hikmah sehingga ilmu filsafat dipadankan dengan ilmu hikmah. Hikmah digunakan sebagai bentuk ungkapan untuk menyebut makna kearifan, kebijaksanaan. sehingga dalam berbagai literatur kitab-kitab klasik dikatakan bahwa orang yang ahli kearifan disebut Hukama’. Seringkali pula ketika dikaji dalam berbagai kitab-kitab pesantren muncul ungkapan-ungkapan dalam sebuah tema dengan konsep yang dalam bahasa arabnya misalnya kalimat ‘wa qala min ba’di al hukama….” dan juga sejajar dengan kata al-hakim yang mengandung arti bijaksana. Perkataan filsafat dalam bahasa Inggris digunakan istilah philosophy yang juga berarti filsafat yang lazim diterjemahkan sebagai cinta kearifan. Unsur pembentuk kata ini adalah kata philos dan sophos. Philos maknanya gemar atau cinta dan sophos artinya bijaksana atau arif (wise). Menurut pengertiannya yang semula dari zaman Yunani Kuno itu filsafat berarti
- 4. 5 cinta kearifan. Namun, cakupan pengertian sophia ternyata luas sekali,sophia tidak hanya berarti kearifan saja, melainkan meliputi pula kebenaran pertama, pengetahuan luas, kebajikan intelektual, pertimbangan sehat sampai kepandaian pengrajin dan bahkan kecerdikkan dalam memutuskan soal-soal praktis yang bertumpu pangkal pada konsep- konsep aktivitas –aktivitas awal yang disebut pseudoilmiah dalam kajian ilmu. Secara lughowi (bahasa) filsafat berarti cinta kebijaksanaan dan kebenaran. Maksud sebenarnya adalah pengetahuan tentang ada dari kenyataan-kenyataan yang paling umum dan kaidah-kaidah realitas serta hakekat manusia dalam segala aspek perilakunya seperti: logika, etika, estetika dan teori pengetahuan. Maka problem pengertian filsafat dalam hakekatnya memang merupakan problem falsafi yang kaya dengan banyak konsep dan pengertian. Hubungan Filsafat dengan Ilmu Meskipun secara historis antara ilmu dan filsafat merupakan suatu kesatuan, namun dalam perkembangannya mengalami divergensi, dimana dominasi ilmu lebih kuat mempengaruhi pemikiran manusia, kondisi ini mendorong pada upaya untuk memposisikan keduanya secara tepat sesuai dengan batas wilayahnya masing-masing, bukan untuk mengisolasinya melainkan untuk lebih jernih melihat hubungan keduanya dalam konteks lebih memahami khazanah intelektual manusia. Harold H. Titus mengakui kesulitan untuk menyatakan secara tegas dan ringkas mengenai hubungan antara ilmu dan filsafat, karena terdapat persamaan sekaligus perbedaan antara ilmu dan filsafat, disamping dikalangan ilmuwan sendiri terdapat perbedaan pandangan dalam hal sifat dan keterbatasan ilmu, dimikian juga dikalangan filsuf terdapat perbedaan pandangan dalam memberikan makna dan tugas filsafat. Adapun persamaan antara ilmu dan filsafat bahwa keduanya menggunakan berfikir reflektif dalam upaya menghadapi/memahami fakta-fakta dunia dan kehidupan, terhadap hal- hal tersebut baik filsafat maupun ilmu bersikap kritis, berpikiran terbuka serta sangat konsen pada kebenaran, disamping perhatiannya pada pengetahuan yang terorganisir dan sistematis. Sementara itu perbedaan filsafat dengan ilmu lebih berkaitan dengan titik tekan, dimana ilmu mengkaji bidang yang terbatas, bersifat analitis dan deskriptif dalam pendekatannya, ilmu menggunakan observasi, eksperimen dan klasifikasi data pengalaman indra serta berupaya untuk menemukan hukum-hukum atas gejala-gejala tersebut, sedangkan filsafat berupaya mengkaji pengalaman secara menyeluruh sehingga lebih bersifat inklusif dan mencakup hal-hal umum dalam berbagai bidang pengalaman manusia. Filsafat lebih
- 5. 6 bersifat sintetis dan sinoptis dan kalaupun analitis maka analisanya memasuki dimensi kehidupan secara menyeluruh dan utuh. Filsafat lebih tertarik pada pertanyaan kenapa dan bagaimana dalam mempertanyakan masalah hubungan antara fakta khusus dengan skema masalah yang lebih luas, filsafat juga mengkaji hubungan antara temuan-temuan ilmu dengan klaim agama, moral serta seni. Dengan memperhatikan ungkapan di atas nampak bahwa filsafat mempunyai batasan yang lebih luas dan menyeluruh ketimbang ilmu, ini berarti bahwa apa yang sudah tidak bisa dijawab oleh ilmu, maka filsafat berupaya mencari jawabannya, bahkan ilmu itu sendiri bisa dipertanyakan atau dijadikan objek kajian filsafat (Filsafat Ilmu). Namun filsafat dan ilmu mempunyai kesamaan dalam menghadapi objek kajiannya yakni berfikir reflektif dan sistematis, meski dengan titik tekan pendekatan yang berbeda. Dengan demikian, Ilmu mengkaji hal-hal yang bersifat empiris dan dapat dibuktikan, filsafat mencoba mencari jawaban terhadap masalah-masalah yang tidak bisa dijawab oleh Ilmu dan jawabannya bersifat spekulatif, sedangkan Agama merupakan jawaban terhadap masalah-masalah yang tidak bisa dijawab oleh filsafat dan jawabannya bersifat mutlak/dogmatis. MenurutSidi Gazlba (1976), Pengetahuan ilmu bahwa segala sesuatu yang dapat diteliti (riset dan/atau eksperimen) dan batasnya sampai kepada yang tidak atau belum dapat dilakukan penelitian. Pengetahuan filsafat bahwa segala sesuatu yang dapat dipikirkan oleh budi (rasio) manusia yang alami (bersifat alam) dan nisbi dan batasnya ialah batas alam namun, ia juga mencoba memikirkan sesuatu yang diluar alam, yang disebut oleh agama “Tuhan”. Sementara itu Oemar Amin Hoesin (1964) mengatakan bahwa ilmu memberikan kepada kita pengetahuan, dan filsafat memberikan hikmat. Dari sini nampak jelas bahwa ilmu dan filsafat mempunyai wilayah kajiannya sendiri-sendiri. Meskipun filsafat ilmu mempunyai substansinya yang khas, namun merupakan bidang pengetahuan campuran yang perkembangannya tergantung pada hubungan timbal balik dan saling pengaruh antara filsafat dan ilmu, oleh karena itu pemahaman bidang filsafat dan pemahaman ilmu menjadi sangat penting, terutama hubungannya yang bersifat timbal balik, meski dalam perkembangannya filsafat ilmu itu telah menjadi disiplin yang tersendiri dan otonom dilihat dari objek kajian dan telaahannya.
- 6. 7 Definisi Filsafat Ilmu Rosenberg menulis “ Philosophy deals with two sets of questions: First, the questions that science – physical, biological, social, behavioral –. Second, the questions about why the sciences cannot answer the first lot of questions”. Dikatakan bahwa filsafat dibagi dalam dua buah pertanyaan utama, pertanyaan pertama adalah persoalan tentang ilmu (fisika,biologi, social dan budaya) dan yang kedua adalah persoalan tentang duduk perkara ilmu yang itu tidak terjawab pada persoalan yang pertama. Dari narasi ini ada dua buah konsep filsafat yang senantiasa dipertanyakan yakni tentang apa dan bagaimana. Apa itu ilmu dan bagaimana ilmu itu disusun dan dikembangkan. Hal ini sangat mendasar dalam kajian dan diskusi ilmiah dan ilmu pengetahuan pada umumnya. Yang satu terjawab oleh filsafat dan yang kedua dijawab oleh kajian filsafat ilmu. Beberapa penjelasan mengenai filsafat tentang pengetahuan. Dipertanyakanlah hal- hal misalnya : Apa itu pengetahuan? Dari mana asalnya? Apa ada kepastian dalam pengetahuan, atau semua hanya hipotesis atau dugaan belaka? Teori pengetahuan menjadi inti diskusi, apa hakekat pengetahuan, apa unsur-unsur pembentuk pengetahuan, bagaimana menyusun dan mengelompokkan pengetahuan, apa batas-bataspengetahuan, dan juga apa saja yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan. Disinilah filsafat ilmu memfokuskan kajian dan telaahnya. Yakni pada sebuah kerangka konseptual yang menyangkut sebuah system pengetahuan yang di dalamnya terdapat hubungan relasional antara, pengetahuan yang mengetahui (the Knower) dan yang terketahui atau yang diketahui (the known) dan juga antara pengamat (the observer) dengan yang diamati (the observed). Pengertian-pengertian tentang filsafat ilmu, telah banyak dijumpai dalam berbagai buku maupun karangan ilmiah. Filsafat ilmu adalah segenap pemikiran reflektif terhadap persoalan-persoalan mengenai segala hal yang menyangkut landasan ilmu maupun hubungan ilmu dengan segala segi dari kehidupan manusia. Filsafat ilmu merupakan suatu bidang pengetahuan integrative yang eksistensi dan pemekarannya bergantung pada hubungan timbal-balik dan saling-pengaruh antara filsafat dan ilmu. Filsafat ilmu merupakan penerusan pengembangan filsafat pengetahuan. Objek dari filsafat ilmu adalah ilmu pengetahuan. Oleh karena itu setiap saat ilmu itu berubah mengikuti perkembangan zaman dan keadaan. Pengetahuan lama menjadi pijakan untuk mencari pengetahuan baru. Untuk memahami arti dan makna filsafat ilmu, di bawah ini dikemukakan pengertian filsafat ilmu dari beberapa ahli yang terangkum dalam sejumlah literatur kajian Filsafat Ilmu :
- 7. 8 1. Robert Ackerman “philosophy of science in one aspect as a critique of current scientific opinions by comparison to proven past views, but such aphilosophy of science is clearly not a discipline autonomous of actual scientific paractice”. (Filsafat ilmu dalam suatu segi adalah suatu tinjauan kritis tentang pendapat-pendapat ilmiah dewasa ini dengan perbandingan terhadap kriteria-kriteria yang dikembangkan dari pendapat-pendapat demikian itu, tetapi filsafat ilmu jelas bukan suatu kemandirian cabang ilmu dari praktek ilmiah secara aktual. 2. Lewis White Beck “Philosophy of science questions and evaluates the methods of scientific thinking and tries to determine the value and significance of scientific enterprise as a whole. (Filsafat ilmu membahas dan mengevaluasi metode-metode pemikiran ilmiah serta mencoba menemukan dan pentingnya upaya ilmiah sebagai suatu keseluruhan) 3. Cornelius Benjamin “That philosopic disipline which is the systematic study of the nature of science, especially of its methods, its concepts and presuppositions, and its place in the general scheme of intellectual discipines. (Cabang pengetahuan filsafati yang merupakan telaah sistematis mengenai ilmu, khususnya metode-metodenya, konsep-konsepnya dan praanggapan- praanggapan, serta letaknya dalam kerangka umum cabang-cabang pengetahuan intelektual.) 4. Michael V. Berry “The study of the inner logic if scientific theories, and the relations between experiment and theory, i.e. of scientific methods”. (Penelaahan tentang logika interen dari teori-teori ilmiah dan hubungan-hubungan antara percobaan dan teori, yakni tentang metode ilmiah.) 5. Stephen R. Toulmin “As a discipline, the philosophy of science attempts, first, to elucidate the elements involved in the process of scientific inquiry observational procedures, patens of argument, methods of representation and calculation, metaphysical presuppositions, and so on and then to veluate the grounds of their validity from the points of view of formal logic, practical methodology and metaphysics”. (Sebagai suatu cabang ilmu, filsafat ilmu mencoba pertama- tama menjelaskan unsur-unsur yang terlibat dalam proses penyelidikan ilmiah prosedur- prosedur pengamatan, pola-pola perbincangan, metode-metode penggantian dan perhitungan, pra-anggapan-pra-anggapan metafisis, dan seterusnya dan selanjutnya menilai landasan- landasan bagi kesalahannya dari sudut-sudut tinjauan logika formal, metodologi praktis, dan metafisika).
- 8. 9 Dari paparan pendapat para pakar dapat disimpulkan bahwa pengertian filsafat ilmu itu mengandung konsepsi dasar yang mencakup hal-hal sebagai berikut: 1) sikap kritis dan evaluatif terhadap kriteria-kriteria ilmiah 2) sikap sitematis berpangkal pada metode ilmiah 3) sikap analisis obyektif, etis dan falsafi atas landasan ilmiah 4) sikap konsisten dalam bangunan teori serta tindakan ilmiah Selanjutnya John Losee dalam bukunya yang berjudul,A Historical Introduction to the Philosophy of Science, Fourth edition, mengungkapkan bahwa : The philosopher of science seeks answers to such questions as: 1. What characteristics distinguish scientific inquiry from other types of investigation? 2. What procedures should scientists follow in investigating nature? 3. What conditions must be satisfied for a scientific explanation to be correct? 4. What is the cognitive status of scientific laws and principles? Dari ungkapan tersebut terdapat sebuah konsep bahwa tugas dari pemikir filsafat ilmu itu untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan persoalan yang menyangkut: pertama, apa yang menjadi perbedaaan ilmiah karakteristik type masing – masing ilmu ntara satu ilmu dengan ilmu lainnya melalu penelitian.Kedua Prosedur apa yang harus dilakukan secara ilmiah dalam melakukan penelitian atas kenyataan yang terjadi di alam?. Ketiga apa yang mestinya dilakukan dalam mendapatkan penjelasan ilmiah untuk melakukan penelitian dan eksperimen itu ?. Keempat apakah teori itu dapat diambil sebagai konsep dan prinsip- prinsip ilmiah?.Sehingga sketsa filsafat ilmu dapat di gambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut: Level Discipline Subject-matter 2 Philosophyof Science Analysis of the Procedures and Logic of Scientific Explanation 1 Science Explanation of Facts 0 Facts Dengan memperhatikan tabel diatas secara jelas ditampilkan bahwa filsafat ilmu menempati level ke-2 sedangkan ilmu (science) pada level pertama dan semuanya pada satu
- 9. 10 pangkal pokok yakni fakta (kenyataan) menjadi basis utama bangunan segala disiplin ilmu. Jika ilmu itu menjelaskan Fakta sementara filsafat ilmu itu subyek materinya adalah menganalisa prosedur-prosedur logis dari ilmu (Analysis of the Procedures and Logic of Scientific Explanation). Tujuan Filsafat Ilmu 1. Filsafat ilmu sebagaisarana pengujian penalaranilmiah Maksudnya bahwa orang menjadi kritis dan cermat terhadap kegiatan ilmiah. Maksudnya seorang ilmuwan harus memiliki sikap kritis terhadap bidang ilmunya sendiri, sehingga dapat menghindarkan diri dari sikap solipsistik, menganggap bahwa hanya pendapatnya yang paling benar. 2. Filsafat ilmu merupakan usaha merefleksi, menguji, mengkritik asumsi dan metode keilmuan. Sebab kecenderungan yang terjadi di kalangan ilmuwan modern adalah menerapkan suatu metode ilmiah tanpa memperhatikan struktur ilmu pengetahuan itu sendiri. Satu sikap yang diperlukan disini adalah menerapkan metode ilmiah yang sesuai atau cocok dengan struktur ilmu pengetahuan, bukan sebaliknya. Metode hanya saran berpikir, bukan merupakan hakikat ilmu pengetahuan. 3. Filsafat ilmu memberikan pendasaran logisterhadap metode keilmuan. Setiap metode ilmiah yang dikembangkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan rasional, agar dapat dipahami dan dipergunakan secara umum. Semakin luas penerimaan dan penggunaan metode ilmiah, maka semakin valid metode tersebut. Pembahasan mengenai hal ini dibicarakan dalam metodologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang cara-cara untuk memperoleh kebenaran. 4. Mendalami unsur-unsur pokok ilmu, sehingga secara menyeluruh kita bisa memahami, sumber, hakekat, dan tujuanilmu.
- 10. 11 5. Memahami sejarah pertumbuhan, perkembangan dan kemajuan ilmu di berbagai bidang, sehingga kita mendapat gambaran tentang proses ilmu kontemporer secra historis. 6. Menjadi pedoman bagi para dosen dan mahasiswa dalam mendalami studi di perguruan tinggi, terutama untuk membedakan persoalan yang ilmiah dan non ilmiah. 7. Mendorong para calon ilmuwan dan ilmuwan untuk konsisten dalam mendalami ilmu dan mengembangkannya. 8. Mempertegas bahwa dalam persoalan sumber dan tujuan antara ilmu dan agama tidakada pertentangan. 9. Memahamidampakkegiatan ilmiah (penelitian) yang berupa teknologiilmu Misalnya alat yang digunakan oleh bidang medis, teknik, komputer dengan masyarakat yaitu berupa tanggung jawab dan implikasi etis. Contoh dampak tersebut misalnya masalaheuthanasia dalam dunia kedokteran masih sangat dilematis dan problematik, penjebolan terhadap sistem sekuriti komputer, pemalsuan terhadap hak atas kekayaaan intelektual (HAKI) , plagiarisme dalam karya ilmiah. Adapun manfaat dari mempelajari filsafat ilmu, yaitu : 1. Menyadarkan seorang ilmuwan agar tidak terjebak ke dalam pola pikir “menara gading”yakni hanya berpikir murni dalam bidangnya tanpa mengaitkannya dengan kenyataan yang ada di luar dirinya. Padahal setiap aktivitas keilmuwan nyaristidak dapat dilepaskan dalam konteks kehidupan sosial kemasyarakatan. Jadi filsafat ilmu diperlukan kehadirannya di tengah perkembangan IPTEK yang ditandai semakin menajamnya spesialisasi ilmu pengetahuan. Sebab dengan mempelajari filsafat ilmumaka para ilmuwan akan menyadari keterbatasan dirinya dan tidak terperangkap ke dalam sikap arogansi intelektual. Hal yang diperlukan adalah sikap keterbukaan diri di kalangan ilmuwan sehingga mereka dapat saling menyapa dan mengarahkan seluruh potensi keilmuan yang dimilikinya untuk kepentingan umat manusia.
- 11. 12 2. Mengembangkan ilmu, teknologi dan perindustrian dalam batasan nilai ontologis. Melalui paradigma ontologism diharapkan dapat mendorong pertumbuhan wawasan spiritual keilmuan yang mampu mengatasi bahaya sekularisme segala ilmu. 3. Mengembangkan ilmu, teknologi dan pertindustrian dalam batasan nilai epistemologis. Melalaui paradigma epistemologis diharapkan akan mendorong pertumbuhan wawasan intelektual keilmuan yang mampu membentuk sikap ilmiah. 4. Mengembangkan ilmu, teknologi dan perindustrian dalam batasan akiologi. Melalui paradigma aksiologis diharapkan dapat menumbuhkembangkan nilai-nilai etis, serta mendorong perilaku adil dan membentuk moral tanggung jawab. Segala macam ilmu dan teknologi dipertanggung jawabkan bukan unntuk kepentingan manusia, namun juga untuk kepentingan obyek semua sebagai sumber kehidupan. 5. Menambah pandangan dan cakrawala yang lebih luas agar tidak berpikir dan bersikap sempit dan tertutup. 6. Menjadikan diri bersifat dinamis dan terbuka dalam menghadapi berbagai problem. 7. Menyadari akan kedudukan manusia baik sebagai pribadimaupun dalam hubungannya dengan orang lain, alam sekitar,dan Tuhan YME. 8. Filsafat ilmu bermanfaat untuk menjelaskan keberadaan manusia di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan alat untuk membuat hidup menjadi lebih baik 9. Filsafat ilmu bermanfaat untuk membangun diri kita sendiri dengan berpikir secara radikal (berpikir sampai ke akar-akarnya), kita mengalami dan menyadari keberadaan kita. 10. Filsafat ilmu memberikan kebiasaan dan kebijaksanaan untuk memandang dan memecahkan persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang hidup secara dangkal saja, tidak mudah melihat persoalan-persoalan, apalagi melihat pemecahannya. 11. Filsafat ilmu memberikan pandangan yang luas, sehingga dapat membendung egoisme dan ego-sentrisme (dalam segala hal hanya melihat dan mementingkan kepentingan dan kesenangan diri sendiri). 12. Filsafat ilmu mengajak untuk berpikir secara radikal, holistik dan sistematis, hingga kita tidak hanya ikut-ikutan saja, mengikuti pada pandangan umum, percaya akan setiap semboyan dalam surat-surat kabar, tetapi secara kritis menyelidiki apa yang dikemukakan orang, mempunyai pendapat sendiri, dengan cita-cita mencari kebenaran.
- 12. 13 13. Filsafat ilmu memberikan dasar-dasar, baik untuk hidup kita sendiri (terutama dalam etika) maupun untuk ilmu-ilmu pengetahuan dan lainnya, seperti sosiologi, ilmu jiwa, ilmu mendidik, dan sebagainya. 14. Filsafat ilmu bermanfaat sebagai pembebas. Filsafat bukan hanya sekedar mendobrak pintu penjara tradisi dan kebiasaan yang penuh dengan berbagai mitos dan mite, melainkan juga merenggut manusia keluar dari penjara itu. Filsafat ilmu membebaskan manusia dari belenggu cara berpikir yang mistis dan dogma. 15. Filsafat ilmu membantu agar seseorang mampu membedakan persoalan yang ilmiah dengan yang tidak ilmiah. Pentingnya Belajar Filsafat Ilmu Bagi Mahasiswa Belajar filsafat ilmu bagi mahasiswa sangat penting, beberapa manfaat yang dapat dirasakan, antara lain : 1. Dengan mempelajari filsafat ilmu diharapkan mahasiswa semakin kritis dalam sikap ilmiahnya. Mahasiswa sebagai insan kampus diharapkan untuk untuk berpikir kritis terhadap berbagai macam teori yang dipelajarinya di ruang kuliah maupun dari sumber-sumber lainnya. 2. Mempelajari filsafat ilmu mendatangkan kegunaan bagi para mahasiswa sebagai calon ilmuwan untuk mendalami metode ilmiah dan untuk melakukan penelitian ilmiah. Dengan mempelajari filsafat ilmu diharapkan mereka memiliki pemahaman yang utuh mengenai ilmu dan mampu menggunakan pengetahuan tersebut sebagai landasan dalam proses pembelajaran dan penelitian ilmiah. 3. Mempelajari filsafat ilmu memiliki manfaat praktis. Setelah mahasiswa lulus dan bekerja, mereka pasti berhadapan dengan berbagai masalah dalam pekerjaannya. Untuk memecahkan masalah diperlukan kemempuan berpikir kritis dalam menganalisis berbagai hal yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi. Dalam konteks inilah pengalaman mempelajari filsafat ilmu diterapkan. 4. Membiasakan diri untuk bersikap logis-rasional dalam Opini & argumentasi yang dikemukakan. 5. Mengembangkan semangat toleransi dalam perbedaan pandangan (pluralitas). Karena para ahli filsafat tidak pernah memiliki satu pendapat, baik dalam isi, perumusan permasalahan maupun penyusunan jawabannya. 6. Mengajarkan cara berpikir yang cermat dan tidak kenal lelah.
- 13. 14 DAFTAR PUSTAKA Alhelya, Manfaat Belajar Filsafat. http://alhelya746.blogspot.com/2013/05/manfaat-belajar- filsafat.html. Muhlisin. Filsafat dan Filsafat Ilmu Mustansyir, Rizal. Filsafat Ilmu. Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2001. Putra, Uhar Suharsa. 2004. Filsafat Ilmu Panca Budi, Manfaat dan Makna Filsafat Ilmu.
- 14. 15 B. MAKALAH SEJARAH PERKEMBANGAN FILSAFAT ILMU PEMBAHASAN A. Perkembangan AwalPemikiran Filsafat Ilmu Periode Filsafat Yunani merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah peradaban manusia karena pada waktu ini terjadi perubahan pola fikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Pola fikir mitosentris adalah pola fikir masyarakat yang sangat mengandalkan mitos untuk menjelaskan fenomena alam seperti gempa bumi dan pelangi. Perubahan pola fikir itu terlihat sederhana tetapi implikasinya tidak sesederhana yang dibayangkan kerena selama ini alam ditakuti dan dijauhi kemudian di dekati bahkan dieksploitasi. Manusia yang dulunya pasif dalam menghadapi fenomena alam menjadi lebih proaktif dan kreatif sehingga alam dijadikan obyek penelitian dan pengkajian. Dari proses inilah kemudian ilmu berkembang dari rahim Filsafat, yang akhirnya kita nikmati dalam bentuk teknologi. Karena itu periode perkembangan Filsafat Yunani merupakan entri poin untuk memasuki peradaban baru umat manusia. Terjadinya perubahan yang besar dalam lapangan pengetahuan empiris yang berdasarkan sikap receptive attitude mind. Bangsa Yunani tak dapat menerima empirirs tersebut secara pasif-reseptif karena bangsa Yunani memiliki sikap jiwa: “an inguiring attitude, an inguiring mind”. Dengan demikian lahirlah pengetahuan filsafat yang pada zaman itu mempunyai arti yang lebih luas dari pada sekarang, yaitu meliputi semua bidang ilmu sebagai induk ilmu pengetahuan (mater scientarum). Seperti yang kita ketahui bahwa secara bahasa Filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan/ kebenaran/ pengetahuan. Mencintai pengetahuan adalah awal proses manusia mau menggunakan daya fikirnya, sehingga dia mampu membedakan mana yang riil dan mana yang ilusi. Orang Yunani awalnya sangat percaya pada dongeng dan takhayul, tetapi lama kelamaan, terutama setelah mereka mampu membedakan yang riil dan yang ilusi, mereka mampu keluar dari kungkungan mitologi dan mendapatkan dasar pengetahuan ilmiah. Inilah titik awal manusia menggunakan rasio untuk meneliti dan sekaligus mempertanyakan dirinya
- 15. 16 dan alam jagat raya. Karena manusia selalu berhadapan dengan alam yang begitu luas dan penuh misteri, timbul rasa ingin mengetahui rahasia alam itu. Lalu timbul pertanyaan dalam pikirannya; dari mana datangnya alam ini, bagaimana kejadiannya, begaimana kemajuannya dan kemana tujuannya? Pertanyaan semacam inilah yang selalu menjadi pertanyaan dikalangan filosof Yunani, sehingga tidak heran kemudian mereka disebut dengan filosof alam karena perhatiannya yang begitu besar kepada alam. Filosof alam ini juga disebut filosof pra Socrates, sedangkan Socrates dan setelahnya disebut dengan filosof pasca Socrates yang tidak haya mengkaji tentang alam, tetapi manusia dan perilakunya. Ciri-ciri pemikiran filsafat barat abad petengahan antara lain: – Cara berfikirnya dipimpin oleh gereja. – Berfilsafat di dalam lingkungan ajaran Aristoteles. – Berfilsafat dengan pertolongan Augustinus dan lain-lain. Masa abad pertengahan ini juga dapat dikatakan sebagai suatu masa yang penuh dengan upaya mengiringi manusia ke dalam kehidupan sistem kepercayaan yang picik dan fanatik, dengan menerima ajaran gereja secara membabi buta. Karena iru paerkembangan ilmu pengetahuan terhambat. Masa ini penuh dengan dominasi gereja, yang tujuannya untuk membimbing umat ke arah hidup yang saleh. Namun, di sisi lain, dominisi gereja ini tanpa memikirkan martabat dan kebebasan manusia yang mempunyai perasaan, pikiran, keinginan, dan cita-cita untuk menentukan masa depannya sendiri. Zaman Abad Pertengahan ditandai dengan tampilnya para teolog di lapangan ilmu pengetahuan. Para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Semboyang yang berlaku bagi ilmu pada masa ini adalah ancilla theologia atau abdi agama. Namun demikian harus diakui bahwa banyak juga temuan bidang ilmu yang terjadi pada masa ini. Periode Abad Pertengahan mempunyai perbadaan yang mencolok dengan abad sebelumnya. Perbedaan itu terutama terletak pada dominasi agama. Timbulnya agama Kristen yang dijarkan oleh Nabi Isa as. pada permulaan Abad Masehi membawa perubahan besar terhadap kepercayaan keagamaan. Agama Kristen menjadi problem kefilsafatan karena mengajarkan bahwa wahyu Tuhanlah yang merupakan kebenaran yang sejati. Hal ini berbeda dengan pandangan Yunani Kuno yang mengatakan bahwa kebenaran dapat dicapai oleh kemampuan akal. Mereka belum mengenal adanya wahyu.
- 16. 17 Mengenai sikap terhadap pemikiran Yunani ada dua: 1. Golongan yang menolak sama sekali pemikiran Yunani, karena pemikiran Yunani merupakan pemikiran orang kafir, karena tidak mengakui wahyu. 2. Menerima filsafat Yunani yang mengatakan bahwa karena manusia itu ciptaan Tuhan, kebijaksanaan manusia berarti pula kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan. Mungkin akal tidak dapat mencapai kebenaran yang sejati maka akal dapat dibantu oleh wahyu. Tokoh yang hidup pada masa abad modern beserta pemikirannya. Tidak dapat dipungkiri, zaman filsafat modern telah dimulai secara historis, zaman modern dimuali sejak adanya krisis zaman pertengahan selama dua abad (abad ke-14 dan ke- 15), yang ditandai dengan munculnya gerakan Renaissance. Renaisance berarti klahiran kembali, yang mengacu kpaa gerakan keagamaan dan kemasyarakatan yang bermula di Italia (pertengahan abad ke-14) tujuan utamanya adalah merealisasikan kesempatan pandangan hidup Kristiani dengan mengaitkan filsafat Yunani dengan ajaran agama Kristen. Selain itu, juga dimaksudkan untuk mempersatukan kembal gereja yang terpecah-pecah. Di samping itu, para humanis bermaksud meningkatkan suatu perkembangan yang harmonis dari keahlian- keahian dan sifat-sifat alamiah manusia dengan mengupayakan kepustakaan yang baik dan mengikuti kultur klasik. Renaissance akan banyak memberikan segala aspek realitas. Perhatian yang sungguh-sungguh atas segala hal yang konkret dalam lingkup alam semesta, manusia, kehidupan masyarakat, dan sejarah. Aliran yang menjadi pendahuluan ajaran filsafat modern ini didasarkan pada suatu kesadaran atas yang individual dan yang konkret. Zaman modern ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pegetahuan pada zaman modern sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman renaissance. Seperti Rene descartes, tokoh yang terkenal sebagai bapak filsafat modern. Rene Descartes juga seorng ahli ilmu pasti. Penemuannya dalam ilmu pasti adalhsistem koordinat yang terdiri atas dua garis lurus X dan Y dalam bidang datar. Isaac Newton dengan temuannya teori gravitasi. Charles Darwin dengan teorinya struggle for life (perjuangan untuk hidup). Dalam era modern, yang kemudian dilanjutkan dengan era filsafat abad ke-20, muncullah berbagai aliran pemikiran: Rasionalsme, Empirisme, Kristisisme, Idealisme,
- 17. 18 Positivisme, Evolusionisme, Materialisme, Neo-Kantianisme, Pragmatisme, Filsafat Hidup, Fenomenologi, Eksistensialisme, dan Neo-Thomisme. a) Rasionalisme Rene Descartes yang mendirikan aliran rasionalisme berpendapat bahwa sumber pengetahuan yang dapat dipercaya adalah akal. Hanya pengetahuan yang diperoleh lewat akallah yang mmenuhi syarat yang dituntut oleh semua ilmu pengetahuan ilmiah. Dengan akal dapat diperoleh kebenaran dengan metodee deduktif, seperti yang dicintohkan dalam ilmu pasti. Ia menemukan ilmu pasti ialah sistem koordinat yang terdiri atas du garis lurus X dan Y dalam bidang datar. Garis X letaknya horizotal dan disebut axis atau simbol X, sedangkan garis Y letaknya tegak lurus sumbu X. Karena sistem tersebut didasarkan pada dua garis lurus yang berpotongan tegak lurus, maka sistem koordinat itu dinamakan orthogonal coordinate system. Kedudukan tiap titik dalam bidang tersebut diproyeksikan dengan garis- garis lurus pada sumbu X dan sumbu Y. Dengan demikian kedudukan tiap titik potong kedua sumbu menyusuri sumbu-sumbu tadi. Latar belakang munuclnya rasionalisme adalah keinginan untuk membebaskan diri dari segala pemikiran tradisional (skolastik), yang pernah diterima, tetapi ternyata tidak mampu menangan hasil-hasil ilmu pengetahuan yang dipahami. Apa yang ditanam Aristoteles dalam pemikiran saat itu juga masih dipengaruhi oleh khayalan-khayalan. b) Empirisme – Thomas Hobbes Ia seorang ahli inggris lahir di Malmesbury. Pada usia 15 tahun ia pergi ke Oxford untuk belajar logika Skolistik dan fisika, yang ternyata gagal, karena ia tidak bermiat sebab guruna beralih Aristotelian. Sumbangan yang besar sebagai ahli pikir adalah suatu sistem materialistis yang besar, termaksuk juga perikehidupan organis dan rohaniah. Dalam bidang kenegaraan ia mengemukakan teori Kontak Sosial. Pendapatnya adalah bahwa ilmu filsafat adlah suatu ilmu pengetahuan yang sifatnya umum. Menurutnya filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan tetang akibatakibat atau tentang gejala-gejala yang diperoleh dari sebabnya. Sasaran filsafat adalah fakta, yaitu untuk mencari sebab-sebabnya. Segala yang ada ditentukan oleh sebab, sedangkan prosesnya sesuai dengan hukum ilmu pasti/ilmu alam. Namanya sangat terkenal karena teorinya tentang Kontrak Sosial, yaitu manusia mempunyai
- 18. 19 kecenderungan untuk mempertahaakan diri. Apabila setiap orang mempunyai kecenderungan demikian, maka pertentangan, pertengkaran atau perang total tak dapat dihindari. – John Locke Ia dilahirkan di Wrington, dekat Btistol, Inggris. Di samping ahli hukum, ia juga menyukai filsafat dan teologi mendalami ilmu kedokteran dan penelitian kimia. Dalam mencapai kebenaran, sampai seberapa jauh (bagaimana) manusia memakai kemampuanya. Dalam penelitiannya ia memeakai istilah sensation dan reflection Sensation adalah suatu yang dapat berhubungan dengan dunia luar, tetapi manusia tidak dapat mengerti dan meraihnya. Sementara itu, reflection adalah pengenalan intuitif yang memberikan pengetahuan kepada manusia, yang sifatnya lebih baik daripaada sensation. Tiap-tiap pengetahuan yang diperoleh manusi aterdiri dari sensation dan relection. Walau;oun demikia, manusia harus mendahulukan sensation. Mengapa demikian? Karen jiwa manusia di saaat dilahirkan putih bersih (tabula rasa) yaitu jiwa kosong bagaikan kertas putih yang belum tertulis. Tisak ada sesuatu yang dlam jiwa yang dibawa sejak lahir, melainkan yang membentuk jiwa seseorang. c) Kristisisme – Isaac Newton Memberikan dasar-dasar berfikir dengan induksi, yaitu pemikiran yang bertitik tolak pada gejala-gejala dan mengembalikan kepada dasar-dasar yang sifatnya umum. Untuk itu dibutuhnkan analisis. Gerakan ini dimulai di Inggris, kemudian ke Prancis, an sekanjutnya menyebar seluruh Eropa, terutama ke Jerman. Di Jerman pertentangan antara rasionalisme denga empirisme semakin berlanjut. Masing-masing berebut otonomi. Kemudian timbul masalah, siapa yang sebenarnya dikatakan sebagai sumber pengetahuan? Apakah pengetahauan yang benar itu lewat rasio atau empiri? Berperan dalam ilmu pengetahuan modern terutama penemuan dalam tiga bidang, yaitu teori Gravitasi, perhitungan Calculus, dan optika. – ImmanuelKant Ia mencoba menyelsaikan persoalan di atas. Pada awalnya, Kant mengikuti rasionalisme, tetapi kemudian terpengaruh oleh empirisme (Hume). Walaupun demikian, Kant tidak begitu mudah menerimanya karena ia mengetahui bahwa empirisme terkadang
- 19. 20 skep-tisisme. Untuk itu, ia tetap mengakui kebenaran ilmu, dan dengan akal manusi akan dpat mencapai kebenaran. Akhirnya, Kant menakui peranan akal dan keharusan empiri, kemudian dicobanya mengadakan sintesis. Walaupun semua pengetahuan bersumber pada akal (rasinalisme), tetapi adanya pengertian timbul dari benda (empirisme). Ibarat burung terbang harus memunyai sayap (rasio) dan udara (empiri). Jadi, metode berfikirnya disebut metode kritis. Walaupun didasarkan diri pada nilai yang tinggi dari akal, tetapi ia tidak mengingkari adanya persoalan-[ersoalan yang melampaui akal. Sehngga akal mengenal bats-batasnaya. Karena itu aspek irrasionalitas dari kehidupan dpat diterima kenyataanya. d) Idealisme I.G Fichte (1762 – 1814), F.W.J. Scheling ( 1775-1854), G.W.T. Hengel (1770-1831), Schopenhauer (1788 – 1860). Apa yang dirintis olej Kant mencapai puncak perkembangannya pada Hegel. Hegel lahir di Struttgart, Jerman. Pegaruhnya begitu besar sampai luar Jerman. Menjadi profesor ilmu filsafat samapai meninggal. Setelah ia mempelajari emikiran Kant, ia tidak merasa puas tentang ilmu pengetahuan yang dibatasi secara kritis. Menurut pendapatnya, segala peristiwa di sunia hanya dapat dimengerti jika suatu syarat dipenuhi, yaitu jika peristiwa-peristiwa itu sudah secara otomatis mengandung penjelasan-penjelasan. Ide yang berfikir itu sebenarnya adla gerak yang menimbulkan gerak lain. Artinya, gerak yang menimbulkan tesis, kemudian menimbulkan anti tesis (gerak yang bertentangan), kemudia timbul sintesis yang merupakan tesis baru, yang nantinya menimbulkan antitesis da seterusnya. e) Positivisme – August Comte Ia lahir di Montpellier, Perancis. Sebuah karyanya dalah Cours de philosophia positive ( Kursus tentang filsafat tahap positif ) dan berjasa dala menciptakan ilmu sosiologi. Menurut pendapatnya, perkembangan pemikiran manusia berlangsung dlam tiga tahap: tahap teologis. Tahap metfisis, dan tahap ilmiah/positif. Tahap teologis, manusia mengarahkan pandangan kepada hakikat batiniah (sebab pertama). Di sini manusia percaya kepada kemungkinan adanya sesuatu yang mutlak. Artinya, di balik setiap kejadian tersirat adanya maksud tertentu. Pada tahap metafisis manusia hanya sebagai tujuan pergeseran dari tahap teologis. Sifat yang khas adlah kekuatan yang tadinya bersifat adi kodrati, diganti dengan kekuatan-kekuatan yang mempunyai pengertian abstrak, yang diitegrasikan dengan alam.
- 20. 21 Pada tahap ilmiah/positif, manusia telah mulai mengatahui dn sdar bahwa upaya pengenalan teologis dan metafis tidak da gunanya. Sekrang manusia berusaha mencari hukum-hukum yang bersal dari fakta-fakta pengamatan denan memakai akal. Tahap-tahap tersebut berlaku pad setap individu (dalam perkembangan rohami) juga di bidang ilmu pngetahuan. Pada akhir hidupnya, ia brupaya untuk membangun agama baru tanpa teologi atas dasar filsafat positifnya. Agama baru tanpa teologi ini menggunakan akal dan mendambakan kemanusiaan dengan semboyang “Cinta sebagai prinsip, teratur sebagai basis, kmajauan sebagai tujuan”. f. Evoluisme Pada tahun 1838 membaca bukunya Malthus An Essay on the Princple of Population. Buku tersebut memberikan inspirasi kepada Darwin untuk membentuk kerangka nerfikir dari teorinya. Menurut Malthus, manusia akan cenderung meningkat jumlahnya (deret ukur), di atas batas bahan-bahan makanan (deret ukur). Degngan demikian, Darwin memberikn kesimpulan bahwa untuk mengatasi hal tersebut manusia harus bekerja sama, harus berjuang di antara sesamanya untuk mempertahankan hidupnya. Karena itu hanya hewan yang ulet yang mampu untuk menyelesaikan diri dengan iklim sekitarnnya. Dalam pemikiranya, ia mengajukan konsepnya tentang perkembangan tentang segala sesuatu termaksud manusia yang diatur oleh hukum-hukum mekanik, yaitu survival of the fittest dan struggle for life. Pada hakikatnya antra bintang dan manusia dan benda pa pun tidak ada bedanya. Dimungkinkan terdapat perkembangan pada masa yang akan datang lebi sempurna. Dalam pemikirannya, Darwin tidak melahirkan sistem filsafat, tetapi pada ahli pikir berikutnya (Herbert Spencer) berfilsafat berdasarkan pada evolusionisme. g. Materialisme Munculnya Positivisme dan Evolusionisme menambah terbukanya pintu pengingkaran terhadap aspek kerohanian. Julien de La mettrie mengemukakan pemikirannya bahwa bintang dan manusia tidak ada bedanya, karena semuanya dianggap sebagai mesin. Buktinya, bahan (badan) tanpa jiwa mungkin hidup (bergerak), sedangkan jiwa tanpa bahan (badan) tidak mungkin ada. Jantung katak yang dikeluarkan jiwa tanpa bahan (badan) tidak mungkin ada. Jantung katak yang dikeluarkan dari tubuh katak masih berdenyut (hidup) walau beberapa saat saja. Seorang tokoh lagi (Materialisme Alam) adalah Lugwig Feueurbach sebagai pengikut Hegel, mengemukakan pendapatnya, bahwa baik pengetahuan
- 21. 22 maupun tindakan berlaku adagium, artinya terimalah dunia yang ada, bila menolak agama/metafisika. Satu-satunya asa kesusilaan adalh keinginan untuk mendapatkan kebahagiaan. Dan untuk mencari kebahagiaan manusia harus ingat akan sesamanya. Dari Mmaterialisme Histori/diaalektis, yaitu Karl Marx, nama lengkapnya Karl Heinrich Marx, dilahirkan di Trier, Prusia, Jerman. Sewaktu menjadi mahasiswa ia terpengaruh oleh ajaran Hegel dan dapat mencapai gelar doktor dalam bidang filsafat. Di kala ia berkawan dengan Bruno Bauer ia mendapatkan kekecewaan, tetapi setelah berkawan dengan Friedrich Engels di Paris, maka dengan kawanya itulah ia (tahun 1848) menyusun Manifesto Komunist. Setelah itu, ia mejadi buronan politik dan diusir dan dipenjara di London, sampai meninggal dunia. Ia meninggalkan warisan sebuah karya terbesarnya, Das Kapital, yang terbit tahun 1867. Menurut pendapatnya, tugas seorang filosof bukan untuk menerangkan dunia, tetapi untuk mengubahnya. Hidu manusia itu ternyata ditentukan oleh keadaan ekonomi. Dari segala hasil tindakannya: ilmu, seni, agama, kesusilaan, hukum, pilotik – semuanya itu hanya endapan dari keadaan itu, sedangkan keadaan itu sendiri ditentukan benar-benar dalam sejarah. h. Neo-Kantianisme Setelah Materialisme pengaruhnya merajalela, para murid Kant mengadakan gerakan lagi. Banyak filosof Jerman yang tidak puas terhadap Materalisme, Positivisme dan Materialisme. Gerakan ini di sebut Neo-Kantianisme. Tokohnya antara lain Wilhelm Windlband (1848 – 1915), Herman Cohen (1842 – 1918), Paul Natrop (1854 – 1924), Heinrich Reickhart (1863 – 1939). Herman Cohen memberika titik tolak pemikiran mengemukakan bahwa keyakinan padsa otoritas akal manusia untuk mencipta. Mengapa demikian, karena segala sesuatu itu baru dikatakan ‘ada’ apabila terlebih dahulu dipirkan. Artikan, ‘ada’ dan ‘dipikirkan’ adalah sama sehingga apa yang dipikirkan akan melahirkan isi pikiran. Tuhan, menurut pendapatnya, bukan sebagai person, tetapi sebagai cita-cita dari seluruh perilaku manusia. i. Pragmatisme Tokohnya William James lahir di New York, memperkenalkan ide-idenya tentang pragmisme kepada dunia. Ia ahli dalam bidang seni, psikologi, anatomi, fisiologi, dan filsafat. Pemikiran filsafatnya lahir karena dalam sepanjang hidupnya mengalami konflik antara pandangan ilmu pengetahuan dengan pandangan agama, ia beranggapan, bahwa masalah
- 22. 23 kebenaran tenang asal/tujuan dan hakikat bagi orang Amerika terlalu teoristis. Ia mnginginkan hasil-hasil yang konkert. Dengan demikian, untuk mengetahui kebenaran dari ide atau konsep haruslah diselidiki konsekuensi-konsekuensi praktisnya. j. FilsafatHidup Tokohnya adalah Henry Bergson. Pada mulanya ia belajar matematika dan fisika. Karena ia mempunyai kepandaian menganalisis, muncul msalah baru dalam pemikiranya. Ia diharapkan pada masalah metafisika yang tidak tampak dan tempatnya di belakang lmu pengetahuan. Itulah yang menyebabkan ia terjun ke dalam didang filsafat. Pemikiranya, alam semesta ini merupakan suatu organisme yang kreatif, tetapi perkembangannya tidak sesuai dengan implikasi logis. Perkembanganya seperti meletup-meletup dalam keadaan tidak sama sehingga melahirkan akibat-akibat dengan spektrum yang baru. Pemikiran filsafat Henry Bergson ini sebagai reaksi dari Positivisme, Materialisme, Subjektivisme, Relativisme. Kemudian ia mengupayakan, dengan melalui yang positif (ilmu) tersebut untuk menyalami yang mutlak dalam pengetahuan metafisis. Ia mempertahankan kebebasan dan kemerdekaan kehendak. John Dewey, ia lahir di Brulington, dan sekaligus menjadi guru filsafat. Pemikirannya, tugas filsafat adalah memberikan pengarahan dalam tindakan hidup manusia. Untuk itu, filsafat tidak boleh berada dalam pemikiran metafisika yang tidak ada manfaatnya. Dengan demikian, flsafat harus berasaskan pada pengalaman, kemudian mengadakan penyelidikan dan mengolahnya secara kritis sehngga filsafat akan mampu memberikan suatu sistem norma-norma dan nilai-nilai. k. Fenomenologi Fenomenologi berasal dari kata fenomen yang artinya gejala, yaitu suatu hal yang tidak nyata dan semua. Dan yan lebih penting dalam filsafat fenomenologi sebagai sumber berfikir yang kritis. Pemikiran yang demikian besar pengaruhnya di Eropa dan Amerika antara tahun 1920 hingga tahun 1945 dalam bidang ilmu pengetahuan positif. Tokohnya: Edmund Husserl (1839 – 1939), dan pengikutnya Max Scheler (1874 – 1928). Edmund Husserl lahir di Wina. Ia belajar ilmu alam, ilmu falak, matematika, kemudian filsafat. Akhirnya menjadi guru besar di Helle, Gottingen, Freiburg. Pemikiranya, bahwa objek/benda harus diberi kesempatan untuk berbicara, yaitu dngan cara deskriptif fenomenologis yang didukung oleh metode deduktif. Tujuannya adalah untuk melihat hakikat gejala-gejala secara intuitif. Sedangkan metode deduktif artinya mengkhayalkan gejala-gejala dlam berbagai
- 23. 24 macam yang berbeda. Sehingga akan terlihat batas invariable dalam situasi yang berbeda-bda. Sehingga akan muncul unsur yang tidak berubah-ubah yaitu hakikat. Inilah yang dicarinya dalam metode variasi eidetis. l. Eksistensialisme Kata Eksistensialisme berasal dari kata eks = ke luat, dan sistensi atau sisto = berdiri, menempatkan. Eksistensialisme merupakan alran filsafat yang memandang berbagai gejala dengan berdasar pda eksistensiny. Artinnya, bagaimana manusia berada (bereksistensi) dalam dunia. Pelopornya adalah Soren Kierkegaard (1813 – 1855), Martin Heidegger, J.P.Sartre, Karl Jaspers, Gabriel Marcel. Pemikiran Soren Kierkegaard mengemukakan bahwa kebenaran itu tidak berada pada suatu sistem yang umum tetapi berada dalam eksistensi yang individual, yang konkret. Karena, eksistensi manusia penuh dengan dosa, hanya iman kepada Kristus sajalah yang dapat mengatasi perasaan bersalah karena dosa. m. Neo-Thomisme Pada pertengahan abad ke-19, di tengah-tengah gereja Katolik banyak penganut paham Thomisme, yaitu aliran yang mengikuti Paham Thomas Aquinus. Pada mulanya di kalangan gereja terdapat semacam keharusan untuk mempelajari ajaran tersebut. Kemudian, akhirnya menjadi suatu paham Thomisme, yaitu pertama, paham yang menganggap bahwa ajara homas sudah sempurna. Tugas kita adalah membrikan tafsir sesuai dengan keadaan zaman. Kedua, paham yang menganggap bahwa walaupun ajaran Thomas telah sempurna, tetapi masih terdapat hal-hal yang pada suatu saatbelum dibahas. Oleh karena itu, sekarang perlu diasakan penyesuaian sehubungan dengan perkembangan ilmu pegetahuan. Ketiga, paham yang mengganggap bahwa Thomas harus diikuti, akan tetapi tidak boleh beranggapa bahwa ajaranya betu-betul sempurna. Perkembangan Filsafat ilmu di zaman Islam Sebelum di uaraikan sejarah dan perkembangan ilmu dalam Islam, ada baiknya diuraikan sedikit tentang pandangan Islam terhadap ilmu. Hal ini penting untuk diketahui karena menjadi landasan bagi pengembangan ilmu di sepanjang sejarah kehidupan umat Islam. Sejak awal kelahirannya, Islam sudah memberikan penghargaan yang begitu besar kepada ilmu. Sebagaimana sudah diketahui, bahwa Muhhammad saw ketika diutus oleh Allah sebagai Rasul, hidup dalam masyarakat yang terbelakang dimana paganism tumbuh
- 24. 25 menjadi sebuah identitas yang melekat pada masyarakat Arab pada masa itu. Kemudian Islam datang menawarkan cahaya penerang yang mengubah masyarakat Arab jahiliyyah menjadi masyarakat yang berilmu dan beradab. Kalau dilacak akar sejarahnya, pandangan Islam tentang pentingnya ilmu tumbuh bersamaan dengan munculnya Islam itu sendiri. Ketika rasulullah menerima wahyu yang pertama yang mula-mula diperintahkan kepadanya adalah “membaca”. Dengan demikian, al- Qur'an dan hadis menjadi sumber ilmu yang dikembangkan oleh umat Islam dalam spectrum yang seluas-luasnya. Selanjutnya kita akan masuk kedalam inti pembahasan, yaitu tentang sejarah dan perkembangan ilmu dalam Islam. Untuk memudahkan pemahaman kita penulis mencoba membagi sejarah perkembangan ilmu dalam Islam dalam beberapa zaman, seperti uraian berikut: 1.Penyampaian Ilmu Dalam FilsafatYunaniKe Dunia Islam. Pengalihan pengetahuan ilmiah dan Filsafat Yunani ke dunia Islam, dan penyerapan serta pengintegrasian pengetahuan itu oleh umat Islam, merupakan sebuah catatan sejarah yang unik. Dalam sejarah peradaban manusia, amat jarang ditemukan suatu kebudayaan asing dapat diterima sedemikian rupa oleh kebuadaan lain, yang kemudian menjadikannya landasan bagi perkembangan intelektual dan pemahaman filosofisnya. Dalam perjalanan ilmu dan juga Filsafat di dunia Islam, pada dasarnya terdapat rekonsiliasi dalam arti mendekatkan dan mempertemukan dua pandangan yang berbeda, bahkan sering kali ekstrim antara pandangan Filsafat Yunani, seperti Filsafat Plato dan Aristoteles, dengan pandangan keagamaan dalam Islam yang sering kali menimbulkan benturan-benturan. Sebagai contoh konkret dapat disebutkan bahwa Plato dan Aristoteles telah memberikan pengaruh yang besar pada mazhab-mazhab Islam, khususnya mazhab eklektisisme. Al- FArabi dalam hal ini memiliki sikap yang jelas krena ia percaya pada kesatuan Filsafat dan bahwa tokoh-tokoh Filsafat harus bersepakat diantara mereka sepanjang yang menjadi tujuan mereka adalah kebenaran. Bahkan bisa dikatakan bahwa para filosof muslim mulai dari al- Kindi sampai Ibnu Rusyd terlibat dalam upaya rekonsiliasi tersebut, dengan cara mengemukakan pandangan-pandangan yang relative baru dan menarik. Usaha-usaha mereka pada gilirannya menjadi alat dalam penyebaran Filsafat dan penetrasinya ke dalam studi-studi keislaman lainnya, dan tak diragukan lagi, upaya-upaya rekonsiliasi oleh para filosof muslim ini menghasilkan afinitas dan ikatan yang kuat antara Filsafat Arab dan Filsafat Yunani.
- 25. 26 Selanjutnya, ketika berbicara tentang proses penyampaian ilmu dan Filsafat Yunani ke dunia Islam, kita harus melihat sisi lain yang juga menunjang keberhasilan Islam dalam menemukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Sisi lain itu adalah aktivitas penerjemahan. Menurut C. A. Qadir yang dikutip oleh Prof. Dr. Amsal Bakhtiar, M.A. dalam bukunya Filsafat Ilmu, proses penerjemehan dan penafsiran buku-buku Yunani di negri-negri Arab di mulai jauh sebelum lahirnya agama Islam atau penaklukkan Timur Dekat oleh bagsa Arab pada tahun 614M. Jauh sebelum umat Islam dapat menaklukkan daerah-daerah di Tmur Dekat, pada saat itu Suriah merupakan tempat bertemunya dua kekuasaan dunia, Romawi dan Persia. Atas dasar itu bangsa Suriah disebut-sebut memainkan peranan yang sangat penting dalam penyebaran budaya Yunani ke Timur dan Barat. Dikalangan umat Kristen di Suriah, terutama kaum Nestorian, ilmu pengetahuan Yunani dipelajari dan disebarluaskan melalui sekolah-sekolah mereka. Walaupun tujuan uatama mereka adalah menyebarluaskan pengetahuan injil, namun pengetahuan ilmiah seperti ilmu kedokteran banyak diminati oleh pelajar. Selain itu pada masa ini juga didapati pusat-pusat ilmu pengetahuan seperti Ariokh, Ephesus, dan Iskandariyah di aman buku-buku Yunani Purba masih dibaca dan diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Sejarah Filsafat Islam. Telah disebutkan sebelumnya bahwa ilmu filsafat islam berkembang dari adaptasi ilmu filsafat bangsa Yunani yang berasal dari benua Eropa. Timbulnya ilmu filsafat islam juga tidak jauh berkaitan dengan perkembangan islam di Eropa tersebut Awal Mula PerkembanganFilsafat Sejarah filsafat islam dimulai ketika Raja Iskandar Zulkarnain melakukan ekspansi militer ke beberapa Negara dibenua Eropa dan Afrika dan termasuk menguasai kota Iskandariah di Mesir. Dikota tersebut yakni sekitar abad ke 3 Masehi, Raja Ptolomeus di Mesir membangun Universitas Iskandaria dan dari situlah para ilmuwan barat memperkenalkan ilmu filsafat termasuk diantaranya para cendekiawan atau pemikir dari Yunani. Selanjutnya budaya bangsa Yunani tersebut mulai mengalami perbaduan dengan budaya baru bangsa Arab dan kemudian dikenallah ilmu filsafat dalam islam.
- 26. 27 PerkembanganFilsafatDikota Harran Selain kota Iskandariyah, pengarut budaya falsafah bangsa barat juga berkembang dikota Harran yang terletak disebelah utara negeri Syiria atau yang saat itu dikenal dengan sebutan Syam. Kota Harran tersebut kemudian jatuh ketangan bangsa Arab dan selanjutnya menjadi lebih terbuka dengan falsafah dan kebudayaan bangsa barat khususnya bangsa Yunani. Ilmu pengetahuan dan falsafah saat itu kemudian banyak diterjemahkan kedalam bahasa Arab sehingga bangsa Arab dapat dengan mudah mempelajarinya. PerkembanganFilsafatDi Baghdad Baghdad, ibukota Negara Iraq juga merupakan salah satu pusat perkembangan ilmu filsafat pada jaman dahulu. Setelah Baghdad mengalami perkembangan pesat, pusat studi ilmu dan filsafat berpindah dari Harran ke Baghdad dan selanjutnya para ahli yang menguasai filsafat juga turut berpindah ke kota tersebut. Sebut saja penerjemah terkenal ilmu filsafat dari kalangan bangsa Arab yang terkenal yakni Tsabit bin Qurrah dan juga Qista bin Luca. Kemajuan pesat ilmu filsafat saat itu memang didukung oleh para guru dan penterjemah sehingga tidak hanya kota dan kebudayaannya saja yang berkembang, dizaman itu juga lahirlah sosok penikir islam yakni Al Farabi dan Al Kindi. Tokoh Filsafat Islam Dalam ilmu filsafat islam ada beberapa tokoh yang dianggap membawa pengaruh dan karya-karyanya dikenal oleh sebagian umat muslim saat ini. Beberapa tokoh tersebut antara lain 1. Al-Kindi Al-Kindi atau Abu Yusuf Ya’qub bin Ishak bin Ash-Shabah bin Imran bin Ismail bin Al- Asy’ats bin Qays Al-Kindi dikenal sebagai sosok muslim pertama yang memunculkan gagasan tentang filsafat dan ia jugalah yang berpendapat bahwa ajaran agama islam sebenarnya tidak berbeda jauh dengan ilmu filsafat atau falsafah sehingga keduanya bukanlah dua hal yang bertentangan. Tidak hanya cerdas sebagai filsuf atau pemikir islam yang diakui oleh bangsa barat, Al kindi juga menghasilkan banyak karya dalam bidang ilmu pengetahuan lainnya seperti aritmatika dan musik
- 27. 28 2. Al-Farabi Al Farabi atau Abū Nasir Muhammad bin al-Farakh al-Fārābi‘ adalah seorang tokoh ilmuwan sekaligus filsuf muslim yang berusaha memadukan beberapa aliran filsafat antara lain aliran falsafah al taufiqhiyah yang berkembang sebelumnya dari hasil pe mikiran filsuf Yunani seperti Plato, Aristoteles, Plotinus. Al farabi juga berpandapat bahwa pada hakikatnya filsafat itu mmeiliki satu tujuan yakni untuk mencari kebenaran dari suatu hal. 3. Ibnu Rusyd Abu Walid Muhammad bin Rusyd atau yang dikenal dengan nama ibnu rusyid adalah salah satu tokoh ilmuwan muslim yang cukup dikenal. Ia juga merupakan salah seorang filsuf yang dikenal dnegan aliran rasionalnya. Sebagai seorang filsuf dan pemikir, Ibnu Rusyid menjunjung tinggi akal dan peranananya dalam kehidupan. Ibnu rusyid juga berpendapat bahwa akal fikiran bekerja dengan didasari oleh pengertian umum atau maj’ani kulliyah dandidalamnya tercakup hal-hal yang bersifat partial atau disebut juz’iyah. 4. Ibnu Sina Ibnu sina yang terkenal sebagai ilmuwan dalam bidnag kedokteran juga dikenal sebagai seorang sosok filsuf muslim. Ia berpendapat bahwa semua intelenji atau akal berasal dari Tuhan dan segala hal yang menyangkut dasar semua ilmu juga berasal dari Tuhan. Ibnu sina jugalah yang menyatakan bahwa esensi berada dalam akal dan wujud berada diluarakal. Ia juga banyak membahas mengenai metafisika dan filsafah tentang jiwa. 5. Al-Ghazali Muhammad bin Ahmad, Al-Imamul Jalil, Abu Hamid Ath Thusi Al-Ghazali atau yang lebih dikenal sebagai Al Ghazali adalah salah seorang filsuf ternama yang berasal dari daerah Thusi yang merupakan bagian dari Negara Persia. Al ghazali banyak menghasilkan karya dibidang filsafat dan ia pada mulanya berpendapat bahwa ilmu pengetahuan sebenarnya tidak bisa ditangkan dengan menggunakan panca indera manusia. Al ghazali lebih cenderung percaya terhadap akal daripada kelima panca indera. Dizamannya, ia pernah menjadi guru besar di Nidzamiyah, Baghdad selama empat tahun.beberapa kitab karangan Al
- 28. 29 ghazali yang terkenal antara lain Ihya Ulum Ad-Din, Tahafut al-Falasifah dan Al-Munqidz min adh-Dhalal. KESIMPULAN Filsafat Yunani mengalami kemegahan dan kejayaan dengan hasil yang sangat gemilang, yaitu melahirkan peradaban Yunani. Menurut pandangan sejarah filsafat, dikemukakan bahwa peradaban Yunani merupakan titik tolak peradaban manusia di dunia. Maka pandangan sejarah filsafat dikemukakan manusia di dunia. Giliran selanjutnya adalah warisan peradaban Yunani jatuh ke tangan kekuasaan Romawi. Kekuasaan Romawi memperlihatkan kebesaran dan kekuasaan hingga daratan Eropa (Britania), tidak ketinggalan pula pemikiran filsafat Yunani juga ikut terbawa. Hal ini berkat peran Caesar Augustus yang menciptakan masa kemasan kesusastraan Latin, kesian, dan arsitektur Romawi. DAFTAR PUSTAKA Afid burhanudin. https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/sejarah-perkembangan- ilmu-filsafat-pada-masa-abad-pertengahan/ Callasandra of Hanafiah http://berawaldarihati.blogspot.com/2010/12/sejarah-dan- perkembangan-filsafat-ilmu.html Sobirin Malian. https://journal.uii.ac.id/Unisia/article/view/2399 anggi rosalia. https://dalamislam.com/dasar-islam/ilmu-filsafat-islam
- 29. 30 C.MAKALAH FILSAFAT TEORI KEBENARAN PEMBAHASAN Manusia selalu berusaha menemukan kebenaran. Beberapa cara ditempuh untuk memperoleh kebenaran, antara lain dengan menggunakan rasio seperti para rasionalis dan melalui pengalaman atau empiris. Pengalaman-pengalaman yang diperoleh manusia membuahkan prinsip-prinsip yang lewat penalaran rasional, kejadian-kejadian yang berlaku di alam itu dapat dimengerti. Ilmu pengetahuan harus dibedakan dari fenomena alam. Fenomena alam adalah fakta, kenyataan yang tunduk pada hukum-hukum yang menyebabkan fenomena itu muncul. Ilmu pengetahuan adalah formulasi hasil aproksimasi atas fenomena alam atau simplifikasi atas fenomena tersebut. Struktur pengetahuan manusia menunjukkan tingkatan-tingkatan dalam hal menangkap kebenaran. Setiap tingkat pengetahuan dalam struktur tersebut menunjukkan tingkat kebenaran yang berbeda. Pengetahuan inderawi merupakan struktur terendah dalam struktur tersebut. Tingkat pengetahuan yang lebih tinggi adalah pengetahuan rasional dan intuitif. Tingkat yang lebih rendah menangkap kebenaran secara tidak lengkap, tidak terstruktur, dan pada umumnya kabur, khususnya pada pengetahuan inderawi dan naluri. Oleh sebab itulah pengetahuan ini harus dilengkapi dengan pengetahuan yang lebih tinggi. Pada tingkat pengetahuan rasional-ilmiah, manusia melakukan penataan pengetahuannya agar terstruktur dengan jelas. Filsafat ilmu memiliki tiga cabang kajian yaitu ontologi, epistemologi dan aksiologi. Ontologi membahas tentang apa itu realitas. Dalam hubungannya dengan ilmu pengetahuan, filsafat ini membahas tentang apa yang bisa dikategorikan sebagai objek ilmu pengetahuan. Dalam ilmu pengetahuan modern, realitas hanya dibatasi pada hal-hal yang bersifat materi dan kuantitatif. Ini tidak terlepas dari pandangan yang materialistik-sekularistik. Kuantifikasi objek ilmu pengetahuan berari bahwa aspek-aspek alam yang bersifat kualitatif menjadi diabaikan. Epistemologis membahas masalah metodologi ilmu pengetahuan. Dalam ilmu pengetahuan modern, jalan bagi diperolehnya ilmu pengetahuan adalah metode ilmiah dengan pilar utamanya rasionalisme dan empirisme. Aksiologi menyangkut tujuan diciptakannya ilmu pengetahuan, mempertimbangkan aspek pragmatis-materialistis.
- 30. 31 Ada beberapa wujud kebenaran, dan wujud ini berbeda – beda tingkatannya. Perbedaan tingkat ini terutama ditentukan oleh potensi subyek yang menyadari atau menangkap kebenaran itu. Baik panca indra, maupun rasio, bahkan juga akal budi manusia adalah potensi subyek yang menangkap dan menghayati kebenaran itu. Berdasarkan scope (jangkauan) potensi subyek itu tadi, maka susunan tingkatan kebenaran itu terbagi menjadi: 1.Kebenaran indra (empiris), adalah tingkatan yang paling sederhana dan pertama dialami manusia, Indra adalah gerbang kesadaran manusia. 2. Kebenaran ilmiah (rational), pengalaman-pengalaman yang tidak hanya didasarkan indra namun diolah juga dengan rasio. 3.Kebenaran filosofis (reflective thinking), rasio dan pikir murni, renungan yang mendalam mengolah kebenaran itu semakin tinggi nilainya. 4. Kebenaran religious (supernatural), kebenaran mutlak yang bersumber dari Tuhan yang Maha Esa dan dihayati oleh kepribadian dengan integritas dengan iman dan kepercayaan. Kebenaran itu ialah fungsi kejiwaan, fungsi rohaniah. Manusia selalu mencari kebanran itu, membina dan menyempurnakannya sejalan dengan kematangan kepribadiannya. Ukuran Kebenarannya : – Berfikir merupakan suatu aktifitas manusia untuk menemukan kebenaran – Apa yang disebut benar oleh seseorang belum tentu benar bagi orang lain – Oleh karena itu diperlukan suatu ukuran atau kriteria kebenaran Jenis-jenis Kebenaran : 1. Kebenaran Epistemologi (berkaitan dengan pengetahuan) 2. Kebenaran ontologis (berkaitan dengan sesuatu yang ada/ diadakan) 3. Kebenaran semantis (berkaitan dengan bahasa dan tutur kata) Manusia selalu mencari kebenaran, jika manusia mengerti dan memahami kebenaran, sifat asasinya terdorong pula untuk melaksankan kebenaran itu. Sebaliknya pengetahuan dan pemahaman tentang kebenran, tanpa melaksankan konflik kebenaran, manusia akan mengalami pertentangan batin, konflik spilogis. Karena di dalam kehidupan manusia sesuatu yang dilakukan harus diiringi akan kebenaran dalam jalan hidup yang dijalaninya dan
- 31. 32 manusia juga tidak akan bosan untuk mencari kenyataan dalam hidupnya yang dimana selalu ditunjukkan oleh kebanaran. Kebenaran agama yang ditangkap dengan seluruh kepribadian, terutama oleh budi nurani merupakan puncak kesadaran manusia. Hal ini bukan saja karena sumber kebnarna itu bersal dari Tuhan Yang Maha Esa supernatural melainkan juga karena yang menerima kebenaran ini adalah satu subyek dengna integritas kepribadian. Nilai kebenaran agama menduduki status tertinggi karena wujud kebenaran ini ditangkap oleh integritas kepribadian. Seluruh tingkat pengalaman, yakni pengalaman ilmiah, dan pengalaman filosofis terhimpun pada puncak kesadaran religius yang dimana di dalam kebenaran ini mengandung tujuan hidup manusia dan sangat berarti untuk dijalankan oleh manusia. B. Teori-Teori Kebenaran Menurut Filsafat 1. Teori Corespondence Masalah kebenaran menurut teori ini hanyalah perbandingan antara realita oyek (informasi, fakta, peristiwa, pendapat) dengan apa yang ditangkap oleh subjek (ide, kesan). Jika ide atau kesan yang dihayati subjek (pribadi) sesuai dengan kenyataan, realita, objek, maka sesuatu itu benar. Teori korispodensi (corespondence theory of truth) ® menerangkan bahwa kebenaran atau sesuatu kedaan benar itu terbukti benar bila ada kesesuaian antara arti yang dimaksud suatu pernyataan atau pendapat dengan objek yang dituju/ dimaksud oleh pernyataan atau pendapat tersebut. Kebenaran adalah kesesuaian pernyataan dengan fakta, yang berselaran dengan realitas yang serasi dengan sitasi aktual. Dengan demikian ada lima unsur yang perlu yaitu : 1. Statemaent (pernyataan) 2. Persesuaian (agreemant) 3. Situasi (situation) 4. Kenyataan (realitas) 5. Putusan (judgements)
- 32. 33 Kebenaran adalah fidelity to objektive reality (kesesuaian pikiran dengan kenyataan). Teori ini dianut oleh aliran realis. Pelopornya plato, aristotels dan moore dikembangkan lebih lanjut oleh Ibnu Sina, Thomas Aquinas di abad skolatik, serta oleh Berrand Russel pada abad moderen. Cara berfikir ilmiah yaitu logika induktif menggunakan teori korespodensi ini. Teori kebenaran menuru corespondensi ini sudah ada di dalam masyarakat sehingga pendidikan moral bagi anak-anak ialah pemahaman atas pengertian-pengertian moral yang telah merupakan kebenaran itu. Apa yang diajarkan oleh nilai-nilai moral ini harus diartikan sebagai dasar bagi tindakan-tindakan anak di dalam tingkah lakunya. Artinya anak harus mewujudkan di dalam kenyataan hidup, sesuai dengan nilai-nilai moral itu. Bahkan anak harus mampu mengerti hubungan antara peristiwa-peristiwa di dalam kenyataan dengan nilai-nilai moral itu dan menilai adakah kesesuaian atau tidak sehingga kebenaran berwujud sebagai nilai standard atau asas normatif bagi tingkah laku. Apa yang ada di dalam subyek (ide, kesan) termasuk tingkah laku harus dicocokkan dengan apa yang ada di luar subyek (realita, obyek, nilai-nilai) bila sesuai maka itu benar. 2. Teori Consistency Teori ini merupakan suatu usah pengujian (test) atas arti kebenaran. Hasil test dan eksperimen dianggap relible jika kesan-kesanyang berturut-turut dari satu penyelidik bersifat konsisten dengan hasil test eksperimen yang dilakukan penyelidik lain dalam waktu dan tempat yang lain. Menurut teori consistency untuk menetapkan suatu kebenarna bukanlah didasarkan atas hubungan subyek dengan realitas obyek. Sebab apabila didasarkan atas hubungan subyek (ide, kesannya dan comprehensionnya) dengan obyek, pastilah ada subyektivitasnya. Oleh karena itu pemahaman subyek yang satu tentang sesuatu realitas akan mungkin sekali berbeda dengan apa yang ada di dalam pemahaman subyek lain. Teori ini dipandang sebagai teori ilmiah yaitu sebagai usaha yang sering dilakukan di dalam penelitian pendidikan khsusunya di dalam bidang pengukuran pendidikan. Teori konsisten ini tidaklah bertentangan dengan teori korespondensi. Kedua teori ini lebih bersifat melengkapi. Teori konsistensi adalah pendalaman dankelanjutan yang teliti dan
- 33. 34 teori korespondensi. Teori korespondensi merupakan pernyataan dari arti kebenaran. Sedah teori konsistensi merupakan usaha pengujian (test) atas arti kebenaran tadi. Teori koherensi (the coherence theory of trut) menganggap suatu pernyataan benar bila di dalamnya tidak ada perntentangan, bersifat koheren dan konsisten dengna pernyataan sebelumnya yang telah dianggap benar. Dengan demikian suatu pernyataan dianggap benar, jika pernyataan itu dilaksanakan atas pertimbangan yang konsisten dan pertimbangan lain yang telah diterima kebenarannya. Rumusan kebenaran adalah turth is a sistematis coherence dan trut is consistency. Jika A = B dan B = C maka A = C Logika matematik yang deduktif memakai teori kebenaran koherensi ini. Logika ini menjelaskan bahwa kesimpulan akan benar, jika premis-premis yang digunakan juga benar. Teori ini digunakan oleh aliran metafisikus rasional dan idealis.Teori ini sudah ada sejak Pra Socrates, kemudian dikembangan oleh Benedictus Spinoza dan George Hegel. Suatu teori dianggapbenar apabila telah dibuktikan (klasifikasi) benar dan tahan uji. Kalau teori ini bertentangan dengan data terbaru yagn benar atau dengan teori lama yang benar, maka teori itu akan gugur atau batal dengan sendirinya. 3. Teori Pragmatisme Paragmatisme menguji kebenaran dalam praktek yang dikenal apra pendidik sebagai metode project atau medoe problem olving dai dalam pengajaran. Mereka akan benar-benar hanya jika mereka berguna mampu memecahkan problem yang ada. Artinya sesuatu itu benar, jika mengmbalikan pribadi manusia di dalamkeseimbangan dalam keadaan tanpa persoalan dan kesulitan. Sebab tujuan utama pragmatisme ialah supaya manusia selalu ada di dalam keseimbangan, untuk ini manusia harus mampu melakukan penyesuaian dengan tuntutan- tuntutan lingkungan. Dalam dunia pendidikan, suatu teori akan benar jika ia membuat segala sesutu menjadi lebih jelas dan mampu mengembalikan kontinuitas pengajaran, jika tidak, teori ini salah. Jika teori itu praktis, mampu memecahkan problem secara tepat barulah teori itu benar. Yang dapat secara efektif memecahkan masalah itulah teori yang benar (kebenaran). Teori pragmatisme (the pragmatic theory of truth) menganggap suatu pernyataan, teori atau dalil itu memliki kebanran bila memiliki kegunaan dan manfaat bagi kehidupan manusia. Kaum pragmatis menggunakan kriteria kebenarannya dengan kegunaan (utility) dapat dikerjakan (workobility) dan akibat yagn memuaskan (satisfaktor consequence). Oleh karena
- 34. 35 itu tidak ada kebenaran yang mutak/ tetap, kebenarannya tergantung pada manfaat dan akibatnya. Akibat/ hasil yang memuaskan bagi kaum pragmatis adalah : 1. Sesuai dengan keinginan dan tujuan 2. Sesuai dengan teruji dengan suatu eksperimen 3. Ikut membantu dan mendorong perjuangan untuk tetap eksis (ada) Teori ini merupakan sumbangan paling nyata dari pada filsup Amerika tokohnya adalha Charles S. Pierce (1914-1939) dan diikuti oleh Wiliam James dan John Dewey (1852- 1859). Wiliam James misalnya menekankan bahwa suatu ide itu benar terletak pada konsikuensi, pada hasil tindakan yang dilakukan. Bagi Dewey konsikasi tidaklah terletak di dalam ide itu sendiri, malainkan dalam hubungan ide dengan konsekuensinya setelah dilakukan. Teory Dewey bukanlah mengerti obyek secara langsung (teori korepondensi) atau cara tak langsung melalui kesan-kesan dari pada realita (teori konsistensi). Melainkan mengerti segala sesuai melalui praktek di dalam program solving. 4. Kebenaran Religius Kebenaran adalah kesan subjek tentang suatu realita, dan perbandingan antara kesan dengan realita objek. Jika keduanya ada persesuaian, persamaan maka itu benar. Kebenaran tak cukup hanya diukur dnenga rasion dan kemauan individu. Kebenaran bersifat objective, universal,berlaku bagi seluruh umat manusia, karena kebenaran ini secara antalogis dan oxiologis bersumber dari Tuhan yang disampaikan melalui wahyu. Nilai kebenaran mutlak yang bersumber dari Tuhan itu adalah objektif namun bersifat superrasional dan superindividual. Bahkan bagi kaum religius kebenarn aillahi ini adalah kebenarna tertinggi, dimnaa semua kebanaran (kebenaran inderan, kebenaran ilmiah, kebenaran filosofis) taraf dan nilainya berada di bawah kebanaran ini : Agama sebagai teori kebenaran Ketiga teori kebenaran sebelumnya menggunakan alat, budi,fakta, realitas dan kegunaan sebagai landasannya. Dalam teori kebanran agama digunakan wahyu yang bersumber dari Tuhan. Sebagai makluk pencari kebeanran, manusia dan mencari dan menemukan kebenaran melalui agama. Dengan demikian, sesuatu dianggap benar bila sesuai
- 35. 36 dan koheren dengan ajaran agama atau wahyu sebagai penentu kebenaran mutlak.agama dengan kitab suci dan haditsnya dapat memberikan jawaban atas segala persoalan manusia, termasuk kebenaran. KESIMPULAN Bahwa kebenaran itu sangat ditentukan oleh potensi subyek kemudian pula tingkatan validitas. Kebanran ditentukan oleh potensi subyek yang berperanan di dalam penghayatan atas sesuatu itu. Bahwa kebenaran itu adalah perwujudan dari pemahaman (comprehension) subjek tentang sesuatu terutama yang bersumber dari sesuatu yang diluar subyek itu realita, perisitwa, nilai-nilai (norma dan hukum) yang bersifat umum. Bahwa kebenaran itu ada yang relatif terbatas, ada pula yang umum. Bahkan ada pula yang mutlak, abadi dan universal. Wujud kebenaran itu ada yang berupa penghayatan lahiriah, jasmaniah, indera, ada yang berupa ide-ide yang merupkan pemahaman potensi subjek (mental,r asio, intelektual). Bahwa substansi kebenaran adalah di dalam antaraksi kepribadian manusia dengan alam semesta. Tingkat wujud kebenaran ditentukan oleh potensi subjek yang menjangkaunya. Semua teori kebanrna itu ada dan dipraktekkan manusia di dalam kehidupan nyata. Yang mana masing-masing mempunyai nilai di dalam kehidupan manusia. DAFTAR PUSTAKA Syam, Muhammad Noor. 1988. Filsafat Kependidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila. Surabaya: Usaha Nasional Bertens, K. 1976. Ringkasan Sejarah Filsafat. Jakarta: Yayasan Krisius Sumantri Surya. 1994. Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- 36. 37 D. MAKALAH FILSAFAT MANUSIA PEMBAHASAN Filsafat manusia adalah cabang filsafat khusus yang secara spesifik mempelajari hakekat/esensi manusia. Filsafat adalah metode pemikiran yang membahas tentang sifat dasar dan hakikat kebenaran yang ada di dunia ini. Filsafat manusia adalah bagian filsafat yang membahas apa arti manusia sendiri secara mendetail. Antropologi filsafat atau yang lebih dikenal dengan filsafat manusia adalah bagian integral dari sistem filsafat, yang secara spesifik menyoroti hakikat atau esensi manusia. Objek material filsafat manusia dan ilmu-ilmu tentang manusia (misalnya psikologi dan antropologi) adalah gejala manusia. Pada dasarnya ilmu ini bertujuan untuk menyelidiki, menginterpretasi, dan memahami gejala-gejala atau ekspresi-ekspresi manusia. Filsafat manusia jelasnya adalah filsafat yang mengupas apa arti manusia sendiri, ia mencoba mengucap sebaik mungkin apa sebenarnya makhluk itu yang disebut “manusia”, istilah filusuf manusia atau “antropologi filusuf” (antropos dalam bahasa Yunani berarti manusia) tampak lebih eksok karena apa yang dipelajari dengannya adalah manusia sepenuhnya, roh serta badan jiwa serta daging. Alasan untuk mempelajari filsafat manusia cukup jelas. Pertama manusia adalah makhluk yang memiliki kemampuan dan kewajiban (sampai batas tertentu) untuk menyelidiki arti yang dalam “dari yang ada” kerap kali dalam usia remaja manusia merasa dalam dirinya sendiriang paling pribadi suatu dorongan yang menurut Sokrates, telah didengarnya di bawah langit Delphi : “Kenalilah dirimu sendiri”. Manusia secara bahasa disebut juga insan, yang dalam bahasa arabnya berasal dari kata ‘nasiya’ yang berarti lupa. Dan jika dilihat dari kata dasar ‘al-uns’ yang berarti jinak. Kata insan dipakai untuk menyebut manusia, karena manusia memiliki sifat lupa dan jinak artinya manusia selalu menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru disekitarnya. Manusia memiliki cara keberadaan yang sekaligus membedakannya secara nyata dengan mahluk yang lain. Seperti dalam kenyataan mahluk yang berjalan diatas dua kaki, kemampuan berfikir, dan berfikir tersebut yang menentukan manusia pada hakekat manusia.
- 37. 38 Ada beberapa pandangan para ahli tentang filsafat manusia ini, yaitu: 1. Manusia memiliki karya yang dihasilkan sehingga berbeda dengan mahluk yang lain. Manusia dalam memiliki karya dapat dilihat dalam seting sejarah dan seting psikologis situasi emosional dan intelektual yang melatarbelakangi karyanya. Dari karya yang dibuat manusia tersebut menjadikan ia sebagai mahluk yang menciptakan sejarah. Manusia juga dapat dilihat dari sisi dalam pendekatan teologis, dalam pandangan ini melengkapi dari pandangan yang sesudahnya dengan melengkapi sisi trasendensi dikarenakan pemahaman lebih bersifat fundamental. 2. Ada yang mengatakan manusia adalah hewan rasional (animal rasional) dan pendapat ini diyakini oleh para filosof. Sedangkan yang lain menilai manusia sebagai animal simbolik, pernyataan tersebut dikarenakan manusia mengkomunikasikan bahasa melalui simbol-simbol dan manusia menafsirkan simbol-simbol tersebut. 3. Ada yang lain menilai tentang manusia adalah sebagai homo feber dimana manusia adalah hewan yang melakukan pekerjaan dan dapat gila terhadap kerja. Manusia memang sebagai mahluk yang aneh dikarenakan disatu pihak ia merupakan “mahluk alami”, seperti binatang, ia memerlukan alam untuk hidup. Dipihak lain ia berhadapan dengan alam sebagai sesuatu yang asing ia harus menyesuaikan alam sesuai dengan kebutuh-kebutuhannya. Manusia dapat disebut sebagai homo sapiens, manusia arif memiliki akal budi dan mengungguli makhluk yang lain. 4. Marx menunjukan perbedaan antara manusia dengan binatang tentang kebutuhannya. Manusia dalam bekerja secara bebas dan universal, bebas dapat bekerja meskipun tidak merasakan kebutuhan langsung, universal dikarenakan ia dapat memakai beberapa cara untuk tujuan yang sama. Dipihak yang lain ia dapat menghadapi alam tidak hanya dalam kerangka salah satu kebutuhan. Oleh sebab itu menurut Marx manusia hanya terbuka pada nilai-nilai estetik dan hakekat perbedaan manusia dengan binatang adalah menunjukan hakekat bebas dan universal. 5. Menurut Paulo Freire manusia merupakan satu-satunya mahluk yang memiliki hubungan dengan dunia. Manusia berbeda dari hewan yang tidak memiliki sejarah, dan hidup dalam masa kini yang kekal, yang mempunyai kontak tidak kritis dengan dunia, yang hanya berada dalam dunia. Tindakan dan kesadaran manusia bersifat historis, manusia membuat hubungan dengan dunianya bersifat epokal, yang menunjukan disini berhubungan disana, sekarang berhubungan masa lalu dan berhubungan dengan masa depan. manusia menciptakan sejarah juga sebaliknya manusia diciptakan oleh sejarah.
- 38. 39 B. Hakekat Manusia menurut para ahli Hakikat Manusia Menurut Socrates Pemikir hebat di Yunani yang memberikan sumbangsihnya dengan membantu terbentuknya fondasi filsafat di Barat. Metode yang ia gunakan dan konsep yang ia paparkan telah membantu terbentuknya dunia fisafat barat. Penolakannya terhadap kompromi mengenai integritas intelektualnya membuatnya menghadapi hukuman mati. Pandangan Socrates mengenai hakikat manusia : Manusia adalah seorang yang rasional. Manusia mungkin bervariasi dalam kemampuan rasionalitasnya, mungkin mereka dapat kekurangan secara mental, atau mungkin mereka malah menolak kerasionalitasan. Tetapi bagaimanapun juga definisi hakikat manusia secara universal tetaplah memegang kebenaran. Manusia dapat membedakan kebajikan, pengetahuan dari ketidaktahuan. Manusia dapat mengetahui kebaikan, dari mengetahuinya dia dapat mengikutinya. Untuk kepada orang yang tidak mengenal kebaikan dia akan memilih mengikuti keburukan. Hakikat Manusia Menurut Plato Seorang filsuf dan matematikawan, murid dari Socrates. Pandangan dan metodenya juga telah membantuk terbentuknya fondasi dunia filsafat barat. Ranah pemikirannya sampai kepada, etic, logika, filsafat, agama, retorik dan matematika. Hakikat manusia menurut plato adalah : “Setiap manusia lahir dengan memilki kebutuhan biologis masing-masing. Tugas paling mendasar dari jiwa manusia adalah untuk mengejar pengetahuan. Kebutuhan dari jiwa yang menginginkan pemurnian dari badannya, dan jiwa tersebut tidak akan dapat murni sampai dia mati. Bagian paling rasional dari jiwanya adalah bagian yang dapat mendapatkan kebenaran. Ini adalah tugas dari yang tercerahkan. Jiwa memiliki tiga bagian, yang mempertanyakan, semangat, dan hasrat. Jika manusia tidak berkecimpung di dalam sebuah kelompok, dia tidak akan bertahan. Interaksi sosiallah yang membuat kita benar-benar manusia.”
- 39. 40 C. Kedudukan FilsafatManusiaDalam KehidupanManusia 1. Memberikan pengertian dan kesadaran kepada manusia akan arti pengetahuan tentang kenyataan yang diberikan oleh filfafat. 2. Berdasarkan atas dasar hasil-hasil kenyataan , maka filsafat memberikan pedoman hidup kepada manusia. Pedoman itu mengenai sesuatu yang terdapat di sekitar manusia sendiri, seperti kedudukan dalam hubungannya dengan yang lain. Kita juga mengetahui bahwa alat- alat kewajiban manusia meliputi akal, rasa, dan kehendak. Dengan akal filsafat memberikan pedoman hidup untuk berpikir guna memperoleh pengetahuan. Dengan rasa dan kehendak, maka filsafat memberikan pedoman tentang kesusilaan mengenai baik dan buruk. Filsafat bukanlah ilmu positif seperti fisika, kimia, biologi, tetapi filsafat adalah ilmu kritis yang otonom di luar ilmu-ilmu positif. Tiga unsur pembentukan manusia, yaitu: 1. Pengetahuan manusia tentang diri sendiri dan lingkungannya Pengetahuan menjadi unsur yang penting dalam usaha membentuk manusia yang lebih baik. Dalam hal ini ilmu lebih kritis daripada hanya menerima apa yang didapat dari pengetahuan. Pengetahuan yang dimaksud di sini lebih pada pengetahuan manusia tentang diri sendiri dan dunianya. Ketika manusia mengetahui dan mengenal dirinya secara penuh, ia akan hidup secara lebih sempurna dan lebih baik dalam dunia yang adalah dunianya. Berkaitan dengan itu manusia juga membutuhkan pengetahuan tentang lingkungan atau dunianya. Dengan pengetahuan yang ia miliki tentang dunia atau lingkungannya, manusia dapat mengadaptasikan dirinya secara cepat dan lebih mudah. 2. Manusia Dalam Hubungannya Dengan Hidup Komunitas Manusia membutuhkan orang lain untuk dapat membentuk dan mengembangkan dirinya sehingga dapat hidup secara lebih baik, lebih bijaksana dan lebih kritis. Dengan demikian manusia pada hakikatnya hidup bersama dengan orang lain atau hidup dalam suatu komunitas tertentu, mengalami kehidupan polis. Jadi, kebersamaannya dengan orang lain dalam suatu komunitas inilah yang turut menentukan pembentukan yang memperkenankan manusia itu hidup atas cara yang lebih baik dan lebih sempurna dalam dunianya. Unsur lain yang dapat membantu membentuk manusia sehingga manusia dapat hidup secara lebih baik, lebih bijaksana adalah agama. Dengan kata lain, agama mengandung nilai- nilai universal yang pada hakikatnya mengajarkan yang baik bagi penganutnya.
- 40. 41 a. Hubungan Filsafat Manusia Dengan Disiplin Ilmu Lain Tentang Manusia 1. Psikologi membahas objek materi yakni manusia. Ilmu ini hanya membahas manusia dari segi psikis yang dapat diperoleh dari melihat perilaku manusia, menjelaskan gejala-gejala jiwa dan mental, bagaimana pengalaman manusia dapat mempengaruhi kehidupan selanjutnya dan menjelaskan perkembangan manusia dari masa prenatal hingga menjelang kematian. 2. Sosiologi juga membahas objek materi yakni manusia. Namun, ilmu ini membatasi diri untuk mencoba menjawab perilaku manusia dari ruang lingkup sosialnya, menjelaskan status sosial, pranata sosial, dan menjelaskan bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri. 3. Antropologi juga membahas objek materi yakni manusia. Namun, ilmu ini membatasi pada pola kebudayaan dan peradaban yang telah diciptakan manusia atau ditinggalkan manusia, menjelaskan hasil-hasil kebudayaan, suku, etnis, dan ras suatu masyarakat yang bersifat lokal. b. Esensi Dan Eksistensi FilsafatManusia Serta Peranan Manusia Model esensi adalah pendekatan dalam filsafat kepada suatu objek dengan cara yang abstrak. Model ini memandang manusia terlepas dari situasi dan perkembangannya. Model esensi hanya memperhatikan kodrat yang menentukan manusia sebagai manusia. Sementara itu model eksistensi adalah pendekatan dalam filsafat kepada suatu objek dengan memandangnya secara menyeluruh. Manusia dipandang secara konkret secara utuh dalam keberadaannya. Model eksistensi tidak percaya akan kodrat yang menentukan manusia. 1. Esensi Manusia Menurut Sejumlah Aliran dalam Filsafat Di dalam filsafat manusia terdapat beberapa aliran. Tiap-tiap aliran memiliki pandangan tentang hakikat atau esensi manusia yang berbeda-beda. Dari sekian banyak aliran, terdapat dua aliran tertua dan terbesar, yaitu materialisme dan idealisme. Sedangkan aliran- aliran lain, pada prinsipnya merupakan reaksi yang berkembang kemudian terhadap kedua aliran tersebut.
- 41. 42 a. Materialisme · Essensi manusia bersifat material/fisik menempati ruang dan waktu, memiliki keluasan dan bersifat objektif sehingga dapat diukur, dihitung, diobservasi. · Tidak ada aspek spiritual dibalik yang material. · Materialisme/Naturalisme. Istilah materi diganti dengan istilah nature/alam setiap gejala/gerak dapat dijelaskan menurut hukum kausalitas. Gerak disebabkan karena ada gerak eksternal yang menggerakkan. · Kaum materialis pada umumnya sangat deteministik gerak bersifat mekanis untuk menggerakkan manusia adalah mesin. · Manusia adalah bagian dari alam/materi, manusia adalah objek yang substansinya adalah berkeluasan, manusia adalah mesin/kumpulan sel dan sistem syaraf. · Manusia merupakan makhluk deterministik/tidak memiliki kebebasan. Perilaku manusia adalah akibat dari suatu sebab eksternal. Manusia bertindak karena ada suatu sebab yang mendahului (stimulus) yang menuntut untuk diberikan respons/reaksi. b. Idealisme · Kenyataan sejati bersifat spiritual, yaitu spiritualisme ada kenyataan dibalik setiap penampakan/kejadian esensi dari kenyataan spiritual adalah berpikir, karena tidak dapat diukur atau dijelaskan berdasarkan pada pengamatan empiris menggunakan metafor kesadaran manusia. Kekuatan spiritual bersifat rasional, berkehendak, berperasaan, kreatif, dll. · Penganut idealisme berpandangan deterministik, roh absolut/Tuhan adalah bebas dan tidak terhingga tetapi manusia sebagai bagian dari roh absolut maka tidak bebas dan berhingga. Kedudukan dan tindakan manusia sudah diatur sebelumnya oleh roh absolut. Kebalikan dari materialisme adalah idealisme. c. Dualisme · Kenyataan sejati bersifat fisik maupun spirt hal/merupakan perpaduan materi dan roh. · Keberadaan tubuh tidak menolak keberadaan jiwa yang keberadaannya tidak dapat diamati secara indrawi tetapi dapat dibuktikan melalui ratio. · Contoh : Menurut Descartes. Menurut Descartes, keberadaan jiwa karakteristiknya adalah res cogitans (berfikir) justru lebih jelas dan tegas dibandingkan dengan keberadaan tubuh. Untuk membuktikannya maka perlu berfikir secara skeptis, misalnya meragukan keberadaan apa saja yang bersifat fisik (computer, kekasih yang berada disamping kita dan keberadaan tubuh kita sendiri). Semua itu bisa diragukan keberadaannya atau hanya
- 42. 43 halusinasi kita, hanya dalam mimpi dan bukan kenyataan yang sebenarnya. Akan tetapi, ada satu hal yang tidak bisa diragukan keberadaannya, yaitu “aku” yang sedang meragukan atau sedang berfikir. Descartes menyebutnya “Cogito ergo sum”- “aku berfikir (meragukan), maka aku ada.” d. Vitalisme · Kenyataan sejati bersifat energi, daya, kekuatan atau nafsu yang bersifat irrasional. · Acuan vitalisme adalah ilmu biologi dan sejarah biologi mengajarkan bahwa kehidupan ditentukan oleh kekuatan untuk bertahan hidup agar tetap dapat survei berdasarkan naluri kehendak buta (schopenhawer), kehendak untuk berkuasa (nietzche) => sejarah dan peradaban manusia digerakkan oleh dorongan tidak rational dan liar. e. Eksistensialisme · Essensi manusia bersifat kongkret, individual, dinamis. Existere (eks = keluar, sistere = ada) istilah eksistensi adalah sesuatu yang mampu melampui dirinya sendiri. · Hanya manusia yang bereksistensi/sanggup keluar dari dirinya melampuai keterbatasan biologis dan lingkungan fisiknya. f. Strukturalisme Menempatkan struktur/sistem bahasa, budaya sebagai kekuatan-kekuatan yang menentukan perilaku bahkan kesadaran manusia, manusia tidak bebas yang berstruktur oleh sistem bahasa dan budayanya. · Tidak ada perilaku, pola pikir dan kesadaran manusia yang bersifat individual dan unik yang bebas dari sistem bahasa dan budaya yang mengungkapkannya. Artinya aliran ini secara tegas menolak humanisme, menolak pandangan tentang kebebasan dan keluhuran (keagungan) manusia. Strukturalisme juga tidak mengakui adanya “ego”, “aku” atau “kesadaran”. Aliran ini berpendapat bahwa “aku” atau manusia bukanlah pusat realitas. Makna dan keberadaaan manusia pada dasarnya tidak tergantung pada diri manusia itu sendiri, melainkan pada kedudukan dan fungsinya dalam sistem. g. Posmodernisme · Hampir sama dengan strukturalisme, tapi manusia didominasi oleh sistem-sistem kecil yang bersifat jamak. · Aliran posmodernisme ini hampir sama dengan strukturalisme. · Kedua ailiran ini boleh disebut anti humanisme, jika humanisme dipahami sebagai pengakuan atas keberadaan dan didominasi “aku” yang terlepas dari sistem atau kondisi yang
- 43. 44 mengitari hidupnya. Akan tetapi berbeda dengan posmodernisme yang membahas tentang aspek kehidupan manusia yang lebih beragam dan actual. · Posmodernisme menentang bukan hanya “aku” yang seolah-olah bebas dan mampu melepaskan diri dari sistem sosial budayanya, tetapi juga menafikan dominasi sitem sosial, budaya, politik, kesenian, ekonomi bahkan arsitektur. 2. Eksistensi dan peranan manusia Manusia sebagai mahluk yang berdimensional memiliki peran dan kedudukan yang sangat mulia. Manusia yang memiliki eksistensi dalam hidupnya sebagai abdullah (kedudukan ketuhanan), an-nas (kedudukan antar manusia), al insan (kedudukan antar alam), al basyar (peran sebagai manusia biasa) dan khalifah (peran sebagai pemimpin). Manusia dengan manusia yang lain memiliki korelasi yang seimbang dan saling berkerjasama dalam rangka memakmurkan bumi. Manusia dengan alam sekitar merupakan sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan rasa syukur kita terhadap Tuhan dan bertugas menjadikan alam sebagai subjek dalam rangka mendekatkan diri kepada Tuhan. Setiap apa yang dilakukan oleh manusia dalam pelaksana pengganti Tuhan sesuai dengan maqasid asy- syari’ah. Maqasid asy-syari’ah merupakan tujuan utama diciptanya sebuah hukum atau mungkin nilai esensi dari hukum, di mana harus menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, akal dan, ekologi. Manusia yang memegang amanah sebagai khalifah dalam melakukan keputusan dan tindakannya sesuai dengan maqasid asy-syari’ah. Ada tiga rantai kehidupan, yaitu: a. Hubungan kepada Tuhan (Manusia sebagai hamba) Dalam kondisi sosial tertentu, tidak sedikit manusia yang melupakan faktor ketuhanan sehingga mereka menjadi atheis. Utamanya bagi penganut materialisme yang mempercayai bahwa segala sesuatu berasal dari benda. Tidak ada unsur spiritual yang membuat benda itu tercipta. Hal ini bertolak belakang dengan ajaran agama-agama di dunia yang mengatakan sumber segala sumber ialah Tuhan. Dalam hal ketuhanan setiap agama memiliki penyembahan yang berbeda-beda. Agama, apapun itu pasti mengajarkan hubungan kepada Tuhan sebagai hubungan yang dinomor satukan. Ini tidak berarti mengutamakan hubungan ketuhanan dan memandang remeh hubungan-hubungan yang lain
- 44. 45 b. Hubungan Antar Manusia (Manusia sebagai makhluk sosial) Hubungan lain yang harus dijalankan manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial ialah hubungan antarmanusia itu sendiri. Munculnya gerakan sparatis menggunakan atribut agama menjadi contoh bagaimana oknum manusia mengedepankan ego pribadi dibanding kepentingan masyarakat luas. Hal ini menjadi ironi apabila pergerakan itu semakin melebarkan sayapnya dan semakin disalahpahami oleh masyarakat luas. Pengatasnamaan negara merupakan wujud dari mispersepsi kehidupan keberagaman yang menjadi simbol perpecahan umat. Perlu dibangun sebuah peradaban manusia yang benar-benar memahami nilai-nilai keberagaman. Manusia kepada manusia tidak diartikan dengan monoisme teologi yang tidak mungkin dicapai kesepakatan apabila benar-benar digencarkan. Namun itu terbatas pada tataran keyakinan yang tidak harus diungkapkan dengan gerakan-gerakan yang justru membuat hubungan antarmanusia menjadi terhalang. Merasa lebih baik merupakan sifat manusiawi yang tidak dapat dihilangkan, namun dapat dikendalikan dengan pemahaman-pemahaman asas ketuhanan. c. Hubungan kepada Alam (Manusia sebagai makhluk) Hubungan terpenting lainnya ialah hubungan kepada alam. Alam tidak terjustifikasi sebagai bentuk dari pepohonan, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Namun alam mencakup semua hal, baik alam yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Spiritualisme menjadi aliran yang dominan apabila pembahasan merambah ke alam yang tidak terlihat (ghaib). Di alam ini terdapat makhluk-makhluk lain yang secara penciptaan sejajar dengan manusia dan partikel alam lain, namun memiliki keistimewaan yang berbeda dengan material yang tampak. Perlu pemahaman khusus mengenai alam ini untuk dapat mempercayai dan meneliti keberadaannya. Kepercayaan terhadap hal ghaib ini berpengaruh terdapat hubungan ketuhanan sebab beberapa aliran keagamaan tidak menggambarkan secara detail bagaimana wujud Tuhan sesungguhnya. Fungsi manusia sebagai khalifah terlihat menonjol peranannya dalam kehidupan kompleks di dunia antara manusia dan alam.
- 45. 46 3. Beberapa perananansebagai manusia, yaitu: a. Peran manusia sebagai manusia biasa Dalam tiga konsep besar yang melibatkan Tuhan, manusia dan alam di atas, peran manusia tidaklah serta merta menjadi komunitas yang terbaik tanpa dorongan fasilitas dari faktor-faktor lain. Manusia tidak akan mampu membangun gedung-gedung tinggi tanpa peran besi baja yang diolah menjadi alat-alat berat. Atau jika lebih ke dalam, manusia tidak akan bisa bertahan hidup tanpa jaminan tumbuhan dan binatang yang menjadi santapannya. Maka klasifikasi makhluk dititikberatkan pada data, bukan semerta-merta menjadikan manusia sebagai komunitas terbaik yang boleh melakukan seenaknya kepada bagian makhluk yang lain. Karena kesewenang-wenangan ini menjadikan gagalnya manusia dalam menjalani perannya sebagai khalifah (pemimpin). b. Peran manusia sebagai khalifah Sebagai pemimpin di muka bumi, manusia diajarkan bagaimana cara memimpin yang baik. Lagi-lagi kembali kepada tiga konsep besar di atas. Dari Tuhan manusia memiliki kekuatan dan pengetahuan yang jika diimplementasikan terhadap kata ‘manusia sebagai khalifah’ akan menjadi sangat ideal. Karena hanya manusialah makhluk yang memiliki akal dan nurani yang masing-masing menjadi pengontrol bagian lainnya. Dengan akal manusia mengonsep, dan dengan nurani manusia dapat membenarkan tindakannya. F. Perbedaan Filsafat Manusia Dan Ilmu Tentang Manusia (Psikologi & Antropologi) Ilmu tentang manusia Filsafat manusia 1. Bersifat positifistik menggunakan metodologi ilmu alam, observasional dan eksperimental yang terbatas tampak secara empiris. Bersifat metafisis menggunakan metode ilmu kemanusiaan, sintesis, reflektif, intensif, dan kritis yang merupakan gejala seperti filsafat manusia. 2. Oleh karena itu tidak dapat menjawab pertanyaan yang mendasar tentang manusia. Oleh karena itu dapat menjawab pertanyaan yang mendasar tentang manusia.
- 46. 47 3. Metode lebih fragmentaris yaitu menyelidiki hanya bagian tertentu dari manusia. Contoh: Psikologi hanya menekankan aspek psikis dan fisiologis manusia sebagai organisme. Antropologi dan sosiologi pada gejala budaya dan pranata sosial. Metode sintesis dan reflektif (ekstensif) atau menyeluruh, intensif (mendalam) dan kritis. Contoh: Filsafat manusia menekankan kesatuan dua aspek/lebih dalam satu visi. G. Manfaat Mempelajari Filsafat Manusia 1. Secara praktis Membutuhkan pemahaman manusia secara menyeluruh, sehingga memudahkan mengambil keputusan-keputusan praktis/menjalankan aktivitas hidup sehari-hari. 2. Secara teoritis Pemahaman manusia secara yang esensial sehingga kita dapat meninjau secara kritis asumsi- asumsi yang tersembunyi di balik teori-teori antropologi dan psikologi dan ilmu-ilmu tentang manusia. KESIMPULAN Filsafat manusia adalah cabang filsafat khusus yang secara spesifik mempelajari hakekat/esensi manusia. Filsafat adalah metode pemikiran yang membahas tentang sifat dasar dan hakikat kebenaran yang ada di dunia ini. Pengetahuan menjadi unsur yang penting dalam usaha membentuk manusia yang lebih baik. Dalam hal ini ilmu lebih kritis daripada hanya menerima apa yang didapat dari pengetahuan. Pengetahuan yang dimaksud di sini lebih pada pengetahuan manusia tentang diri sendiri dan dunianya. Di dalam filsafat manusia terdapat beberapa aliran. Tiap-tiap aliran memiliki pandangan tentang hakikat atau esensi manusia yang berbeda-beda. Manusia dengan manusia yang lain memiliki korelasi yang seimbang dan saling berkerjasama dalam rangka memakmurkan bumi. Manusia dengan alam sekitar merupakan sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan rasa syukur kita terhadap Tuhan dan bertugas menjadikan alam sebagai subjek dalam rangka mendekatkan diri kepada Tuhan, hubungan lain yang harus dijalankan manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial ialah
- 47. 48 hubungan antarmanusia itu sendiri dan kemudian disusul oleh hubungan manusia dengan alam. DAFTAR PUSTAKA http://antronesia.com/filsafat-manusia/ http://www.sekelumitpandang.com/hakikat-manusia-menurut-para-ahli/ E.Makalah Filsafat Pengetahuan Dan Ilmu PEMBAHASAN A. ONTOLOGI Ontologi berasal dari bahasa Yunani yang artinya ilmu tentang yang ada. Sedangkan, menurut istilah adalah ilmu yang membahas sesuatu yang telah ada, baik secara jasmani maupun secara rohani. Dalam aspek Ontologi diperlukan landasan-landasan dari sebuah pernyataan-pernyataan dalam sebuah ilmu. Landasan-landasan itu biasanya kita sebut dengan Metafisika. Selain Metafisika juga terdapat sebuah asumsi dalam aspek ontologi ini. Asumsi ini berguna ketika kita akan mengatasi suatu permasalahan. Dalam asumsi juga terdapat beberapa paham yang berfungi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tertentu, yaitu: Determinisme (suatu paham pengetahuan yang sama dengan empiris), Probablistik (paham ini tidak sama dengan Determinisme, karena paham ini ditentukan oleh sebuah kejadian terlebih dahulu), Fatalisme (sebuah paham yang berfungsi sebagai paham penengah antara determinisme dan pilihan bebas), dan paham pilihan bebas. Setiap ilmuan memiliki asumsi sendiri-sendiri untuk menanggapi sebuah ilmu dan mereka mempunyai batasan-batasan sendiri untuk menyikapinya. Apabila kita memakai suatu paham yang salah dan berasumsi yang salah, maka kita akan memperoleh kesimpulan yang berantakan.
- 48. 49 Dasar Ontologi Ilmu Telah disampaikan sebelumnya bahwa kajian ilmu adalah objek empiris. Pengetahuan keilmuan mengenai objek empiris ini pada dasarnya merupakan abstraksi yang disederhanakan. Penyederhanaan ini perlu, sebab kejadian alam yang sesunggunya begitu kompleks, dengan sampel dari berbagai faktor yang terlibat di dalamnya. Ilmu bertujuan untuk mengerti mengapa hal itu terjadi, dengan membatasi diri pada hal-hal yang asasi. Atau dengan perkataan lain, proses keilmuan bertujuan untuk memeras hakikat objek empiris tertentu, untuk mendapatkan sari yang berupa pengetahuan mengenai objek tersebut. Ada 3 hal yang berkaitan dalam mempelajari ontologi ilmu, yaitu: Metafisika, Probabilitas dan Asumsi. 1. Metafisika Secara etimologis metafisika berasal dari kata “meta” dan “fisika” (Yunani). “meta” berarti sesudah, di belakang atau melampaui, dan “fisika”, berarti alam nyata. Kata fisik (physic) di sini sama dengan “nature”, yaitu alam. Metafisika merupakan cabang dari filsafat yang mempersoalkan tentang hakikat, yang tersimpul di belakang dunia fenomenal. Metafisika melampaui pengalaman, objeknya diluar hal yang ditangkap panca indra. Metafisika mempelajari manusia, namun yang menjadi objek pemikirannya bukanlah manusia dengan segala aspeknya, termasuk pengalamannya yang dapat ditangkap oleh indra. Sosiologi mempelajari manusia dalam bentuk kelompok serta interaksinya yang dapat ditangkap indra serta yang berada dalam pengalaman manusia; begitu juga psikologi, biologi, dan sebagainya. Namun metafisika mempelajari manusia melampaui atau diluar fisik manusia dan gejala-gejala yang dialami manusia. Metafisika mempelajari siapa manusia, apa tujuannya, dari mana asal manusia, dan untuk apa hidup di dunia ini. Jadi metafisika mempelajari manusia jauh melampaui ruang dan waktu. Begitu juga pembahasan tentang kosmos maupun Tuhan, yang dipelajari adalah hakikatnya, di luar dunia fenomenal (dunia gejala). Metafisika dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 1) Ontologi, dan 2) Metafisika khusus. Ontologi mempersoalkan tentang esensi dari yang ada, hakikat adanya dari segala sesuatu wujud yang ada, “ontology is the theory of being qua being”(Runes, 1963,h.219). Sedangkan Metafisika Khusus, mempersoalkan theologi, kosmologi, dan antropologi.
- 49. 50 2. Asumsi Ilmu mengemukakan beberapa asumsi mengenai objek empiris. Ilmu menganggap bahwa objek-objek empiris yang menjadi bidang penelaahannya mempunyai sifat keragaman, memperlihatkan sifat berulang dan semuanya jalin-menjalin secara teratur.Sesuatu peristiwa tidaklah terjadi secara kebetulan namun tiap peristiwa mempunyai pola tetap yang teratur.Bahwa hujan diawali dengan awan tebal dan langit mendung, hal ini bukanlah merupakan suatu kebetulan tetapi memang polanya sudah demikian. Kejadian ini akan berulang dengan pola yang sama. Alam merupakan suatu sistem yang teratur yang tunduk kepada hukum-hukum tertentu. Secara lebih terperinci ilmu mempunyai tiga asumsi mengenai objek empiris. Asumsi pertama menganggap objek-objek tertentu mempunyai keserupaan satu sama lain, umpamanya dalam hal bentuk, struktur, sifat dan sebagainya. Berdasarkan ini maka kita dapat mengelompokkan beberapa objek yang serupa ke dalam satu golongan.Klasifikasi merupakan pendekatan keilmuan yang pertama terhadap objek-objek yang ditelaahnya dan taxonomi merupakan cabang keilmuan yang mula-mula sekali berkembang.Konsep ilmu yang lebih lanjut seperti konsep perbandingan (komparatif) dan kuantitatif hanya dimungkinkan dengan adanya taxonomi yang baik. Asumsi yang kedua adalah anggapan bahwa suatu benda tidak mengalami perubahan dalam jangka waktu tertentu.Kegiatan keilmuan bertujuan mempelajari tingkah laku suatu objek dalam suatu keadaan tertentu.Kegiatan ini jelas tidak mungkin dilakukan bila objek selalu berubah-ubah tiap waktu. Walaupun begitu tidak mungkin kita menuntut adanya kelestarian yang absolut, sebab alam perjalanan waktu tiap benda akan mengalami perubahan. Oleh sebab itu ilmu hanya menuntut adanya kelestarian yang relatif, artinya sifat- sifat pokok dari suatu benda tidak berubah dalam jangka waktu tertentu. Tercakup dalam pengertian ini adalah pengakuan bahwa benda-benda dalam jangka panjang akan mengalami perubahan dan jangka waktu ini berbeda-beda untuk tiap benda. Determinisme merupakan asumsi ilmu yang ketiga. Kita menganggap tiap gejala bukan merupakan suatu kejadian yang bersifat kebetulan. Tiap gejala mempunyai pola tertentu yang bersifat tetap dengan urut-urutan kejadian yang sama. Namun seperti juga dengan asumsi kelestarian, ilmu tidak menuntut adanya hubungan sebab akibat yang mutlak sehingga suatu kejadian tertentu harus selalu diikuti oleh suatu kejadian yang lain. Ilmu tidak