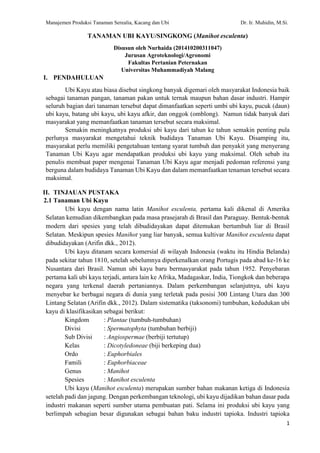
Tanaman ubi kayu
- 1. Manajemen Produksi Tanaman Serealia, Kacang dan Ubi Dr. Ir. Muhidin, M.Si. 1 TANAMAN UBI KAYU/SINGKONG (Manihot esculenta) Disusun oleh Nurhaida (201410200311047) Jurusan Agroteknologi/Agronomi Fakultas Pertanian Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang I. PENDAHULUAN Ubi Kayu atau biasa disebut singkong banyak digemari oleh masyarakat Indonesia baik sebagai tanaman pangan, tanaman pakan untuk ternak maupun bahan dasar industri. Hampir seluruh bagian dari tanaman tersebut dapat dimanfaatkan seperti umbi ubi kayu, pucuk (daun) ubi kayu, batang ubi kayu, ubi kayu afkir, dan onggok (omblong). Namun tidak banyak dari masyarakat yang memanfaatkan tanaman tersebut secara maksimal. Semakin meningkatnya produksi ubi kayu dari tahun ke tahun semakin penting pula perlunya masyarakat mengetahui teknik budidaya Tanaman Ubi Kayu. Disamping itu, masyarakat perlu memiliki pengetahuan tentang syarat tumbuh dan penyakit yang menyerang Tanaman Ubi Kayu agar mendapatkan produksi ubi kayu yang maksimal. Oleh sebab itu penulis membuat paper mengenai Tanaman Ubi Kayu agar menjadi pedoman referensi yang berguna dalam budidaya Tanaman Ubi Kayu dan dalam memanfaatkan tenaman tersebut secara maksimal. II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tanaman Ubi Kayu Ubi kayu dengan nama latin Manihot esculenta, pertama kali dikenal di Amerika Selatan kemudian dikembangkan pada masa prasejarah di Brasil dan Paraguay. Bentuk-bentuk modern dari spesies yang telah dibudidayakan dapat ditemukan bertumbuh liar di Brasil Selatan. Meskipun spesies Manihot yang liar banyak, semua kultivar Manihot esculenta dapat dibudidayakan (Arifin dkk., 2012). Ubi kayu ditanam secara komersial di wilayah Indonesia (waktu itu Hindia Belanda) pada sekitar tahun 1810, setelah sebelumnya diperkenalkan orang Portugis pada abad ke-16 ke Nusantara dari Brasil. Namun ubi kayu baru bermasyarakat pada tahun 1952. Penyebaran pertama kali ubi kayu terjadi, antara lain ke Afrika, Madagaskar, India, Tiongkok dan beberapa negara yang terkenal daerah pertaniannya. Dalam perkembangan selanjutnya, ubi kayu menyebar ke berbagai negara di dunia yang terletak pada posisi 300 Lintang Utara dan 300 Lintang Selatan (Arifin dkk., 2012). Dalam sistematika (taksonomi) tumbuhan, kedudukan ubi kayu di klasifikasikan sebagai berikut: Kingdom : Plantae (tumbuh-tumbuhan) Divisi : Spermatophyta (tumbuhan berbiji) Sub Divisi : Angiospermae (berbiji tertutup) Kelas : Dicotyledoneae (biji berkeping dua) Ordo : Euphorbiales Famili : Euphorbiaceae Genus : Manihot Spesies : Manihot esculenta Ubi kayu (Manihot esculenta) merupakan sumber bahan makanan ketiga di Indonesia setelah padi dan jagung. Dengan perkembangan teknologi, ubi kayu dijadikan bahan dasar pada industri makanan seperti sumber utama pembuatan pati. Selama ini produksi ubi kayu yang berlimpah sebagian besar digunakan sebagai bahan baku industri tapioka. Industri tapioka
- 2. Manajemen Produksi Tanaman Serealia, Kacang dan Ubi Dr. Ir. Muhidin, M.Si. 2 merupakan industri skala besar yang paling berkembang di Lampung. Jumlah perusahaan tapioka yang didaftar pada Dinas Pertanian Lampung Timur saat ini sebanyak 31 perusahaan dengan kapasitas 56.927,08 ton (Anonimous, 2007). Produksi ubi kayu dunia diperkirakan mencapai 184 juta ton pada tahun 2008. Sebagian besar produksi dihasilkan di Afrika 99,1 juta ton dan 33,2 juta ton di Amerika Latin dan Kepulauan Karibia (BPS Indonesia, 2013). Produksi ubi kayu di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat dalam lima tahun terakhir ini dari sebesar 19.321.183 ton pada tahun 2005 menjadi 21.786.691 pada tahun 2009, atau mengalami peningkatan sebesar 11,32% (Departemen Pertanian, 2009). Banyak dijumpai nama lokal dari ubi kayu antara lain singkong, kaspe, budin, sampen dan lain-lain. Tanaman ubi kayu termasuk dalam famili Euphorbiaceae dapat tumbuh dengan mudah hampir di semua jenis tanah dan tahan terhadap serangan hama maupun penyakit. Pada umumnya, umbi ubi kayu dimanfaatkan sebagai bahan pangan sumber karbohidrat (54,2%), industri tepung tapioka (19,70%), industri pakan ternak (1,80%), industri non pangan lainnya (8,50%) dan sekitar 15,80% diekspor (Andrizal, 2003). Berdasarkan sifat fisik dan kimia, ubi kayu merupakan umbi atau akar pohon yang panjang dengan rata-rata bergaris tengah 2-3 cm dan panjang 50-80 cm, tergantung dari jenis ubi kayu yang ditanam. Sifat fisik dan kimia ubi kayu sangat penting artinya untuk pengembangan tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Karakterisasi sifat fisik dan kimia ubi kayu ditentukan olah sifat pati sebagai komponen utama dari ubi kayu. Ubi kayu tidak memiliki periode matang yang jelas karena ubinya terus membesar (Rubatzky and Yamaguchi, 1998). Akibatnya, periode panen dapat beragam sehingga dihasilkan ubi kayu yang memiliki sifat fisik dan kimia yang berbeda – beda. Sifat fisik dan kimia pati seperti bentuk dan ukuran granula, kandungan amilosa dan kandungan komponen non pati sangat dipengaruhi oleh faktor genetik, kondisi tempat tumbuh dan umur tanaman (Moorthy, 2002). Ubi kayu dapat dimanfaatkan untuk keperluan pangan, pakan maupun bahan dasar berbagai industri. Oleh karena itu pemilihan varietas ubi kayu harus disesuaikan untuk peruntukannya. Di daerah dimana ubikayu dikonsumsi secara langsung untuk bahan pangan diperlukan varietas ubi kayu yang rasanya enak dan pulen dan kandungan HCN rendah. Asam sianida (HCN) dikelompokkan sebagai senyawa racun. Asam ini merupakan faktor pembatas dalam pemanfaatan tanaman ubi kayu sebagai pakan karena ternak yang mengkonsumsinya dapat mengalami keracunan (Antari, dkk, 2009). Berdasarkan kandungan HCN ubi kayu dibedakan menjadi ubi kayu manis/tidak pahit, dengan kandungan HCN < 40 mg/kg umbi segar, dan ubikayu pahit dengan kadar HCN ≥ 50 mg/kg umbi segar. Kandungan HCN yang tinggi dapat menyebabkan keracunan bagi manusia maupun hewan, sehingga tidak dianjurkan untuk konsumsi segar. Untuk bahan tape (peuyem) para pengrajin suka umbi ubi kayu yang tidak pahit, rasanya enak dan daging umbi berwarna kekuningan seperti varietas lokal Krentil, Mentega, atau Adira-1. Tetapi untuk industri pangan yang berbasis tepung atau pati ubikayu, diperlukan ubi kayu yang umbinya berwarna putih dan mempunyai kadar bahan kering dan pati yang tinggi. Untuk keperluan industri tepung tapioka, umbi dengan kadar HCN tinggi tidak menjadi masalah karena bahan racun tersebut akan hilang selama pencucian, pemanasan, dan pengeringan dalam proses menjadi tepung dan pati (Antari, dkk, 2009).
- 3. Manajemen Produksi Tanaman Serealia, Kacang dan Ubi Dr. Ir. Muhidin, M.Si. 3 Tanaman ubi kayu terdiri dari dua bagian pokok yaitu umbi dan tops. Tops adalah bagian atas tanaman ubi kayu yang meliputi daun, batang dan cabang ubi kayu. Coch et al. (1973) dalam Abbas et al. (1986). Berikut beberapa organ tanaman ubi kayu : a. Pucuk (daun) ubi kayu Pucuk ubi kayu merupakan bagian atas tanaman yang pada umumnya terdiri dari daun dan tangkai/ ranting-ranting muda; jumlahnya berkisar 7% (daun) dan 12% (ranting). b. Batang ubi kayu Batang ubi kayu mempunyai kulit serta lapisan kayu yang berbentuk bulat dan berongga; terisi oleh lapisan gabus. Pada tanaman yang telah dewasa batang ubi kayu mendominasi persentase bagian tops selain daun dan ranting yakni 89,1%. c. Ubi kayu afkir Pada proses pembuatan gaplek, tepung tapioka maupun bahan olahan ubi kayu yang lain seperti pembuatan snack, tape dan lain-lain; penyiapan bahan baku menyisakan kulit dan bonggol ubi kayu yaitu ubi kayu bagian pangkal yang biasanya keras. Bonggol ubi kayu serta ubi kayu kualitas rendah yang tidak layak diproses inilah yang dikenal dengan istilah ubi kayu afkir. Dapat diberikan kepada ternak dalam keadaan segar maupun kering. d. Kulit ubi kayu Dihasilkan pada proses pengolahan ubi kayu menjadi produk olahan misalnya pada pembuatan gaplek, tapioka maupun aneka bahan pangan asal ubi kayu (snack). Kulit ubi kayu ini merupakan bagian yang cepat terdegradasi di dalam rumen. e. Onggok (gamblong) Merupakan hasil ikutan padat dari pengolahan tepung tapioka. Sebagai ampas pati ubi kayu yang mengandung banyak karbohidrat, onggok dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. 2.2 Potensi Produksi dan Nilai Nutrisi Limbah Ubi Kayu Ubi kayu merupakan bahan pakan yang sangat potensial dan mudah diperoleh hampir di setiap wilayah. Potensi produksi tanaman ubi kayu yang terus meningkat secara otomatis juga meningkatkan limbah ubi kayu dan agroindustrinya sehingga memungkinkan pemanfaatannya sebagai pakan ternak semakin luas. Ubi kayu mengandung protein yang rendah, oleh karena itu, banyak penelitian dilakukan untuk meningkatkan nilai nutrisinya agar dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai pakan ternak. Ruminansia dapat memanfaatkan tidak hanya umbi ubi kayu tetapi juga batang, daun, kulit serta residu dari pengolahan tapioka seperti gamblong/onggok, karena ruminansia punya toleransi yang cukup baik terhadap pakan kualitas rendah. Kandungan nutrisi beberapa limbah dari ubi kayu antara lain daun, kulit dan onggok. Umbi ubi kayu sangat tinggi kandungan energi namun minimal dalam kandungan protein, sebaliknya bagian daun mengandung protein yang cukup tinggi. Secara umum, semua bagian dari tanaman ubi kayu dapat dimanfaatkan sebagai pakan. Bagian daun dapat dijadikan sebagai sumber protein, pemberiannya dalam bentuk kering atau silase. Batang dapat dicampurkan dengan daun sebagai ingredien dalam pakan penguat. Umbi dapat diubah bentuknya menjadi pelet, sedangkan bagian kulit umbi dan onggok dapat dikeringkan terlebih dahulu sebelum digunakan atau dapat digunakan sebagai substrat untuk produksi protein sel tunggal (single cell protein).
- 4. Manajemen Produksi Tanaman Serealia, Kacang dan Ubi Dr. Ir. Muhidin, M.Si. 4 Unsur mineral sangat penting bagi ternak, mineral mempunyai fungsi fisiologis yang tersifat, namun secara umum mineral mempunyai fungsi yang lebih beragam antara lain sebagai: pembentuk tulang dan gigi, mempertahankan keadaan koloidal dari beberapa senyawa dalam tubuh, memelihara keseimbangan asam-basa, sebagai aktivator sistem enzim tertentu, sebagai komponen dari sistem enzim, serta mempunyai sifat yang karakteristik terhadap kepekaan otot dan saraf (Tillman et al., 1998) 2.3 Syarat Tumbuh Tanaman ubi kayu banyak diusahakan di lahan kering dengan berbagai jenis tanah terutama Ultisol, Alfisol, dan Inceptisol. Provinsi Lampung merupakan sentral produksi ubi kayu utama di Indonesia. Di Provinsi Lampung ubi kayu sebagian besar ditanam di lahan Ultisol bersifat masam, Al-dd tinggi dan kandungan hara relatif miskin. Ubi kayu dapat tumbuh dengan baik pada tanah ultisol dengan pH 6,1. Klon yang umum ditanam petani adalah klon unggul UJ-5. Ubi kayu merupakan tanaman tropis. Wilayah pengembangan ubi kayu berada pada 30˚ LU dan 30˚ LS. Namun demikian, untuk dapat tumbuh, berkembang dan berproduksi, tanaman ubi kayu menghendaki persyaratan iklim tertentu (Tim Prima Tani, 2006). a. Suhu Tanaman ubi kayu menghendaki suhu antara 18˚-35˚C. Pada suhu di bawah 10˚C pertumbuhan tanaman ubi kayu akan terhambat. Kelembaban udara yang dibutuhkan ubi kayu adalah 65% (Suharno et al., 1999). Namun demikian, untuk berproduksi secara maksimum tanaman ubi kayu membutuhkan kondisi tertentu, yaitu pada dataran rendah tropis, dengan ketinggian 150 m di atas permukaan laut (dpl), dengan suhu rata-rata antara 25˚-27˚C, tetapi beberapa varietas dapat tumbuh pada ketinggian di atas 1500 m dpl (Anonim, 2003). c. Curah hujan Tanaman ubi kayu dapat tumbuh dengan baik apabila curah hujan cukup, tetapi tanaman ini juga dapat tumbuh pada curah hujan rendah (< 500 mm), ataupun tinggi (5000 mm). Curah hujan optimum untuk ubi kayu berkisar antara 760- 1015 mm per tahun. Curah hujan terlalu tinggi mengakibatkan terjadinya serangan jamur dan bakteri pada batang, daun dan umbi apabila drainase kurang baik (Anonim, 2003, Suharno et al., 1999). Waktu tanam ubi kayu yang baik untuk lahan tegalan adalah pada awal musim penghujan (MH I), sedangkan pada lahan sawah tadah hujan adalah setelah panen padi (MH II), karena selama pertumbuhan vegetatif aktif (3-4 bulan pertama) ubi kayu membutuhkan air. Untuk pertumbuhan selanjutnya ubi kayu tidak terlalu banyak membutuhkan air. 2.4 Budidaya Tanaman Ubi Kayu a. Penyiapan Bibit Sumber bibit ubi kayu berasal dari pembibitan tradisional berupa stek yang diambil dari tanaman yang berumur lebih dari 8 bulan dengan kebutuhan bibit untuk sistem budidaya ubi kayu monokultur adalah 10.000 - 15.000 stek ha-1 (Tim Prima Tani, 2006). Untuk satu batang ubi kayu hanya diperoleh 10 - 20 stek sehingga luas areal pembibitan minimal 20% dari luas areal yang akan ditanami ubi kayu. Asal stek, diameter bibit, ukuran stek, dan lama penyimpanan bibit berpengaruh terhadap daya tumbuh dan hasil ubi kayu. Bibit yang dianjurkan untuk ditanam adalah stek dari batang bagian tengah dengan diameter batang 2-3 cm, panjang 15-20 cm, dan tanpa penyimpanan.
- 5. Manajemen Produksi Tanaman Serealia, Kacang dan Ubi Dr. Ir. Muhidin, M.Si. 5 b. Penyiapan Lahan Penyiapan lahan berupa pengolahan tanah bertujuan untuk : (1) Memperbaiki struktur tanah; (2) Menekan pertumbuhan gulma; dan (3) Menerapkan sistem konservasi tanah untuk memperkecil peluang terjadinya erosi. Tanah yang baik untuk budidaya ubi kayu adalah memiliki struktur gembur atau remah yang dapat dipertahankan sejak fase awal pertumbuhan sampai panen. Kondisi tersebut dapat menjamin sirkulasi O2 dan CO2 di dalam tanah terutama pada lapisan olah sehingga aktivitas jasad renik dan fungsi akar optimal dalam penyerapan hara. Menurut Tim Prima Tani (2006), tanah sebaiknya diolah dengan kedalaman sekitar 25 cm, kemudian dibuat bedengan dengan lebar bedengan dan jarak antar bedengan disesuaikan jarak tanam ubi kayu, yaitu 80-130 cm x 60-100 cm. Pada lahan miring atau peka erosi, tanah perlu dikelola dengan sistem konservasi, yaitu : (1) tanpa olah tanah; (2) olah tanah minimal; dan (3) olah tanah sempurna sistem guludan kontur. Pengolahan minimal (secara larik atau individual) efektif mengendalikan erosi tetapi hasil ubi kayu seringkali rendah dan biaya pengendalian gulma relatif tinggi. Dalam hal ini tanah dibajak (dengan traktor 3-7 singkal piring atau hewan tradisional) dua kali atau satu kali yang diikuti dengan pembuatan guludan (ridging). Untuk lahan peka erosi, guludan juga berperan sebagai pengendali erosi sehingga guludan dibuat searah kontur. c. Penanaman Stek ditanam di guludan dengan jarak antar barisan tanaman 80-130 cm dan dalam barisan tanaman 60-100 cm untuk sistem monokultur, sedangkan jarak tanam ubi kayu untuk sistem tumpangsari dengan kacang tanah, kedelai, atau kacang hijau adalah 200 x 100 cm dan jarak tanam tanaman sela yang efektif mengendalikan erosi dan produktivitasnya tinggi adalah 40 cm antara barisan dan 10-15 cm dalam barisan. Penanaman stek ubi kayu disarankan pada saat tanah dalam kondisi gembur dan lembab atau ketersediaan air pada lapisan olah sekitar 80% dari kapasitas lapang. Tanah dengan kondisi tersebut akan dapat menjamin kelancaran sirkulasi O2 dan CO2 serta meningkatkan aktivitas mikroba tanah sehingga dapat memacu pertumbuhan daun untuk menghasilkan fotosintat secara maksimal dan ditranslokasikan ke dalam umbi secara maksimal pula. Posisi stek di tanah dan kedalaman tanam dapat mempengaruhi hasil ubikayu. Stek yang ditanam dengan posisi vertikal (tegak) dengan kedalaman sekitar 15 cm memberikan hasil tertinggi baik pada musim hujan maupun musim kemarau. Penanam stek dengan posisi vertikal juga dapat memacu pertumbuhan akar dan menyebar merata di lapisan olah. Stek yang ditanam dengan posisi miring atau horizontal (mendatar), akarnya tidak terdistribusi secara merata seperti stek yang ditanam vertikal pada kedalaman 15 cm dan kepadatannya rendah. d. Pemupukan Pemupukan sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan produksi ubi kayu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hara yang hilang terbawa panen untuk setiap ton umbi segar adalah 6,54 kg N; 2,24 kg P2O5; dan 9,32 K2O ha-1 musim-1, dimana 25% N, 30% P2O5, dan 26% K2O terdapat di dalam umbi. Berdasarkan perhitungan tersebut, hara yang terbawa panen ubi kayu pada tingkat hasil 30 ton ha-1 adalah 147,6 kg N; 47,4 kg P2O5; dan 179,4 kg K2O ha-1. Untuk mendapatkan hasil tinggi tanpa menurunkan tingkat kesuburan tanah, hara yang terbawa panen tersebut harus diganti melalui pemupukan setiap musim. Tanpa pemupukan akan terjadi pengurasan hara sehingga tingkat kesuburan tanah menurun. Pemupukan yang tidak rasional dan tidak berimbang juga dapat merusak kesuburan tanah. Pemupukan harus dilakukan secara efisien sehingga didapatkan produksi tanaman dan
- 6. Manajemen Produksi Tanaman Serealia, Kacang dan Ubi Dr. Ir. Muhidin, M.Si. 6 pendapatan yang diharapkan. Umbi ubi kayu adalah tempat menyimpan sementara hasil fotosintesis yang tidak digunakan untuk pertumbuhan vegetatif tanaman. Dengan demikian, pertumbuhan vegetatif yang berlebihan akibat dosis pemupukan yang tinggi dapat menurunkan hasil panen. Efisiensi pemupukan dipengaruhi oleh jenis pupuk, varietas, jenis tanah, pola tanam, dan keberadaan unsur lainnya di dalam tanah. Untuk pertanaman ubi kayu sistem monokultur, disarankan pemberian pupuk anorganik sebanyak 200 kg Urea, 100 kg SP36, dan 100 kg KCl hektar-1 yang diberikan sebanyak tiga tahap. Tahap I umur 7 - 10 hari diberikan 50 kg Urea, 100 kg SP36, dan 50 kg KCl ha-1, dan tahap II umur 2 - 3 bulan diberikan 75 kg Urea dan 50 kg KCl ha-1, serta tahap III umur 5 bulan diberikan lagi 75 kg Urea ha-1. Pupuk organik (kotoran ternak) dapat digunakan sebanyak 1 -2 ton ha-1 pada saat tanam. e. Pemeliharaan Tanaman Kelemahan ubi kayu pada fase pertumbuhan awal adalah tidak mampu berkompetisi dengan gulma. Periode kritis atau periode tanaman harus bebas gangguan gulma adalah antara 5 - 10 minggu setelah tanam. Bila pengendalian gulma tidak dilakukan selama periode kritis tersebut, produktivitas dapat turun sampai 75% dibandingkan kondisi bebas gulma. Untuk itu, penyiangan diperlukan hingga tanaman bebas dari gulma sampai berumur sekitar 3 bulan. Menurut Wargiono dkk. (2006), pada bulan ke-4 kanopi ubi kayu mulai menutup permukaan tanah sehingga pertumbuhan gulma mulai tertekan karena kecilnya penetrasi sinar matahari di antara ubi kayu. Oleh karena itu, kondisi bebas gulma atau penyiangan pada bulan ke-4 tidak diperlukan karena tidak lagi mempengaruhi hasil. Pada saat penyiangan, juga dilakukan pembumbunan, yaitu umur 2 - 3 bulan. Pemeliharaan selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah pembatasan tunas. Pada saat tanaman berumur 1 bulan dilakukan pemilihan tunas terbaik, tunas yang jelek dibuang sehingga tersisa dua tunas yang paling baik. Sementara itu, pengendalian hama dan penyakit tidak perlu dilakukan karena sampai saat ini tanaman ubi kayu tidak memerlukan pengendalian hama dan penyakit. Bila di lapangan diperlukan pengendalian hama penyakit, maka tindakan yang dilakukan sbb.: 1. Tungau/kutu merah (Tetranychus bimaculatus) dikendalikan secara mekanik dengan memetik daun sakit pada pagi hari dan kemudian dibakar. Pengendalian secara kimiawi menggunakan akarisida. 2. Kutu sisik hitam (Parasaissetia nigra) dan kutu sisik putih (Anoidomytilus albus) dikendalikan secara mekanis dengan mencabut dan membatasi tanaman sakit menggunakan bibit sehat. Pengendalian secara kimiawi menggunakan perlakuan stek insektisida seperti tiodicarb dan oxydemeton methil. 3. Penyakit bakteri B. manihotis dan X. manihotis menyerang daun muda dan P. solanacearum menyerang bagian akar tanaman sehingga tanaman layu dan mati. Pengendalian dapat dilakukan menggunakan varietas tahan/agak tahan. 4. Penyakit lain adalah cendawan karat daun (Cercospora sp.), perusak batang (Glomerell sp.), dan perusak umbi (Fusarium sp.). Pengendalian dianjurkan menggunakan larutan belerang 5%. 5. Penyakit virus mosaik (daun mengerting) belum ada rekomendasi pengendaliannya. f. Panen Panen yang paling baik adalah pada saat kadar karbohidrat mencapai tingkat maksimal. Bobot umbi meningkat dengan bertambahnya umur panen, sedangkan kadar pati cenderung stabil pada umur 7 - 9 bulan. Hal ini menunjukan bahwa umur panen ubi kayu fleksibel. Tim
- 7. Manajemen Produksi Tanaman Serealia, Kacang dan Ubi Dr. Ir. Muhidin, M.Si. 7 Prima Tani (2006) menganjurkan panen pada saat tanaman berumur 8 - 10 bulan dan dapat ditunda hingga berumur 12 bulan. Fleksibilitas umur panen tersebut memberi peluang petani melakukan pemanenan pada saat harga jual tinggi. Dalam kurun waktu 5 bulan tersebut (panen 8 - 12 bulan) dapat dilakukan pemanenan bila harga jual ubi kayu naik karena tidak mungkin melakukan penyimpanan ubi kayu di gudang penyimpanan seperti halnya tanaman pangan lainnya. Pembeli biasanya akan membeli ubi kayu dalam bentuk segar yang umurnya tidak lebih dari 2 x 24 jam dari saat panen. III. KESIMPULAN Berdasarkan paparan di atas, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut : a. Ubi kayu dapat dimanfaatkan untuk keperluan pangan, pakan maupun bahan dasar berbagai industri. Produksi ubi kayu di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat dalam lima tahun terakhir. b. Ubi kayu merupakan bahan pakan yang sangat potensial dan mudah diperoleh hampir di setiap wilayah. Ruminansia dapat memanfaatkan tidak hanya umbi ubi kayu tetapi juga batang, daun, kulit serta residu dari pengolahan tapioka seperti gamblong/onggok, karena ruminansia punya toleransi yang cukup baik terhadap pakan kualitas rendah. c. Tanaman Ubi Kayu cocok pada tanah Ultisol, Alfisol, dan Inceptisol, suhu antara 18˚ - 35˚c, serta curah hujan yang optimal antara 760- 1015 mm per tahun. d. Teknik budidaya Tanaman Ubi Kayu terdapat beberapa tahap yaitu penyiapan bibit, penyiapan lahan, penanaman, pemupukan, pemeliharaan tanaman, dan panen.
- 8. Manajemen Produksi Tanaman Serealia, Kacang dan Ubi Dr. Ir. Muhidin, M.Si. 8 DAFTAR PUSTAKA Abbas, S., A. Halim, A. Ahmad dan S.T. Amidarmo. 1986. Limbah Tanaman Ubi Kayu. Dalam: Limbah Hasil Pertanian. Kantor Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Pangan. Andrizal. 2003. Potensi, tantangan dan kendala pengembangan agroindustri ubi kayu dan kebijakan industri perdagangan yang diperlukan. Pemberdayaan Agribisnis Ubi Kayu Mendukung Ketahanan Pangan. Balai Penelitian Tanaman Kacang-kacangan dan Umbi- umbian. Anonim, 2003. Tapioca :Nature of cassava. http://foodmarketexchange.com/datacenter/product/feedstuff/tapioca/detail/dc_pi_ft_tap ioca_0205.htm#. diakses tgl 24 September 2017. Anonim. 2007. Pengolahan Tepung Tapioka. Sipuk-Bank Sentral Republik Indonesia. Arifin, B. 2012. Kebijakan Perdagangan Pangan. Penerbit Universitas Lampung. Bandar Lampung. Antari, R. dan U. Umiyasih. 2009. Pemanfaatan Tanaman Ubi Kayu dan Limbahnya secara Optimal Sebagai Pakan Ternak Ruminansia. Wartazoa Vol. 19 No. 4 Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. 2013. Statistik Lahan Pertanian 2014. BPS Provinsi Lampung. Departemen Pertanian. 2009. Basis Data Pertanian. http://database.deptan.go.id/bdsp/hasil_kom_asp. (30 Maret 2009). Moorthy, S. N. 2002. Physicochemical and Functional Properties Of Tropical Tuber Starches. Starch/ Stärke. 54 : 559-592. Rubatzky, V.E dan Yamaguchi. 1988. Sayuran Dunia; Prinsip. Produksi dan Gizi Jilid 1. Institut Teknologi Bandung. Bandung. 163-177. Suharno et al., 1999. Suharno. Djasmin. Rubiyo. Dasiran. 1999. Budi Daya Ubi Kayu. Kendari: Badan Peneliti dan Pengembangan Pertanian. Tillman, A.D., H. Hartadi, S. Reksohadiprodjo. S. Prawirokusumo dan S. Lebdosoekojo. 1998. Ilmu Makanan Ternak Dasar. UGM Press. Yogyakarta. Tim Prima Tani. 2006. Inovasi Teknologi Unggulan Tanaman Pangan Berbasis Agroekosistem Mendukung Prima Tani. Puslitbangtan Bogor; 40 hlm. Wargiono, J. Hasanudin. Suyanto. 2006. Teknologi Produksi Ubi kayu Mendukung Industri Bioetanol. Jakarta: Badan penelitian dan Pengembangan Pertanian.
