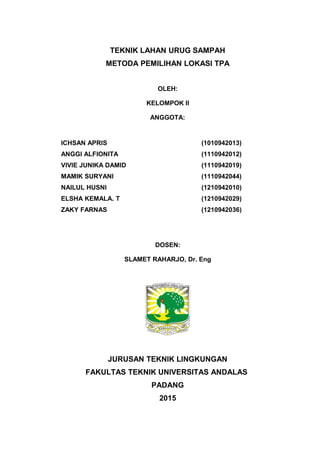
Makalah tlus pemilihan lokasi tpa klp 2
- 1. TEKNIK LAHAN URUG SAMPAH METODA PEMILIHAN LOKASI TPA OLEH: KELOMPOK II ANGGOTA: ICHSAN APRIS (1010942013) ANGGI ALFIONITA (1110942012) VIVIE JUNIKA DAMID (1110942019) MAMIK SURYANI (1110942044) NAILUL HUSNI (1210942010) ELSHA KEMALA. T (1210942029) ZAKY FARNAS (1210942036) DOSEN: SLAMET RAHARJO, Dr. Eng JURUSAN TEKNIK LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS PADANG 2015
- 2. BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) merupakan tempat dimana sampah mencapai tahap akhir dalam pengelolaannya, dimana diawali dari sumber, pengumpulan, pemindahan atau pengangkutan, serta pengolahan dan pembuangannya. TPA merupakan tempat dimana sampah diisolasi secara aman agar tidak menimbulkan kerusakan atau dampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu diperlukan penyediaan fasilitas dan penanganan yang benar agar pengelolaan sampah tersebut dapat terlaksanan dengan baik. Pembuangan limbah ke dalam tanah (land disposal) merupakan cara yang sering dilakukan dalam pengelolaan limbah, namun pengolahan limbah dengan cara ini tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Pengelolaan limbah dengan lahan urug akan tetap menjadi bagian yang sangat sulit untuk dihilangkan dalam pengolahan limbah. Salah satu kendala pembatas dalam penerapan metoda pengurugan limbah dalam tanah (landfilling atau lahan-urug) adalah bagaimana memilih lokasi yang cocok baik dilihat dari sudut kelangsungan pengoperasian, maupun dari sudut perlindungan terhadap lingkungan hidup. Aspek teknis sebagai penentu utama untuk digunakan adalah aspek yang terkait dengan hidrologi dan hidrogeologi site. 1.2 Tujuan Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah: 1. Untuk mengetahui pemilihan lokasi TPA menurut SNI-T-11-1991-03 dan SNI 19-3241-1994? 2. Untuk mengetahui pemilihan lokasi TPA menurut metode Le Grand? 3. Untuk mengetahui pemilihan lokasi TPA menurut metode Hagerty? 1.3 Rumusan Masalah Rumusan masalah yang akan dibahas pada makalah ini adalah: 1. Bagaimana pemilihan lokasi TPA menurut SNI-T-11-1991-03 dan 19-3241- 1994? 2. Bagaimana pemilihan lokasi TPA menurut metode Le Grand?
- 3. 3. Bagaimana pemilihan lokasi TPA menurut metode Hagerty?
- 4. BAB II ISI 2.1 Pengertian Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Pembuangan akhir sampah (TPA) merupakan proses terakhir dalam siklus pengelolaan persampahan formal. Untuk fase ini dapat menggunakan berbagai metode dari yang sederhana hingga tingkat teknologi tinggi. Secara ideal, pertimbangan utama dalam pemilihan lokasi sebuah landfill adalah didasarkan atas berbagai aspek, terutama (Damanhuri, 2008): − Kesehatan masyarakat; − Lingkungan hidup; − Biaya; dan − Sosio-ekonomi Pertimbangan utama yang harus selalu dimasukkan dalam penentuan lokasi site adalah (EPA 530-R-95-023): − Mempertimbangkan penerimaan masyarakat yang akan terkena dampak; − Konsisten dengan land-use planning di daerah tersebut; − Mudah dicapai dari jalan utama; − Mempunyai tanah penutup yang mencukupi; − Berada pada daerah yang tidak akan terganggu dengan dioperasikan landfill tersebut; − Mempunyai kapasitas tampung yang cukup besar, biasanya 10 sampai 30 tahun; − Tidak memberatkan dalam pendanaan pada saat pengembangan, pengoperasian; − penutupan, pemeliharaan setelah ditutup, dan bahkan biaya yang terkait dengan upaya remediasi; − Rencana pengoperasian hendaknya terkait dengan upaya kegiatan lain yang sangat dianjurkan, yaitu daur-ulang. Di samping aspek-aspek lain yang sangat penting, seperti aspek politis dan legal yang berlaku disuatu daerah atau negara. Aspek kesehatan masyarakat berkaitan langsung dengan manusia, terutama kenaikan mortalitas (kematian), morbiditas (penyakit), serta kecelakaan karena operasi sarana tersebut. Aspek
- 5. lingkungan hidup terutama berkaitan dengan pengaruhnya terhadap ekosistem akibat pengoperasian sarana tersebut, termasuk akibat transportasi dan sebagainya. Aspek biaya berhubungan dengan biaya spesifik antara satu lokasi dengan lokasi yang lain, terutama dengan adanya biaya ekstra pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan. Aspek sosio-ekonomi berhubungan dengan dampak sosial dan ekonomi terhadap penduduk sekitar lahan yang dipilih. Walaupun dua lokasi yang berbeda mempunyai pengaruh yang sama dilihat dari aspek sebelumnya, namun reaksi masyarakat setempat dengan dibangunnya sarana tersebut bisa berbeda (Damanhuri, 2008). Proses pemilihan lokasi lahan-urug idealnya hendaknya melalui suatu tahapan penyaringan. Dalam setiap tahap, lokasi-lokasi yang dipertimbangkan akan dipilih dan disaring. Pada setiap tingkat, beberapa lokasi dinyatakan gugur, berdasarkan kriteria yang digunakan di tingkat tersebut. Penyisihan tersebut akan memberikan beberapa calon lokasi yang paling layak dan baik untuk diputuskan pada tingkat final oleh pengambil keputusan. Di negara industri, penyaringan tersebut paling tidak terdiri dari tiga tingkat tahapan, yaitu (Damanhuri, 2008): − penyaringan awal; − penyaringan individu; dan − penyaringan final. Penyaringan awal biasanya bersifat regional biasanya dikaitkan dengan tata guna dan peruntukan yang telah digariskan di daerah tersebut. Secara regional, daerah tersebut diharapkan dapat mendefinisikan secara jelas lokasi-lokasi mana saja yang dianggap tidak/kurang layak untuk lokasi pengurugan limbah. Pada taraf ini parameter yang digunakan hanya sedikit. Tahap kedua dari tahap penyisihan ini adalah penentuan lokasi secara individu, kemudian dilakukan evaluasi dari tiap individu. Pada tahap ini tercakup kajian- kajian yang lebih mendalam, sehingga lokasi yang tersisa akan menjadi sedikit. Parameter beserta kriteria yang diterapkan akan menjadi lebih spesifik dan lengkap. Lokasi-lokasi tersebut kemudian dibandingkan satu dengan yang lain, misalnya melalui pembobotan. Ada 3 metode dalam pemilihan lokasi TPA, yaitu (Damanhuri, 2008): − SNI 19-3241-1994 − Metode Le Grand
- 6. − Metode Hagerty Tahap terakhir adalah tahap penentuan. Penyaringan final ini diawali dengan pematangan aspek-aspek teknis yang telah digunakan di atas, khususnya yang terkait dengan aspek sosio-ekonomi masyarakat dimana lokasi calon berada. Tahap ini kemudian diakhiri dengan aspek penentu, yaitu oleh pengambil keputusan suatu daerah. Aspek ini bersifat politis, karena kebijakan pemerintah daerah/pusat akan memegang peranan penting. Kadangkala pemilihan akhir ini dapat mengalahkan aspek teknis yang telah disiapkan sebelumnya (Damanhuri, 2008). 2.2 Pemilihan Lokasi TPA Menurut SNI 19-3241-1994 Ketentuan Teknis Ketentuan teknis mengatur ketentuan pola ruang pada masing-masing zona, yakni zona penyangga dan zona budi daya terbatas. Penentuan jenis zona yang akan diatur dalam kawasan sekitar TPA sesuai dengan kondisi TPA yang ada, sebagaimana tercantum dalam ketentuan umum. Pemanfaatan ruang yang diatur dalam pedoman akan berbeda untuk tiap klasifikasi TPA. Ketentuannya adalah sebagai berikut: 2.2.1 TPA Baru atau yang Direncanakan 2.2.1.1 Zona Penyangga 1) Zona penyangga sesuai dengan Pedoman Pengoperasian dan Pemeliharaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan Sistem Controlled Landfill dan Sanitary Landfill dengan jarak 0 – 500 meter. Pemanfaatan lahannya ditentukan sebagai berikut: a. 0 – 100 meter : diharuskan berupa sabuk hijau; dan b. 101 – 500 meter : pertanian non pangan dan hutan. 2) Ketentuan pemanfaatan ruang: a. Sabuk hijau dengan tanaman keras yang boleh dipadukan dengan tanaman perdu terutama tanaman yang dapat menyerap racun dengan ketentuan sebagai berikut: a) Jenis tanaman adalah tanaman tinggi dikombinasi dengan tanaman perdu yang mudah tumbuh dan rimbun terutama tanaman yang dapat menyerap bau; dan b) Kerapatan pohon adalah minimum 5 m.
- 7. b. Pemrosesan sampah utama on situ. c. Instalasi pengolahan sampah menjadi energi, atau instalasi pembakaran (incenerator) bersama unit pengelolaan limbahnya. d. Kegiatan budi daya perumahan tidak diperbolehkan pada zona penyangga. 3) Kriteria teknis: a. Tidak menggunakan air tanah setempat dalam kegiatan pengolahan sampah; b. Ketersediaan sistem drainase yang baik; dan c. Ketersediaan fasilitas parkir dan bongkar muat sampah terpilah yang akan didaur ulang di lokasi lain. 4) Pengelolaan: a. Jalan masuk ke TPA, sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal Bina Marga, dipersyaratkan: a) Dapat dilalui truk sampah dua arah dengan lebar badan jalan minimum 7 meter; b) Jalan kelas I dengan kemampuan memikul beban 10 ton dan kecepatan 30 km/jam. b. Drainase permanen terpadu dengan jalan dan bila diperlukan didukung oleh drainase lokal tak permanen. c. Sabuk hijau yang dimaksudkan untuk zona penyangga adalah ruang dengan kumpulan pohon dan bukan sekedar deretan pohon yang bila dimungkinkan mempunyai nilai ekonomi. d. Tanaman yang direkomendasikan adalah yang sesuai dengan kondisi alam setempat, termasuk iklim, rona fisik, dan kondisi lapisan tanah. Spesies yang direkomendasikan termasuk: a) Callophyllum Inophyllum L. Nama lokal: Nyamplung, Bintangur laut. Famili: Guttiferae. Tinggi sampai 20 meter. b) Dalbergia Latifotia Roxb. Nama lokal: Sonokeling. Famili: Leguminosae. Bentuk mahkota bulat dan letaknya kurang dari 5.00 meter. c) Michelia Champaca L. Nama lokal: Cempaka kuning. Famili: Magnoliaceae. Berbunga kuning dan wangi sehingga cocok untuk TPA yang terletak pada lokasi padat atau pada bagian dari lokasi pariwisata.
- 8. d) Mimusop Elengi L. Nama lokal: Tanjung. Famili: Sapotaceae. Tinggi kira-kira 13-27 meter. e) Schleichera Trijuga Willd. Nama lokal: Kesambi. Famili: Sapindaceae. Tinggi kira-kira 25 meter. Mahkota berbentuk bulat dan letaknya kurang dari 5 meter. f) Swietenia Mahagoni Jacq. Nama lokal: Mahoni. Tinggi 10-30 meter. 2.2.1.2 Zona Budi Daya Terbatas 1) Zona budi daya terbatas untuk TPA baru dengan sistem pengurugan berlapis bersih tidak diperlukan. 2) Zona budi daya terbatas untuk sistem pengurugan berlapis terkendali ditentukan sejauh 0 – 300 meter dari batas terluar zona inti. Pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut: a. Rekreasi dan RTH;Industri terkait pengolahan sampah; b. pengolahan kompos, pendaurulangan sampah, dan lain-lain; c. Pertanian non pangan; d. Permukiman di arah hulu TPA bersangkutan diperbolehkan dengan persyaratan tertentu untuk menghindari dampak pencemaran lindi pada daerah hilir TPA. Persyaratan tersebut termasuk sistem drainase yang baik, penyediaan air bersih yang tidak bersumber dari air tanah setempat; e. Fasilitas pemilahan, pengemasan, dan penyimpanan sementara. 3) Kriteria teknis: a. Tersedia akses dan jaringan jalan yang baik; b. Tersedia drainase yang memadai; c. Tersedia sistem pembuangan limbah cair yang baik untuk fasilitas- fasilitas pengolahan sampah yang menghasilkan limbah; d. Tersedia pasokan air dan tidak menggunakan air tanah setempat dalam proses produksi dan kegiatan penunjang lain di dalam kawasan; e. Tersedia parkir dan bongkar muatan sampah dan muat sampah terpilah yang akan didaur ulang di lokasi lain; f. Lebar jalan dan ruang terbuka memungkinkan manuver kendaraan pengangkut sampah dua arah, baik yang sedang bergerak, maupun yang sedang membongkar muatan; g. Penggunaan lahan pada zona budi daya terbatas.
- 9. 2.2.1.3 Zona Budi Daya Pola ruang dalam zona budi daya ditentukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang berlaku, RDTR dan peraturan zonasi yang telah ditetapkan untuk kawasan bersangkutan. 2.2.2 TPA Lama atau yang Sedang Dioperasikan 2.2.2.1 Zona Penyangga 1) Zona penyangga telah tersedia dalam TPA. 2) Pada TPA yang belum memiliki zona penyangga ditetapkan zona penyangga pada area 0 – 500 meter sekeliling TPA dengan pemanfaatan sebagai berikut: a. 0 – 100 meter diharuskan berupa sabuk hijau; b. 101 – 500 meter pertanian non pangan, hutan. 2.2.2.2 Zona Budi Daya Terbatas 1) Zona budi daya terbatas tidak diperlukan pada TPA lama yang menggunakan sistem pengurugan berlapis bersih. 2) Zona budi daya terbatas ditentukan pada TPA lama yang menggunakan sistem pengurugan berlapis terkendali pada jarak 501 – 800 meter dari batas terluar tapak TPA. Pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut: a. Rekreasi dan RTH; b. Industri terkait sampah; c. Pertanian non pangan; dan d. Permukiman di arah hilir bersyarat. e. Permukiman yang telah ada sebelumnya harus memperhatikan persyaratan-persyaratan teknis dalam penggunaan air tanah. Khusus untuk air minum disarankan untuk tidak menggunakan air tanah. 2.2.2.3 Zona Budi Daya Zona budi daya ditentukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah: RTRW, RDTR dan peraturan zonasi dengan memperhatikan kembali kesesuaian pemanfaatan ruang dan aktifitas pada zona budidaya terhadap potensi dampak yang ditimbulkan dari kegiatan TPA sesuai dengan ketentuan khusus.
- 10. 2.2.3 TPA Pascalayan 2.2.3.1 Penambangan Sampah untuk Diolah In Situ dan Gasnya 1) Zona penyangga ditentukan pada area 0 – 500 meter sekeliling TPA, dengan pola ruang sebagai berikut: a. 0 – 100 m : sabuk hijau tanaman keras dan perluasan instalasi pengolahan sampah; dan b. 101 – 500 m : pertanian tanaman non pangan. 2) Zona budi daya terbatas tidak diperlukan. 3) Zona budi daya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. 2.2.3.2 Pemanfaatan Kembali sebagai TPA 1) Zona penyangga ditentukan pada area 0 – 500 meter sekeliling TPA, dengan pola ruang sebagai berikut: a. 0 – 100 m : sabuk hijau tanaman keras dan perluasan instalasi pengolahan sampah; dan b. 101 – 500 m : pertanian tanaman non pangan. 2) Zona budi daya terbatas tidak diperlukan baik pada TPA yang akan digunakan kembali dengan sistem maupun pengurugan berlapis bersih. 3) Zona budi daya terbatas pada TPA yang akan digunakan kembali dengan sistem pengurugan berlapis terkendali ditentukan pada jarak 501-800 meter. Pola ruang adalah sebagai berikut: a. Rekreasi dan RTH; b. Industri terkait sampah; c. Pertanian non pangan; dan d. Permukiman di arah hilir bersyarat. 4) Zona budi daya ditentukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. 5) Penentuan jarak dan zona bersifat fleksibel mengikuti hasil kajian dampak TPA terhadap sekitarnya. 2.2.3.3 Penggunaan Lain 1) Di dalam TPA diatur menurut pedoman yang ada. 2) Industri konversi energi sampah dan penambangan sampah akan mengikuti ketentuan pada kawasan industri. 3) TPA baru boleh dipakai untuk keperluan lain setelah berusia 20 tahun tanpa persyaratan khusus.
- 11. Ketentuan Khusus 1) Untuk dapat menyelenggarakan penataan ruang yang sesuai pada zona penyangga dan budi daya terbatas yang telah dihuni oleh masyarakat atau telah dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, maka kepada masyarakat akan diberikan kompensasi. 2) Pada kawasan yang masuk ke dalam zona penyangga dilakukan relokasi. 3) Pada kawasan yang masuk ke dalam zona budi daya terbatas, apabila memungkinkan untuk mengosongkan lahan tersebut, maka dilakukan relokasi. 4) Apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan relokasi, permukiman yang berada pada kawasan tersebut harus mengikuti peraturan yang disesuaikan dengan kebijakan lokal melalui: a. Arahan pengenaan insentif dan disinsentif dalam meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang; b. Memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rtrw, rdtr, dan peraturan zonasi; dan c. Meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang. 5) Insentif diberikan untuk mendorong dilakukannya relokasi pemanfaatan budidaya di kawasan tersebut dan memberikan eksternalitas positif keberadaan TPA di kawasan tersebut terhadap wilayah sekitarnya berupa: a. Pemberian kompensasi; b. Imbalan; c. Sewa lahan dan urun saham; d. Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur; e. Kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah; dan/atau f. Kemudahaan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari Daerah pemberi manfaat. 6) Disinsentif diberikan untuk menghambat dan membatasi kegiatan dalam zona budidaya kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif kepada lingkungan dan masyarakat, berupa:
- 12. a. Kewajiban pemberian kompensasi; b. Pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah; c. Kewajiban membayar imbalan; d. Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur; dan/atau e. Pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari Daerah pemberi manfaat. 7) Dalam menjaga tertib dan tegaknya peraturan dalam mengatasi pelanggaranan penyelenggaraan penataan ruang di kawasan sekitar TPA diberlakukan pengenaan sanksi terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau izin pemanfaatan ruang khususnya dalam pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya. Tata cara pengenaan saksi terhadap pelanggaraan penyelenggaraan penataan ruang berupa: peringatan tertulis; penghentian kegiatan sementara; penghentian sementara pelayanan umum; penutupan lokasi; pencabutan izin; penolakan izin; pembatalan izin; pembongkaran bangunan; pemulihan fungsi ruang 8) Pemberian insentif disinsentif dan sanksi dilakukan dalam jangka waktu tertentu selama kawasan tersebut mendapatkan efek negatif dari keberadaan TPA, yang dibuktikan dengan kajian lingkungan yang menunjukkan terdapatnya hal-hal berikut: a. Kondisi air tanah yang buruk, tidak sesuai dengan standar baku mutu air bersih; b. Padatnya populasi vektor penyakit yang diduga kuat berasal dari TPA, seperti lalat dan tikus; c. Buruknya kualitas udara akibat dari proses pengelolaan sampah; dan d. Dampak negatif lain yang ditimbulkan oleh TPA. 2.3 Pemilihan Lokasi TPA Menurut SNI-T-11-1991-03 Pemilihan lokasi TPA sampah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: TPA sampah tidak boleh berlokasi di danau, sungai dan laut. Kriteria Kriteria pemilihan lokasi TPA sampah dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: 1. Kriteria regional, yaitu kriteria yang digunakan untuk menentukan zona layak atau zona tidak layak sebagai berikut:
- 13. a. Kondisi geologi: tidak boleh di zona bahaya geologi. b. Kondisi hidrogeologi: 1). Tidak boleh mempunyai muka air tanah kurang dari 3 meter 2). Tidak boleh kelulusan tanah lebih besar dari 10-6 cm/det 3). Jarak terhadap sumber air minum harus lebih besar dari 100 meter di hilir aliran. 4). Dalam hal tidak ada zona yang memenuhi kriteria-kriteria tersebut di atas, maka harus diadakan masukan teknologi. c. Kemiringan zona harus kurang dari 20%. d. Jarak dari lapangan terbang harus lebih besar dari 3.000 meter untuk penerbangan turbo jet dan harus lebih besar dari 1.500 meter untuk jenis lain. e. Tidak boleh pada daerah lindung/cagar alam dan daerah banjir dengan perioda ulang 25 tahun. 2. Kriteria penyisih yaitu kriteria yang digunakan untuk memilih lokasi terbaik yaitu terdiri dari kriteria regional ditambah dengan kriteria berikut: a. Iklim. 1). Hujan: intensitas hujan makin kecil dinilai makin banyak. 2). Angin: arah angin dominan tidak menuju ke pemukiman dinilai makin baik. b. Utilitas: tersedia lebih lengkap dinilai makin baik. c. Lingkungan biologis. 1). Habitat: kurang bervariasi, dinilai makin baik. 2). Daya dukung: kurang menunjang kehidupan flora dan fauna, dinilai makin baik d. Kondisi tanah. 1). Produktifitas tanah: tidak produktifitas dinilai lebih tinggi. 2). Kapasitas dan unsur: dapat menampung lahan lebih banyak dan lebih lama dinilai lebih baik. 3). Ketersediaan tanah penutup: mempunyai tanah penutup yang cukup, dinilai lebih baik. 4). Status tanah: makin bervariasi dinilai tidak baik. e. Demografi: kepadatan penduduk lebih rendah, dinilai makin baik. f. Batas administrasi: dalam batas administrasi dinilai semakin baik. g. Kebisingan: semakin banyak zona penyangga dinilai semakin baik. h. Bau: semakin banyak zona penyangga dinilai semakin baik.
- 14. i. Estetika: semakin tidak terlihat dari luar dinilai semakin baik. j. Ekonomi: semakin kecil biaya satuan pengelolaan sampah (per m3 /ton) dinilai semakin baik. 3. Kriteria penetapan yaitu kriteria yang digunakan oleh instansi yang berwenang untuk menyetujui dan menetapkan lokasi terpilih sesuai dengan kebijaksanaan instansi yang berwenang setempat dan ketentuan yang berlaku. 2.4 Pemilihan Lokasi TPA Menurut Metoda Le Grand Metode “numerical rating” menurut Le Grand yang telah dimodifikasi oleh Knight, telah digunakan oleh Direktorat Geologi Tata Lingkungan, guna evaluasi pendahuluan dari lokasi pembuangan limbah di Indonesia. Parameter utama yang digunakan dalam analisis ini adalah: 1. Jarak antara lokasi (sumber pencemaran) dengan sumber air minum; 2. Kedalaman muka air tanah terhadap dasar lahan-urug; 3. Kemiringan hidrolis air tanah dan arah alirannya dalam hubungan dengan pusat sumber air minum atau aliran air sungai; 4. Permeabilitas tanah dan batuan; 5. Sifat-sifat tanah dan batuan dalam meredam pencemaran; 6. Jenis limbah yang akan diurug di sarana tersebut. Metode Le Grand ini terdiri dari 4 tahap, yaitu: Tahap 1: deskripsi hidrogeologis lokasi (Langkah ke 1 sampai ke 7); Tahap 2: derajat keseriusan masalah (Langkah ke 8); Tahap 3: gabungan tahap 1 dan tahap 2 (Langkah ke 9); dan Tahap 4: penilaian setelah perbaikan (Langkah ke 10). Untuk menentukan score masing-masing tahap tersebut digunakan tabulasi seperti terlihat dalam langkah-langkah di bawah ini. Contoh: Suatu calon lokasi landfilling sampah kota memiliki data sebagai berikut: • Batas lokasi landfill secara horizontal akan berjarak 20 m dari sumur penduduk; • Kedalaman muka air tanah dari data bor adalah 14 m; • Gradien kemiringan 1,5% menuju searah aliran air yang menuju sumur;
- 15. • Dari analisa ayakan, campuran lempung dan pasir = 40% dan merupakan tanah impermeable dengan ketebalan 10-12 m; • Tingkat keakuratan data baik. Kemampuan sorpsi dan permeabilitas: batuan dasar merupakan lapisan impermeabel (I) dengan lempung dan pasir <50% dengan kedalaman 10-14 m, sehingga nilai = 2. Langkah 5: Parameter 5, yaitu tingkat keakuratan/ketelitian data, yaitu: A = kepercayaan terhadap nilai parameter: akurat B = kepercayaan terhadap nilai parameter: cukup C = kepercayaan terhadap nilai parameter: tidak akurat Karena dalam contoh data yang diperoleh berasal dari data obeservasi dan pengukuran langsung di lapangan, maka tingkat kepercayaan terhadap nilai parameter dianggap akurat, sehingga nilai = A. Langkah 6: Parameter 6.1: sumber air sekitar lokasi
- 16. W = jika yang akan tercemar sumur (well) S = jika yang akan tercemar mata air (spring) atau sungai (stream) B = jika yang akan tercemar daerah lain (boundary) Sumber air sekitar lokasi yang mungkin tercemar karena adanya sarana ini adalah sumur. Dengan demikian Nilai = W. Parameter 6.2: informasi tambahan tentang calon lokasi: C : memerlukan kondisi khusus yang memerlukan komentar D : terdapat kerucut depresi pemompaan E : pengukuran jarak titik tercemar dilakukan dr pinggir calon lokasi F : lokasi berada pada daerah banjir K : batuan dasar calon lokasi adalah karst M : terdapat tampungan air di bawah timbunan sampah P : lokasi mempunyai angka perkolasi yang tinggi Q : akuifer dibawah calon lokasi adalah penting dan sensitif R : pola aliaran air tanah radial sampai sub radial T : muka air tanah pada celah/retakan/rongga batuan dasae Y : terdapat satu atau lebih akuifer tertekan Informasi tambahan tentang calon lokasi adalah berada pada lokasi banjir (F), sedang akuifer di bawah calon lokasi adalah penting dan sensitif (Q), dan terdapat satu atau lebih akuifer tertekan di bawahnya (Y). Nilai menjadi = FQY. Langkah 7: Rekapitulasi deskriptif hidrogeologi dari langkah-langkah di atas adalah menjumlah nilai yang diperoleh yaitu = 15. Nilai penjumlahan tersebut kemudian dibandingkan dengan standar kondisi hidrogeologi seperti tercantum dalam Tabel 2.2. Dengan demikian maka site tersebut dari sisi hidrogeologi merupakan site yang “baik” dengan nilai = C.
- 17. Tabel 2.2 Penilaian Kondisi Hidrogeologi Langkah 8: Derajat kepekaan akuifer dan jenis limbah Gambar 2.1 Derajat Keseriusan dan Potensi Bahaya Tahap ini menggambarkan derajat keseriusan yang disajikan dalam bentuk matrik yang menggabungkan kepekaan akuifer dengan tingkat bahaya limbah yang akan diurug/ditimbun. Jenis akuifer dipilih pada ordinat sumbu-Y, yaitu
- 18. mulai dari liat berpasir yang dianggap tidak sensitif sampai batu kapur yang dianggap sangat sensitif. Sedangkan tingkat keseriusan pencemar, yang dipilih pada absis sumbu-X, akan tergantung pada jenis limbah yang masuk, mulai dari limbah inert yang tidak berbahaya sampai limbah B-3. Titik pertemuan garis yang ditarik dari sumbu-X dan sumbu-Y tersebut menggambarkan derajat keseriusan pencemaran, mulai dari relatif rendah (A) sampai sangat tinggi (I). Derajat keseriusan tersebut dibagi dalam 9 katagori. Dari data contoh di atas, calon lokasi mempunyai tingkat derajat keseriusan agak tinggi (E). Langkah 9: Tahap ini merupakan penggabungan langkah 1 sampai 4 dengan langkah 8. Posisi grafis yang digunakan pada langkah 9 digunakan kembali. Dari posisi lokasi tersebut dapat diketahui peringkat situasi standar yang dibutuhkan agar akuifer tidak tercemar. Peringkat ini dinyatakan dalam PAR (protection of aquifer rating). Hasil pengurangan PAR dari deskripsi numerik lokasi, digunakan untuk menentukan tingkat kemungkinan pencemaran yang akan terjadi. Nilai-nilai lempung pasir PAR dalam zone-zone isometrik diperoleh berdasarkan pengalaman empiris yang menyatakan nilai permeabilitas serta sorpsi yang tidak boleh terlampaui agar akuifer tidak tercemar: • Dari langkah 1 sampai 4 diperoleh nilai berturut-turut : 7-3-3-2 • Dari langkah 9, diperoleh PAR = 14-4 maka penggabungannya adalah: Nilai tersebut (= -1) dibandingkan dengan daftar dalam Tabel 2.3 di bawah ini. Situasi peringkat menghasilkan nilai = C, artinya kemungkinan pencemaran sulit terkatagorikan, dan derajat penerimaannya adalah “terima” atau “ditolak”. Tabel 2.3 Situasi Peringkat Nilai
- 19. Langkah 10: Langkah ini digunakan bila pada lokasi dilakukan tersebut dilakukan masukan teknologi untuk mengurangi dampak pencemaran yang mungkin terjadi, sehingga diharapkan terjadi pergeseran nilai PAR. Perubahan dilakukan dengan memperbaiki kondisi pada langkah 8, sehingga PAR di langkah 9 juga akan berubah. Masukan teknologi yang mungkin diterapkan pada lokasi ini untuk mengurangi potensi bahaya pencemaran antara lain: 1. Desain saluran drainase di sekitar lokasi dengan baik dimana meminimalisasi air hujan yang akan masuk ke area landfill seminimal mungkin pula; 2. Pembuatan lapisan dasar (liner) yang dapat dilakukan dengan beberapa lapisan pelindung seperti geomembran dengan tujuan agar lindi yang timbul tidak akan merembes ke dalam ailiran air tanah; 3. Desain pipa lindi yang memungkinkan air lindi dapat terkumpul; 4. Adanya instalasi pengolahan air lindi sebelum dibuang ke badan air penerima 2.4 Pemilihan Lokasi TPA Menurut Metoda Hagerty Evaluasi dengan metode ini mengandalkan pada tiga karakteristik umum dari sebuah lahan, yaitu (Damanhuri, 2008): 1. Potensi infiltrasi air eksternal ke dalam sub-permukaan, 2. Potensi transportasi cemaran menuju air tanah, 3. Mekanisme lain yang berkaitan dengan transportasi cemaran ke luar Pertimbangan yang digunakan dalam sistem pembobotan ini adalah (Damanhuri, 2008): 1. Parameter-parameter yang langsung berpengaruh pada transmisi cemaran dianggap sebagai parameter dengan prioritas pertama, misalnya potensi infiltrasi, potensi bocornya dasar lahan-urug, dan kecepatan air tanah. Nilai maksimum adalah 20 SRP (satuan rangking prioritas). 2. Parameter-parameter yang mempengaruhi transportasi cemaran setelah terjadinya kontak dengan air dianggap sebagai prioritas kedua, seperti kapasitas penyaringan dan kapasitas sorpsi. Nilai maksimum adalah 15 SRP. 3. Parameter-parameter yang mewakili kondisi awal dari air tanah dikenal sebagai prioritas ketiga. Nilai maksimum adalah 10 SRP. 4. Parameter-parameter yang mewakili faktor-faktor lain, dikenal sebagai prioritas keempat, seperti jarak potensi cemaran, arah angin dan populasi penduduk. Nilai maksimum adalah 5 SRP.
- 20. Rangking suatu lokasi dihitung berdasarkan penjumlahan parameter yang dinilai secara individual, yaitu (Damanhuri, 2008): 1. Infiltrasi Ip + Lp + Fc + Ac + Oc + Bc + Td + Gv + Wp + Pf dimana : Ip = potensi infiltrasi Lp = potensi keretakan dasar Fc = kapasitas filtrasi Ac = kapasitas adsorpsi Oc = potensi kandungan organik dalam air Bc = kemampuan kapasitas penyangga Td = potensi jarak tempuh cemaran Gv = kecepatan air tanah Wd = arah dominan angin Pf = faktor penduduk Potensi infiltrasi (Ip) dihitung dengan (Damanhuri, 2008): dimana: i = infiltrasi ( % dari rata-rata hujan tahunan) FC = kapasitas penahan air bervariasi antara 0,05 (pasir) sampai 0,40 (liat) H = ketebalan tanah penutup (inch) 2. Potensi keretakan dasar (Lp) dihitung dengan (Damanhuri, 2008): dimana: K = koefisien permeabilitas (cm/det) T = ketebalan dasar (ft) 3. Kapasitas filtrasi (Fc) dihitung dengan (Damanhuri, 2008): dimana: φ = diameter rata-rata butiran (inch) 4. Kapasitas adsorpsi (Ac) dihitung dengan (Damanhuri, 2008):
- 21. dimana: Or = kandungan organik tanah (% berat kering) KTK = kapasitas tukar kation (mev/100 gr) 5. Kapasitas organik dalam air tanah (Oc) dihitung dengan (Damanhuri, 2008): Oc = 0,2 BOD dimana: BOD = kebutuhan oksigen secara biokimia (mg/L) 6. Kapasitas penyangga air tanah (Bc) dihitung dengan (Damanhuri, 2008): Bc = 10 - Nme dimana: Nme = nilai terkecil kebutuhan asam atau basa untuk menurunkan pH air sampai 4,5 atau sampai 8,5 (mev) 7. Potensi jarak tempuh cemaran (Td) dihitung seperti Tabel 3.4 di bawah ini (Damanhuri, 2008): Tabel 2.4: Jarak tempuh cemaran Jarak diukur dari dari lokasi lahan-urug ke muka air tanah di bawahnya, atau ke air permukaan lainnya. 8. Potensi kecepatan air tanah (Gv) dihitung dengan (Damanhuri, 2008): dimana : S = kemiringan hidrolis (ft/mil)
- 22. K = permeabilitas (cm/det) 9. Potensi arah angin (Wp) dihitung dengan (Damanhuri, 2008): dimana : Ai = sudut arah angin potensial terhadap populasi Pi = populasi di setiap kuadran (jiwa) dalam jarak 40 km 10. Faktor populasi (Pf) dihitung dengan (Damanhuri, 2008): Pf = log p dimana : p = populasi terbesar (jiwa) pada radius 40 km. Kelebihan Metoda Hagerty dibandingkan metoda lain adalah : 1. Parameter-parameter yang dievaluasi cukup luas, meliputi aspek-aspek penting diantaranya: potensi infiltrasi yang menunjukkan potensi air yang masuk ke dalam tempat pembuangan limbah, kapasitas organik dalam air tanah yang menggambarkan transmutasi cemaran yang berkontak dengan air tanah serta arah dan kecepatan angin untuk mengantisipasi potensi dampak dari TPA terhadap kualitas udara di sekitarnya. 2. Menggunakan sistem pembobotan dengan empat level prioritas yang berbeda, disesuaikan dengan tingkat kepentingan dari parameter-parameter yang ditinjau yaitu parameter-parameter yang langsung berpengaruh pada transmisi cemaran, parameter-parameter yang mempengaruhi transportasi cemaran setelah kontak dengan air, parameter-parameter yang mewakili kondisi awal dari air tanah dan parameter yang mewakili faktor-faktor lain seperti; jarak potensi cemaran, arah angin dan populasi penduduk Kelemahan metoda ini dibandingkan metoda lain adalah : 1. Memerlukan biaya lebih mahal dari pada metoda SNI T-11-1991-03, karena selain pengukuran di lapangan juga perlu dilakukan analisis laboratorium untuk pengukuran contoh tanah dan air tanah masing-masing lokasi. 2. Lokasi yang dikaji merupakan lokasi hasil dari tahap regional dengan metoda SNI T-11-1991-03, metoda ini tidak mempunyai kajian pendahuluan seperti pada tahap regional yang terdapat dalam metoda SNI T-11-1991-03. 3. Dalam analisis terhadap arah angin, arah angin yang digunakan adalah arah angin regional. Arah angin ini dirasakan tidak mewakili keadaan yang
- 23. sebenarnya di lokasi usulan karena terlalu global. Selain itu populasi yang diperhitungkan adalah pada radius 40 km. Hal ini dianggap terlalu besar, karena diperkirakan konsentrasi cemaran yang terbawa angin akan semakin kecilsehingga tidak mengganggu. Tingkat keterganggguan yang paling besar yang mungkin terjadi adalah pada populasi yang berada di sekitar lokasi TPA. 4. Pada metoda Hagerty tidak terdapat kajian tentang batas administrasi dari lokasi, kapasitas lahan dan jalan menuju lokasi.
- 24. BAB III KESIMPULAN DAN SARAN 3.1 Kesimpulan Berdasarkan makalah yang telah dibuat, maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) merupakan tempat dimana sampah mencapai tahap akhir dalam pengelolaannya, dimana diawali dari sumber, pengumpulan, pemindahan atau pengangkutan, serta pengolahan dan pembuangannya. TPA merupakan tempat dimana sampah diisolasi secara aman agar tidak menimbulkan kerusakan atau dampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya; 2. Metode-metode yang dapat digunakan dalam pemilihan lokasi TPA adalah: a.SNI 19-3241-1994; b.Metode Le Grand; c. Metode Hagerty. 3.2 Saran Saran yang dapat diberikan berdasarkan makalah yang telah dibuat adalah pemerintah dan masyarakat hendaknya berpartisipasi dan bekerja sama dalam mengatasi masalah-masalah tersebut dan memahami metode pemilihan lokasi TPA yang ada, sehingga dapat menentukan pembuatan lokasi TPA yang baik dan benar sesuai dngan prosedur yang telah diterapkan.
- 25. DAFTAR PUSTAKA Damanhuri, Enri. 2008. Diktat Landfilling Limbah Versi 2008. ITB: Bandung SNI 03-3241-1994 Tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi TPA Sampah SNI 03-3241-1994 Tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah
