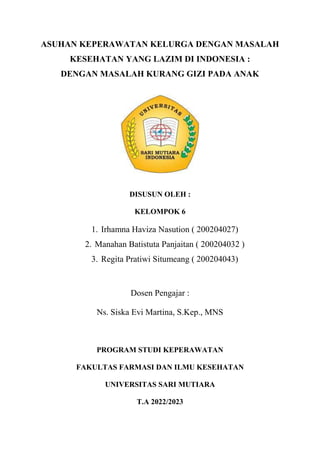
ASUHAN KEPERAWATAN KELURGA DENGAN MASALAH KESEHATAN YANG LAZIM DI INDONESIA.docx
- 1. ASUHAN KEPERAWATAN KELURGA DENGAN MASALAH KESEHATAN YANG LAZIM DI INDONESIA : DENGAN MASALAH KURANG GIZI PADA ANAK DISUSUN OLEH : KELOMPOK 6 1. Irhamna Haviza Nasution ( 200204027) 2. Manahan Batistuta Panjaitan ( 200204032 ) 3. Regita Pratiwi Situmeang ( 200204043) Dosen Pengajar : Ns. Siska Evi Martina, S.Kep., MNS PROGRAM STUDI KEPERAWATAN FAKULTAS FARMASI DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS SARI MUTIARA T.A 2022/2023
- 2. i KATA PENGANTAR Puji dan syukur penulis panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa yang telahmemberi segala rahmat sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah AsuhanKeperawatan yang berjudul : ” ASUHAN KEPERAWATAN KELURGA DENGAN MASALAH KESEHATAN YANG LAZIM DI INDONESIA : DENGAN MASALAH KURANG GIZI PADA ANAK” Dalam penulisan Asuhan Keperawatan ini penulis telah banyak mendapat bantuan, motivasi, dukungan dan bimbingan yang berharga dari berbagai pihak.Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yangsebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu : 1. Parlindungan Purba, SH, MM, sebagai Ketua Yayasan Sari Mutiara Medan. 2. Dr. Ivan Elisabeth Purba, M.Kes., sebagai Rektor Universitas Sari Mutiara Indonesia. 3. Taruli Rohana Sinaga, SP, MKM, sebagai Dekan Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan Universitas Sari Mutiara Indonesia. 4. Ns. Marthalena Simamora, M.Kep sebagai Ketua Program Studi S-I Keperawatan Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan 5. Ns. Siska Evi Martina, S.Kep., MNS sebagai dosen pengajar yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan saran kepada penulis dalam penyelesaian Asuhan Keperawatan ini. 6. Teman-teman mahasiswa/i S-I Keperawatan Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan Universitas Sari Mutiara Indonesia yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam penyusun Asuhan Keperawatan ini. Dengan rendah hati, penyusun sangat mengharapkan masukan, kritik dansaran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan Asuhan Keperawatanini. Akhir kata penyusun ucapkan terima kasih Medan. 10 Oktober 2022 Kelompok 6
- 3. ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ........................................................................................................ i DAFTAR ISI ...................................................................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................. iv 1.1 Latar Belakang........................................................................................................ iv 1.2 Tujuan Penulisan .................................................................................................... v BAB II TINJAUAN TEORI .............................................................................................. 1 2.1KONSEP KELUARGA ................................................................................................ 1 2.1.1 Defenisi ......................................................................................................... 1 2.1.2 Karakteristik Keluarga Sehat ......................................................................... 1 2.1.3 Karakteristik Keluarga Sejahtera ................................................................... 2 2.1.4 Tipe Keluarga................................................................................................. 2 2.1.5 Peran Keluarga............................................................................................... 3 2.1.6 Struktur Keluarga........................................................................................... 4 2.1.7 Fungsi Keluarga............................................................................................. 5 2.1. 8 Tahap dan Tugas Perkembangan Keluarga................................................... 6 2.2 Konsep Kurang Gizi Pada Anak .................................................................................. 9 2.2.1 Pengertian Kurang Gizi ................................................................................. 9 2.2.2 Etiologi Kurang Gizi ..................................................................................... 9 2.2.3 Kategori dan Ambang Status Gizi Anak ....................................................... 10 2.2.4 Jenis-jenis Gizi Buruk ................................................................................... 12 2.2.5 Faktor Pendukung Terjadinya Gizi Buruk .................................................... 14 2.2.6 Akibat Gizi Buruk ......................................................................................... 15 2.2.7 Kebutuhan Gizi Balita.................................................................................... 17
- 4. iii 2.2.8 Komplikasi .................................................................................................... 19 2.2.9 Penatalaksanaan Gizi Kurang ....................................................................... 20 2.3 Konsep Asuhan Keperawatan Keluarga Pada Kasus Gizi Kurang .............................. 21 2.3.1 Pengkajian ..................................................................................................... 21 3.1.2 Diagnosa Keperawatan ................................................................................. 26 3.1.3 Rencana Keperawatan .................................................................................. 39 2.3.4 Implementasi Keperawatan ........................................................................... 39 2.3.5 Evaluasi Keperawatan ................................................................................... 40 BAB III ASUHAN KEPERAWATAN KELUARGA Tn S PADA An A DENGAN GIZI KURANG .......................................................................................................................... 41 3.1 Pengkajian ................................................................................................................... 41 3.2 Diagnosa Keperawatan ............................................................................................... 53 3.3 Rencana Keperawatan.................................................................................................. 54 3.4 Implementasi Keperawatan ........................................................................................ 57 3.5 Evaluasi Keperawatan ................................................................................................ 59 BAB IV PENUTUP ........................................................................................................... 60 4.1 Kesimpulan .................................................................................................................. 60 4.2 Saran ............................................................................................................................ 60 DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................................ 61
- 5. iv BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Status gizi kurang merupakan salah satu masalah malnutrisi yang membutuhkan perhatian khusus dan perlu penanganan sejak dini. Hal ini karena kondisi kurang gizi dalam jangka lama dapat mempengaruhi pertumbuhan balita, gangguan sistem imun, dan risiko terkena penyakit infeksi meningkat serta risiko terjadinya kematian pada balita (Hong dkk.,2006). Penelitian Devi (2010), mengemukakan beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya gizi kurang adalah berat bayi lahir rendah (BBLR), penyakit penyerta balita, pengetahuan orang tua tentang gizi rendah, keadaan ekonomi keluarga, keadaan lingkungan, pola asuh orang tua, dan lama pemberian ASI Eksklusif. Jenis kelamin, status pendidikan ayah, jumlah kelahiran juga mempengaruhi status gizi balita (Asfaw dkk., 2015). Upaya penanggulangan gizi kurang memerlukan pendekatan dari berbagai segi kehidupan. Pencegahan dan penanggulangan gizi kurang tidak cukup dengan memperbaiki aspek makanan saja, tetapi juga lingkungan kehidupan balita seperti, pola asuh, tersedianya air bersih dan kesehatan lingkungan (Soekirman, 2002).Terkait dengan permasalahan gizi atau penyebaran penyakitberbasis lingkungan sangat diperlukan kesadaran masyarakat maupun rumah tangga dalam berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). PHBSadalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran setiap anggota keluarga sehingga anggota keluarga atau keluarga dapatmenolong dirinya sendiri dibidang kesehatan
- 6. v dan dapat berperan aktifdalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat (Depkes RI, 2007). Berdasarkan data yang diperoleh Departemen Kesehatan (2009) bahwa di Indonesia masih banyak daerah-daerah yang memiliki sanitasi buruk karena mayoritas masyarakatnya belum menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat sehingga angka kesakitan pada masyarakat masih tinggi (Tim Teknis Pembangunan Sanitasi, 2009). Indikator- indikator PHBS yang perlu dilaksanakan dalam suatu rumah tangga meliputi, mencari pertolongan persalinan ke tenaga kesehatan, melakukan penimbangan bayi dan balita, memberikan air susu ibu (ASI) Eksklusif, penggunaan air bersih, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, memberantas jentik nyamuk, memakai jamban sehat, makan buah dan sayur setiap hari, melakukan aktivitas fisik setiap hari, dan tidak merokok di dalam rumah. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dimulai dari tingkatan rumah tangga, karena karakteristik rumah tangga akan memudahkan penanganan terhadap balita yang memiliki masalah gizi. Apabila seorang balita terdeteksi penderita gizi kurang dan balita tersebut memiliki orangtua, maka akan lebih mudah mendapatkan informasi terperinci (Depkes RI, 2006). 1.2 Tujuan Penulisan 1.2.1 Tujuan Umum Mengetahui dan memahami lebih dalam mengenai Asuhan Keperawatan Keluarga Dengan Masalah yang Lazim Di Indonesia: Dengan Masalah Kurang Gizi Pada Anak
- 7. vi 1.2.2 Tujuan Khusus Tujuan khusus yang ingin dicapai penulis setelah pelaksaan asuhan keperawatan adalah: 1. Mampu memahami Konsep Keluarga 2. Mampu memahami Konsep Kurang Gizi pada Anak 3. Mampu memahami Asuhan Keperawatan Keluarga Dengan Masalah yang Lazim Di Indonesia: Dengan Masalah Kurang Gizi Pada Anak 4. Mampu Melaksanakan Asuhan Keperawatan Keluarga Dengan Masalah yang Lazim Di Indonesia: Dengan Masalah Kurang Gizi Pada Anak
- 8. 1 BAB II TINJAUAN TEORI 2.1 KONSEP KELUARGA 2.1.1 Defenisi Keluarga adalah dua atau lebih dari dau individu yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan dan mereka hidup dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan didalam perannya masing-masing menciptakan serta mempertahankan kebudayaan (Friedman, 2010). Keluarga adalah suatu system sosial yang berisi dua atau lebih orang yang hidup bersama yang mempunyai hubungan darah, perkawinan atau adopsi, tingga bersama dan saling menguntungkan, empunyai tujuan bersama, mempunyai generasi peneus, saling pengertian dan saling menyayangi (Achjar, 2010). Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga didefinsikan dengan istilah kekerabatan dimana invidu bersatu dalam suatu ikatan perkawinan dengan menjadi orang tua. Dalam arti luas anggota keluarga merupakan mereka yang memiliki hubungan personal dan timbal balik dalam menjalankan kewajiban dan memberi dukungan yang disebabkan oleh kelahiran,adopsi,maupun perkawinan (Stuart,2014) 2.1.2 Karakteristik Keluarga Sehat Karakteristik keluarga sehat : 1. Menunjukkan tingkat kemampuan keterampilan negosiasi yang tinggi dan menghadapi masalahnya terus menerus. 2. Mengungkapkan berbagai perasaan, kepercayaan, dan perbedaan mereka dengan jelas, terbuka, dan spontan. 3. Menghargai perasaan anggotanya. 4. Mengharapkan anggota untuk memikul tanggung jawab pribadi terhadap tindakan yang mereka lakukan. 5. Menunjukan perilaku afiliatif (kedekatan dan kehangatan) satu sama lain.
- 9. 2 (Setiawati, 2010) 2.1.3 Karakteristik Keluarga Sejahtera Berdasarkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, psikososial, ekonomi, dan aktualisasi keluarga dalam masyarakat keluarga dikelompokkan menjadi 5 tahap yaitu sebagai berikut : 1. Keluarga pra sejahtera Adalah yaitu kebutuhan pengajaran agama, pangan sandang, papan dan kesehatan atau keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator keluarga sejahteraan tahap 1. 2. Keluarga sejahtera tahap I Keluarga yang telah memenuhi kebutuhan dasar secara minimal serta memenuhi kebutuhan sosial psikologinya, yaitu kebutuhan pendidikan, keluarga berencana (KB), interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan transportasi. 3. Keluarga sejahtera tahap II Keluarga telah dapat memenuhi kebutuhan secara minimal serta telah memenuhi seluruh kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi. 4. Keluarga sejahtera tahap III Keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikososial dan pengembangan, tetapi belum dapat memberikan sumbangan baik internal atau keluarga, serta berfikir dengan menjadi pengurus lembaga masyarakat, yayasan sosial, kegamaan, kesenian,olahraga, pendidikan dan sebagainya. 5. Keluarga sejahtera tahap III (plus) Keluarga yang telah dapat memenuhi kebuthan baik yang bersifat dasar, sosial psikologis, pengembangan, serta telah mampu memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat. 2.1.4 Tipe Keluarga Tipe keluarga dibedakan menjadi dua jenis yaitu : a) Tipe keluarga tradisional 1. Nuclear family atau keluarga inti merupakan keluarga yang terdiri atas suami,istri dan anak.
- 10. 3 2. Dyad family merupakan keluarga yang terdiri dari suami istri namun tidak memiliki anak 3. Single parent yaitu keluarga yang memiliki satu orang tua dengan anak yang terjadi akibat peceraian atau kematian. 4. Single adult adalah kondisi dimana dalam rumah tangga hanya terdiri dari satu orang dewasa yang tidak menikah 5. Extended family merupakan keluarga yang terdiri dari keluarga inti ditambah dengan anggota keluarga lainnya 6. Middle-aged or erdely couple dimana orang tua tinggal sendiri dirumah dikarenakan anak-anaknya telah memiliki rumah tangga sendiri. 7. Kit-network family, beberapa keluarga yang tinggal bersamaan dan menggunakan pelayanan Bersama. b) Tipe keluarga non tradisional 1. Unmaried parent and child family yaitu keluarga yang terdiri dari orang tua dan anak tanpa adanya ikatan pernikahan. 2. Cohabitating couple merupakan orang dewasa yang tinggal bersama tanpa adanya ikatan perkawinan. 3. Gay and lesbian family merupakan seorang yang memiliki persamaan jenis kelamin tinggal satu rumah layaknya suami-istri 4. Nonmarital Hetesexual Cohabiting family,keluarga yang hidup Bersama tanpa adanyanya pernikahan dan sering berganti pasangan 5. Faster family, keluarga menerima anak yang tidak memiliki hubungan darah dalam waktu sementara (Widagdo,2016). 2.1.5 Peran Keluarga Peranan keluarga menggambarkan pola perilaku interpersonal, sifat, dan kegiatan yang berhubungan dengan individu dalam situasi dan posisi tertentu. Adapun macam peranan dalam keluarga antara lain (Istiati, 2010): a. Peran Ayah Sebagai seorang suami dari istri dan ayah dari anak-anaknya, ayah berperan sebagai kepala keluarga, pendidik, pelindung, mencari nafkah, serta pemberi rasa aman bagi
- 11. 4 anak dan istrinya dan juga sebagai anggota dari kelompok sosialnya serta sebagai anggota masyarakat di lingkungan di mana dia tinggal. b. Peran Ibu Sebagai seorang istri dari suami dan ibu dari anak-anaknya, dimana peran ibu sangat penting dalam keluarga antara lain sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya, sebagai pelindung dari anak-anak saat ayahnya sedang tidak ada dirumah, mengurus rumah tangga, serta dapat juga berperan sebagai pencari nafkah. Selain itu ibu juga berperan sebagai salah satu anggota kelompok dari peranan sosial serta sebagai anggota masyarakat di lingkungan di mana dia tinggal. c. Peran Anak Peran anak yaitu melaksanakan peranan psikososial sesuai dengan tingkat perkembangan baik fisik, mental, sosial maupun spiritual. 2.1.6 Struktur Keluarga Struktur keluarga oleh Friedman dalam (Harmoko, 2012) sebagai berikut: 4. Struktur komunikasi Komunikasi dalam keluarga dikatakan berfungsi apabila dilakukan secara jujur,terbuka, melibatkan emosi, konflik selesai, dan ada hierarki kekuatan. Komunikasi keluarga bagi pengirim yakin mengemukakan pesan secara jelas dan berkualitas, sertameminta dan menerima umpan balik. Penerima pesan mendengarkan pesn, memberikanumpan balik, dan valid. 5. Struktur peran Serangkaian perilaku yang diharapkan sesuai posisi sosial yang diberikan. Jadi, padastruktur peran bisa bersifat formal atau informal. Posisi/ status adalah posisi individudalam masyarakat misal status sebagai istri/ suami. 6. Struktur kekuatan Kemampuan dari individu untuk mengontrol, memengaruhi, atau mengubah perilakuorang lain. Hak (legitimate power), ditiru (referent power), keahlian (exper power),hadiah (reward power), paksa (coercive power), dan effektif power. 7. Strukur nilai dan normaa a) Nilai, suatu sistem, sikap, kepercayaan yang secara sadar atau tidak dapat mempersatukan annggota keluarga.
- 12. 5 b) Norma, pola perilaku yang baik menurut masyarakat berdasarkan sistem nilaidalam keluarga. c) Budaya, kumpulan daripada perilaku yang dapat dipelajari, dibagi dan ditularkandengan tujuan untuk menyelesaikan masalah. Adapun Struktur Keluarga Lainnya: a. Patrilineal : keluarga sedarah yang terdiri dari sanak saudara sedarahdalam beberapa generasi, dimana hubungan itu disusun melalui jalurayah b. Matrilineal : keluarga sedarah yang terdiri dari sanak saudara sedarahdalam beberapa generasi dimana hubungan itu disusun melalui jalurgaris ibu c. Matrilokal : sepasang suami istri yang tinggal bersama keluargasedarah ibu d. Patrilokal : sepasang suami istri yang tinggal bersama keluarga sedarahsuam e. Keluarga kawinan : hubungan suami istri sebagai dasar bagi pembinaan keluarga, dan beberapa sanak saudara yang menjadi bagiankeluarga karena adanya hubungan dengan suami atau istri. 2.1.7 Fungsi Keluarga Fungsi keluarga adalah ukuran dari bagaimana sebuah keluarga beroperasi sebagai unit dan bagaimana anggota keluarga berinteraksi satu sama lain. Hal ini mencerminkan gaya pengasuhan, konflik keluarga, dan kualitas hubungan keluarga. Fungsi keluarga mempengaruhi kapasitas kesehatan dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga (Families, 2010). Fungsi keluarga menurut (Marilyn M. Friedman, 2010): 1) Fungsi Afektif Memfasilitasi stabilisasi kepribadian orang dewasa, memenuhi kebutuhan psikologis anggota keluarga 2) Fungsi Sosialisasi Memfasilitasi sosialisasi primer anak yang bertujuan menjadikan anak sebagai anggota masyarakat yang produktif serta memberikan status pada anggota keluarga 3) Fungsi reproduksi Untuk mempertahankan kontinuitas keluarga selama beberapa generasi dan untuk keberlangsungan hidup masyarakat
- 13. 6 4) Fungsi ekonomi Menyediakan sumber ekonomi yang cukup dan alokasi efektifnya 5) Fungsi perawatan kesehatan Menyediakan kebutuhan fisik-makanan, pakaian, tempat tinggal, perawatan kesehatan 2.1.8 Tahap dan Tugas Perkembangan Keluarga Tahapan Tugas Perkembangan Keluarga Tahap perkembangan keluarga menurut Friedman (2010) adalah : 1) Tahap 1 : Keluarga pemula Perkawinan dari sepasang insan menandai bermulanya sebuah keluarga baru, keluarga yang menikah atau prokreasi dan perpindahan dari keluarga asal atau status lajang ke hubungan baru yang intim. Adapun tugas perkembangan keluarga yaitu : Membangun perkawinan yang saling memuaskan. Menghubungkan jaringan persaudaraan secara harmonis. Keluarga berencana (keputusan tentang kedudukan sebagai orangtua). 2) Tahap II : Keluarga yang sedang mengasuh anak Tahap kedua dimulai dengan kelahiran anak pertama hingga bayi berumur 30 bulan. Biasanya orang tua bergetar hatinya dengan kelahiran anak pertama mereka, tapi agak takut juga. Kekhawatiran terhadap bayi biasanya berkurang setelah beberapa hari, karena ibu dan bayi tersebut mulai mengenal. Ibu dan ayah tiba-tiba berselisih dengan semua peran-peran mengasyikkan yang telah dipercaya kepada mereka. Peran tersebut pada mulanya sulit karena perasaan ketidakadekuatan menjadi orang tua baru. Adapun tugas perkembangan keluarga yaitu : Membentuk keluarga muda sebagai sebuah unit yang mantap (mengintegrasikan bayi baru kedalam keluarga). Rekonsilisiasi tugas-tugas perkembangan yang bertentangan dan kebutuhan anggota keluarga. Mempertahankan hubungan perkawinan yang memuaskan. Memperluas persahabatan dengan keluarga besar dengan menambahkan peran-peran orangtua dan kakek-nenek.
- 14. 7 3) Tahap III : Keluarga yang anak usia prasekolah Tahap ketiga siklus kehidupan keluarga dimulai ketika anak pertama berusia 2,5 tahun dan berakhir ketika anak berusia 5 tahun. Sekarang, keluarga mungkin terdiri tiga hingga lima orang, dengan posisi suami - ayah, istri – ibu, anak laki-laki – saudara, anak perempuan – saudari. Keluarga menjadi lebih majemuk dan berbeda. Adapun tugas perkembangan keluarga yaitu :] Memenuhi kebutuhan anggota keluarga seperti rumah, ruang bermain, privasi, keamanan. Mensosialisasikan anak. Mengintegrasikan anak yang baru sementara tetap memenuhi kebutuhan anak-anak yang lain. Mempertahankan hubungan yang sehat dalam keluarga (hubungan perkawinan dan hubungan orangtua dan anak) dan diluar keluarga (keluarga besar dan komunitas). 4) Tahap IV : Keluarga dengan anak usia sekolah Tahap ini dimulai ketika anak pertama telah berusia 6 tahun dan mulai masuk sekolah dasar dan berakhir pada usia 13 tahun, awal dari masa remaja. Keluarga biasanya mencapai jumlah anggota maksimum, dan hubungan keluarga di akhir tahap ini. Adapun tugas perkembangan keluarga yaitu : Membantu sosialisasi anak dengan tetangga, sekolah dan lingkungan Mempertahankan hubungan perkawinan bahagia Memenuhi kebutuhan dan biaya hidup yang semakin meningkat Meningkatkan komunikasi terbuka 5) Tahap V : Keluarga dengan anak remaja Ketika anak pertama melewati umur 13 tahun, tahap kelima dari siklus kehidupan keluarga dimulai. Tahap ini berlangsung selama 6 hingga 7 tahun, meskipun tahap ini dapat lebih singkat jika anak meninggalkan keluarga lebih awal atau lebih lama jika anak masih tinggal dirumah hingga berumur 19 atau 20 tahun. Adapun tugas perkembangan keluarga yaitu :
- 15. 8 Menyeimbangkan kebebasan dengan tanggung jawab ketika remaja menjadi dewasa dan semakin mandiri Memfokuskan kembali hubungan perkawinan Berkomunikasi secara terbuka antara orangtua dan anak-anak 6) Tahap VI : Keluarga yang melepaskan anak usia dewasa muda Permulaan dari fase kehidupan keluarga ini ditandai oleh anak pertama meninggalkan rumah orang tua dan berakhir dengan rumah kosong, ketika anak terakhir meninggalkan rumah. Tahap ini dapat singkat atau agak panjang, tergantung pada berapa banyak anak yang ada dalam rumah atau berapa banyak anak yang belum menikah yang masih tinggal di rumah. Adapun tugas perkembangan keluarga yaitu : Memperluas keluarga inti menjadi keluarga besar Mempertahankan keintiman pasangan Membantu orang tua suami/isteri yang sedang sakit dan memasuki masa tua Membantu anak untuk mandiri di masyarakat Penataan kembali peran dan kegiatan rumah tangga 7) Tahap VII : Orang tua pertengahan Tahap ketujuh dari siklus kehidupan keluarga, tahap usia pertengahan dari bagi orangtua, dimulai ketika anak terakhir meninggalkan rumah dan berakhir pada saat pensiun atau kematian salah satu pasangan. Tahap ini biasanya dimulai ketika orangtua memasuki usia 45-55 tahun dan berakhir pada saat seorang pasangan pensiun, biasanya 16-8 tahun kemudian. Adapun tugas perkembangan keluarga yaitu : Mempertahankan kesehatan Mempertahankan hubungan yang memuaskan dengan teman sebaya dan anak-anak Meningkatkan keakraban pasangan 8) Tahap VIII : Keluarga dalam masa pensiun dan lansia Tahap terakhir siklus kehidupan keluarga dimulai dengan salah satu atau kedua pasangan memasuki masa pensiun, terus berlangsung hingga salah satu pasangan meninggal, dan
- 16. 9 berakhir dengan pasangan lain meninggal. Adapun tugas perkembangan keluarga yaitu : Mempertahankan suasana rumah yang menyenangkan Adaptasi dengan perubahan, kehilangan pasangan, teman, dll Mempertahankan keakraban suami-isteri dan saling merawat Mempertahankan hubungan dengan anak dan sosial masyarakat 2.2 Konsep Kurang Gizi Pada Anak 2.2.1 Pengertian Kurang Gizi Gizi (nutrition) adalah proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi (penyerapan), transportasi, penyimpanan, metabolisme dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan, untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal organ-organ, serta menghasilkan energi (Pudiastuti, 2011). Gizi kurang atau kurang gizi (sering kali tersebut malnutrisi) muncul akibat asupan energi dan makronutrien yang tidak memadai. Pada beberapa orang kurang gizi juga terkait dengan defisiensi mikronutrien nyata ataupun subklinis (Webster-Gandy, 2014) 2.2.2 Etiologi Kurang Gizi Penyebab gizi kurang pada anak menurut Pudiastuti (2011), antara lain adalah : a. Pola makan yang salah Asupan gizi dari makanan sangat berpengaruh besar pada pertumbuhan balita. Jumlah makanan yang dikonsumsi oleh balita harus diperhatikan, pola makan yang salah dapat menyebabkan balita mengalami gizi kurang. b. Anak sering sakit dan perhatian yang kurang Perhatian dan kasih sayang orang tua pada anak sangat dibutuhkan pada masa perkembangan anak. Rendahnya perhatian dan kasih sayang orang tua pada anak menyebabkan makan anak tidak terkontrol. c. Infeksi penyakit
- 17. 10 Adanya penyakit infeksi dapat memperburuk keadaan/ kondisi balita terutama pada balita yang asupan gizinya tidak terkontrol dengan baik. d. Kurangnya asupan gizi Rendahnya asupan gizi pada anak menyebabkan anak mengalami gizi kurang sehingga pertumbuhan tubuh dan otak anak terganggu. e. Berbagai hal buruk yang terkait dengan kemiskinan Status ekonomi yang terlalu rendah menyebabkan keluarga tidak mampu memberikan asupan makanan yang cukup pada anak sehingga penyakit mudah berkembang di tubuh anak. 2.2.3 Kategori dan Ambang Status Gizi Anak Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Standar Antropometri Anak, mengkategorikan Status gizi pada anak, yaitu Indeks Kategori Status Gizi Ambang Batas (Z-Score) Berat Badan menurut Umur (BB/U) anak usia 0 - 60 bulan Berat badan sangat kurang (severely underweight) <-3 SD Berat badan kurang (underweight) - 3 SD sd <- 2 SD Berat badan normal -2 SD sd +1 SD Risiko Berat badan lebih1 > +1 SD Panjang Badan atau Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U) anak usia 0 - 60 bulan Sangat pendek (severely stunted) <-3 SD Pendek (stunted) - 3 SD sd <- 2 SD Normal -2 SD sd +3 SD Tinggi2 > +3 SD Berat Badan menurut Panjang Gizi buruk (severely wasted) <-3 SD
- 18. 11 Badan atau Tinggi Badan (BB/PB atau BB/TB) anak usia 0 - 60 bulan Gizi kurang (wasted) - 3 SD sd <- 2 SD Gizi baik (normal) -2 SD sd +1 SD Berisiko gizi lebih (possible risk of overweight) > + 1 SD sd + 2 SD Gizi lebih (overweight) > + 2 SD sd + 3 SD Obesitas (obese) > + 3 SD Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U) anak usia 0 - 60 bulan Gizi buruk (severely wasted)3 <-3 SD Gizi kurang (wasted)3 - 3 SD sd <- 2 SD Gizi baik (normal) -2 SD sd +1 SD Berisiko gizi lebih (possible risk of overweight) > + 1 SD sd + 2 SD Gizi lebih (overweight) > + 2 SD sd +3 SD Obesitas (obese) > + 3 SD Indeks Massa Tubuh menurut Gizi buruk (severely thinness) <-3 SD Indeks Kategori Status Gizi Ambang Batas (Z-Score) Umur (IMT/U) anak usia 5 - 18 tahun Gizi kurang (thinness) - 3 SD sd <- 2 SD Gizi baik (normal) -2 SD sd +1 SD Gizi lebih (overweight) + 1 SD sd +2 SD Obesitas (obese) > + 2 SD Keterangan: 1. Anak yang termasuk pada kategori ini mungkin memiliki masalah pertumbuhan, perlu dikonfirmasi dengan BB/TB atau IMT/U
- 19. 12 2. Anak pada kategori ini termasuk sangat tinggi dan biasanya tidak menjadi masalah kecuali kemungkinan adanya gangguan endokrin seperti tumor yang memproduksi hormon pertumbuhan. Rujuk ke dokter spesialis anak jika diduga mengalami gangguan endokrin (misalnya anak yang sangat tinggi menurut umurnya sedangkan tinggi orang tua normal). 3. Walaupun interpretasi IMT/U mencantumkan gizi buruk dan gizi kurang, kriteria diagnosis gizi buruk dan gizi kurang menurut pedoman Tatalaksana Anak Gizi Buruk menggunakan Indeks Berat Badan menurut Panjang Badan atau Tinggi Badan (BB/PB atau BB/TB). 2.2.4 Jenis-jenis Gizi Buruk Menurut Khaidirmuhaj (2009) Jenis-jenis gizi buruk antara lain: 1. Marasmus Marasmus adalah suatu bentuk malgizi protein, energi karena kelaparan, semua unsur diet kurang (Sodikin, 2011). Tanda dan Gejala : Anak tampak sangat kurus, tinggal tulang terbungkus kulit Wajah seperti orang tua Cengeng, rewel Kulit keriput, jaringan lemak subkutis sangat sedikit, bahkan sampai tidak ada
- 20. 13 Sering disertai diare kronik atau konstipasi:susah buang air, serta penyakit kronik Tekanan darah, detak jantung, dan pernapasan berkurang 2. Kwashiorkor Kwashiorkor adalah suatu keadaan kekurangan gizi yang merupakan sindrom klinis yang diakibatkan defisiensi protein berat dan kalori yang tidak adekuat. Walaupun sebab utama penyakit ini adalah defisiensi protein, tetapi karena bahan makanan yang dimakan kurang mengandung nutrisi lainnya ditambah dengan konsumsi setempat yang berlainan, maka akan terdapat perbedaan gambaran kwashiorkor di berbagai negara (Khaidirmuhaj, 2009). Tanda dan Gejala : Edema( terutama kaki/dorsum pedis) Wajah membulat dan sembab Pandangan sayu Rambut tipis,kemerahan seperti warna rambut jagung,mudah dicabut/rontok Perubahan status mental : rewel,cengeng,kadang apatis Pembesaran hati Otot mengecil (hipotrofi) Kelainan kulit Sering disertai : infeksi,anemia,diare
- 21. 14 3. Kurang kalori dan protein (marasmus–kwashiorkor) Marasmus Kwashiorkor adalah suatu sindrom protein calorie malnutrition di mana ditemukan gejala-gejala marasmus dan juga terdapat gejala-gejala kwashiorkor. Jadi, marasmik kwashiorkor merupakan sindrom perpaduan dari marasmus dan kwashiorkor. Marasmus-Kwashiorkor terjadi karena makanan sehari-harinya tidak cukup mengandung protein dan juga energi untuk pertumbuhan normal. Pada tipe ini terjadi penurunan berat badan dibawah 60 % dari normal (Khaidirmuhaj, 2009). Tanda dan Gejala : Gambaran klinik merupakan campuran dari beberapa gejala klinikkwashiokor dan marasmus,dengan BB/U<60% Baku median WHO-NCHS disertai edema yang mencolok. 2.2.5 Faktor Pendukung Terjadinya Gizi Buruk Menurut Webster-Gandy (2012), dalam kebanyakan kasus, ada berbagai faktor penyebab kurang gizi. Kesadaran akan beberapa faktor pendukung tertentu merupakan langkah pertama dalam pencegahan yang sangat berharga. Berikut penjelasan singkatnya. 1. Asupan gizi menurun a. Ketersediaan makanan yang tidak memadai (kuantitatif ataupun kualitatif) : Pasien diasuh di ruang isolasi sehingga baki makanan mungkin saja ditinggalkan di luar kamar atau di tempat yang tidak terjangkau pasien. Kelaparan berulang yang disengaja , mis., harus berpuasa peroral karena menjalani berbagai macam pemeriksaan atau terapi Koordinasi motorik lambat sehingga perlu bantuan saat makan Hidangan yang tidak sesuai dengan budaya pasien, mis menyediakan makanan yang tidak halal bagi orang islam atau bukan kosher bagi orang Yahudi. Makanan tidak menggugah selera atau berkualitas buruk 2. Anoreksia (kehilangan nafsu makan) : Dampak penyakit, mis. akibat kanker, infeksi, inflamasi. Mual dan muntah. Masalah psikologi, mis. akibat depresi, kecemasan, kesepian.
- 22. 15 Dampak pengobatan, mis. akibat kemoterapi. 3) Gangguan makan : a) Gangguan gigi-geligi b) Perubahan pengecap dan pembau c) Mulut kering atau nyeri d) Sesak napas e) Gangguan menelan 4) Absorpsi nutrien menurun a) Sekresi saluran cerna tidak mencukupi, termasuk empedu dan semua enzim saluran cerna, mis. akibat kekurangan enzim pankreas. b) Kerusakan permukaan absorptif di saluran cerna, mis. akibat penyakit Crohn. c) Reseksi + fistula saluran cerna. d) Komplikasi terapi obat. 5) Kebutuhan meningkat a) Hipermetabolisme terkait penyakit, misalnya akibat sirosis hati, beberapa kanker. b) Infeksi c) Akibat terapi, misalnya setelah pembedahan. d) Peningkatan kehilangan, misalnya melalui saluran cerna, urine, kulit, napas, atau drainase bedah. e) Peningkatan aktivitas, baik sadar maupun tidak sadar, mis. akibat penyakit Parkinson. 2.2.6 Akibat Gizi Buruk Menurut Webster-Gandy (2012), dampak kurang gizi bervariasi mulai dari subklinis, yakni tidak ada gangguan klinis sama sekali, sampai kematian, dan bergantung pada jenis, lama, dan derajat keparahan ketidakcukupan gizi, usia, serta status gizi dan kesehatan pasien. Menurut Webster-Gandy (2012), selain tingginya risiko mortalitas, kurang gizi juga terkait dengan morbilitas yang lebih besar : a. Berat badan turun (utamanya lemak dan otot) b. Fungsi otot terganggu :
- 23. 16 1) Otot rangka – mobilitas buruk, tingginya risiko jatuh 2) Pernapasan – tingginya resiko infeksi paru-paru, penurunan kapasitas olahraga penyapihan ventilasi tertunda 3) Jantung – bradikardia, hipotensi, penurunan curah jantung 4) Saluran cerna – penurunan integritas dinding usus berpotensi menambah akses masuk mikroorganisme c. Fungsi imun melemah : 1) Penurunan fagositosis, penurunan kemotaksis, penurunan penghancuran bakteri intrasel, penurunan limfosit T 2) Peningkatan angka infeksi 3) Respons yang buruk terhadap vaksinasi d. Sintesis protein baru terganggu : 1) Penyembuhan luka kurang baik, tingginya risiko ukserasi 2) Perlambatan masa pulih dari pembedahan 3) Perlambatan atau penghentian pertumbuhan anak 4) Penurunan fertilitas pada wanita dan pria e. Gangguan psikologis : 1) Depresi, anoreksia, penurunan motivasi 2) Penurunan kualitas hidup 3) Gangguan intelektual jika kurang gizi terjadi pada masa bayi f. Beban ekonomi bertambah : 1) Peningkatan komplikasi 2) Peningkatan lama rawat inap di rumah sakit dan unit perawatan intensif (ICU) 3) Tingginya angka rawat inap kembali setelah sebelumnya dipulangkan dari rumah sakit 4) Rehabilitasi lebih lama 5) Tingginya ongkos obat 6) Meningkatnya kunjungan ke dokter umum
- 24. 17 2.2.7 Kebutuhan Gizi Balita Menurut Proverawati dan Wati (2011), menjelaskan kebutuhan gizi seseorang adalah jumlah yang diperkirakan cukup untuk memelihara kesehatan pada umumnya. Secara garis besar, kebutuhan gizi ditentukan oleh usia, jenis kelamin, aktivitas, berat badan, dan tinggi badan. Antara asupan zat gizi dan pengeluarannya harus ada keseimbangan sehingga diperoleh status gizi yang baik. Status gizi balita dapat dipantau dengan menimbang anak setiap bulan dan dicocokkan dengan Kartu Menuju Sehat (KMS). a) Kebutuhan energi Kebutuhan energi bayi dan balita relatif besar dibandingkan dengan orang dewasa, sebab pada usia tersebut pertumbuhannya masih sangat pesat. Kecukupannya akan semakin menurun seiring dengan bertambahnya usia. Menurut Almatsier (2013), kebutuhan energi pada anak umur 0 – 6 bulan 350 kkal, umur 7 – 11 bulan 650 kkal, 1 – 3 tahun 1000 kkal dan 4 – 6 tahun 1550 kkal. b) Kebutuhan zat pembangun (protein) Secara fisiologis, balita sedang dalam masa pertumbuhan sehingga kebutuhannya relatif lebih besar dari pada orang dewasa. Namun, jika dibandingkan dengan bayi yang usianya kurang dari satu tahun, kebutuhannya relatif lebih kecil. Menurut Almatsier (2013), kebutuhan protein pada anak umur 0 – 6 bulan 10 gr, umur 7 – 11 bulan 16 gr, 1 – 3 tahun 25 gr dan 4 – 6 tahun 39 gr. c) Kebutuhan zat pengatur Kebutuhan air bayi dan balita dalam sehari berfluktuasi seiring dengan bertambahnya usia. Menurut Almatsier (2013), kebutuhan zat pengatur anak yaitu :
- 25. 18 Untuk pertumbuhan dan perkembangan, balita memerlukan enam zat gizi utama, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Zat gizi tersebut dapat diperoleh dari makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Agar balita dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, makan makanan yang dimakannya tidak boleh hanya sekedar mengenyangkan perut saja. Makanan yang dikonsumsi balita seharusnya : 1) Beragam jenisnya 2) Jumlah atau porsi cukup (tidak kurang atau berlebihan) 3) Higienis dan aman (bersih dari kotoran dan bibit penyakit serta tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan) 4) Makan dilakukan secara teratur 5) Makan dilakukan dengan cara yang baik Menurut Proverawati dan Wati (2011), keenam zat gizi utama digunakan oleh tubuh anak untuk : 1) Menghasilkan tenaga yang digunakan oleh anak untuk melakukan berbagai kegiatan seperti belajar, berolah raga, bermain, dan aktivitas lain (disebut zat tenaga). Zat makanan yang merupakan sumber tenaga utama adalah karbohidrat dan lemak. Makanan yang banyak mengandung karbohidrat adalah beras, jagung, singkong, ubi jalar, kentang, talas, gandum dan sagu. Makanan yang banyak
- 26. 19 mengandug lemak adalah lemak hewani (gajih), mentega, minyak goreng, kelapa dan keju. 2) Membangun jaringan tubuh dan mengganti jaringan tubuh yang aus/rusak. (disebut zat pembangun). Zat makanan yang merupakan zat pembangun adalah protein. Makanan yang banyak mengandung protein adalah tahu, tempe oncom, kacang-kacangan, telur, daging, ikan, udang dan kerang. 3) Mengatur kegiatan-kegiatan yang terjadi di dalam tubuh (disebut zat pengatur). Zat makanan yang merupakan zat pengatur adalah vitamin, mineral dan air. Makanan yang banyak mengandung vitamin, mineral dan air adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Kebutuhan tubuh balita akan keenam macam gizi untuk melakukan tiga fungsi tersebut tidak bisa dipenuhi hanya dari satu macam makanan saja karena tidak ada satu pun makanan dari alam yang mempunyai kandungan gizi lengkap. Jika makanan anak beragam, maka zat gizi yang tidak terkandung atau kurang dalam satu jenis makanan akan dilengkapi oleh zat gizi yang berasal dari makanan jenis lain. Agar makanan yang dimakan anak beraneka ragam, maka kita harus selalu ingat bahwa makanan yang dimakan anak harus mengandung zat tenaga, zat pembangun dan zat pengatur. Ketiga zat ini dapat berasal dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan air. 2.2.8 Komplikasi Menurut Suariadi dan Rita (2010), komplikasi gizi kurang diantaranya : a. Kwashiorkor (kekurangan karbohidrat) : diare, infeksi, anemia, gangguan tumbuh kembang, hipokalemia, dan hipernatremia. b. Marasmus (kekurangan protein) : infeksi, tuberculosis, parasitosis, disentri, malnutrisi kronik, gangguan tumbuh kembang. c. Marasmus-kwashiorkor (kekurangan karbohidrat dan protein) : terjadi edema, kelainan rambut dan kelainan kulit
- 27. 20 2.2.9 Penatalaksanaan Gizi Kurang Gizi kurang terjadi akibat kurangnya asupan gizi pada anak, yang bila tidak ditangani secara cepat, tepat dan komprehensif dapat mengakibatkan terjadinya gizi buruk. Perawatan gizi kurang dapat dilakukan dengan cara : a. Terapi Kurang Gizi Menurut Webster-Gandy (2012), ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa bantuan gizi mampu menambah asupan protein dan energi, memperbaiki berat badan dan mengurangi penurunan berat badan diantaranya adalah : 1) Penilaian Disaat kurang gizi didiagnosis, penilaian gizi secara menyeluruh harus dilakukan guna mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan menjadi dasar terapi. 2) Akses makanan Setelah penilaian, jelas terlihat bahwa diperlukan beberapa tindakan nonteknis yang relatif mudah untuk membantu mereka yang kurang gizi mendapat makanan yang sesuai. 3) Pemberian suplemen menggunakan makanan Modifikasi dan/atau penyediaan makanan dan minuman menggunakan bahan makanan yang sudah umum dapat meningkatkan asupan energi dan zat gizi yang besar bagi banyak pasien. Langkah ini relatif jelas dan lugas serta harus dicoba terlebih dulu sebelum intervensi yang rumit dimulai. Status pasien harus rutin dipantau. Kelebihan langkah ini antara lain : fleksibel, makanan memiliki cita rasa, perilaku makan diperbaiki tanpa ada intervensi obat-obatan, dan terjangkau. Kelemahannya antara lain : memerlukan motivasi dan upaya yang tinggi dan + keterampilan kuliner dari sang pasien, pengasuh dan profesional kesehatan, terbatasnya persediaan bahanbahan makanan yang sesuai di institusi dan berpotensi memerlukan suplemen mikronutrien tambahan. 4) Pemberian suplemen menggunakan suplemen gizi khusus per oral Suplemen gizi per oral siap-guna sering disebut sip feeds dapat digunakan bersama fortifikasi makanan untuk menutupi kekurangan jika seseorang tidak dapat mengasup cukup makanan. Kelebihannya antara lain : komposisinya sudah diketahui, sebagian besar menyajikan energi, makro- dan mikronutrien yang seimbang, tersedia dalam bentuk siap-guna. Kelemahannya antara lain : penggunaan produk-produk siap pakai
- 28. 21 yang cepat dan praktis tanpa menilai kebutuhan pasien seutuhnya, rasa bosan terhadap cita rasa produk setelah dipergunakan sekian lama. 2.3 Konsep Asuhan Keperawatan Keluarga Pada Kasus Gizi Kurang 2.3.1 Pengkajian Format pengkajian keluarga model Friedman yang diaplikasikan ke kasus dengan masalah utama Gizi Kurang menurut Friedman (2010), meliputi : a. Data umum Menurut Friedman (2010), data umum yang perlu dikaji adalah : 1) Nama kepala keluarga dan anggota keluarga, alamat, jenis kelamin, umur, pekerjaan dan pendidikan. Pada pengkajian pendidikan diketahui bahwa pendidikan berpengaruh pada kemampuan dalam mengatur pola makan dan pentingnya asupan gizi bagi balita. Sedangkan pekerjaan yang terlalu sibuk bagi orang tua mengakibatkan perhatian orang tua terhadap tumbuh kembang anak tidak ada. 2) Tipe keluarga Menjelaskan mengenai jenis/tipe keluarga beserta kendala atau masalah- masalah yang terjadi dengan jenis/tipe keluarga yang mengalami gizi kurang (Padila, 2012). Biasanya keluarga yang mempunyai balita dengan gizi kurang mempunyai jumlah anggota keluarga yang banyak sehingga kebutuhan nutrisi anak tidak terpenuhi. 3) Suku bangsa Identifikasi budaya suku bangsa tersebut terkait dengan kesehatan (Sutanto, 2012). Biasanya keluarga dengan gizi kurang mempunyai budaya tidak terlalu memperhatikan menu makan balita, yang terpenting balita sudah mendapatkan makanan. 4) Status sosial ekonomi keluarga
- 29. 22 Status sosial ekonomi keluarga ditentukan oleh pendapatan baik dari kepala keluarga maupun dari anggota keluarga lainnya. Pada pengkajian status sosial ekonomi diketahui bahwa tingkat status sosial ekonomi berpengaruh pada tingkat kesehatan seseorang. Dampak dari ketidakmampuan keluarga membuat seseorang tidak bisa mencukupi kebutuhan nutrisi keluarga (Padila, 2012). Biasanya keluarga dengan gizi kurang mempunyai perekonomian yang rendah karena keluarga tidak mampu mencukupi semua kebutuhan balita. b. Riwayat dan tahap perkembangan keluarga 1) Tahap perkembangan keluarga saat ini Tahap perkembangan keluarga ditentukan dengan anak tertua dari keluarga inti (Gusti, 2013). Biasanya keluarga dengan gizi kurang berada pada tahap perkembangan keluarga dengan anak pra sekolah. 2) Tahap perkembangan keluarga yang belum terpenuhi Menjelaskan mengenai tugas perkembangan keluarga yang belum terpenuhi oleh keluarga serta kendala-kendala yang dialami (Padila 2012). Biasanya keluarga belum mampu memenuhi semua kebutuhan anak karena keterbatasan penghasilan yang diperoleh. 3) Riwayat keluarga inti Menjelaskan riwayat kesehatan masing-masing anggota keluarga inti, upaya pencegahan dan pengobatan pada anggota keluarga yang sakit, serta pemanfaatan fasilitas kesehatan yang ada (Gusti, 2013). Biasanya keluarga dengan gizi kurang tidak memantau tumbuh kembang anak ke tenaga kesehatan. c. Pengkajian Lingkungan 1) Karakteristik rumah Karakteristik rumah diidentifikasi dengan melihat tipe rumah, jumlah ruangan, jenis ruang, jumlah jendela, jarak septic tank dengan sumber air, sumber air minum yang digunakan, tanda cat yang sudah mengelupas, serta dilengkapi dengan denah rumah (Friedman, 2010). Biasanya keluarga dengan gizi kurang
- 30. 23 mempunyai keuangan yang tidak mencukupi kebutuhan anak sehingga luas rumah tidak sesuai dengan jumlah anggota keluarga. d. Fungsi Keluarga 1) Fungsi afektif Hal yang perlu dikaji seberapa jauh keluarga saling asuh dan saling mendukung, hubungan baik dengan orang lain, menunjukkan rasa empati, perhatian terhadap perasaan (Friedman, 2010). Bisanya keluarga dengan gizi kurang jarang memperhatikan kebutuhan akan kasih sayang dan perhatian pada anak, serta tidak mau bersosialisasi dengan lingkungan luar karena merasa malu akan kondisi anak. 2) Fungsi sosialisasi Dikaji bagaimana interaksi atau hubungan dalam keluarga, sejauh mana anggota keluarga belajar disiplin, penghargaan, hukuman, serta memberi dan menerima cinta (Friedman, 2010). Biasanya keluarga dengan gizi kurang tidak disiplin terhadap pola makan balita. 3) Fungsi perawatan kesehatan a) Keyakinan, nilai, dan prilaku kesehatan : menjelaskan nilaiyang dianut keluarga, pencegahan, promosi kesehatan yang dilakukan dan tujuan kesehatan keluarga (Friedman, 2010). Biasanya keluarga tidak mengetahui pencegahan yang harus dilakukan agar balita tidak mengalami gizi kurang. b) Status kesehatan keluarga dan keretanan terhadap sakit yangdirasa : keluarga mengkaji status kesehatan, masalah kesehatan yang membuat kelurga rentan terkena sakit dan jumlah kontrol kesehatan (Friedman, 2010). Bisanya keluarga tidak mampu mengkaji status kesehatan keluarga. c) Praktik diet keluarga : keluarga menegtahui sumber makananyang dikonsumsi, cara menyiapkan makanan, banyak makanan yang dikonsumsi perhari dan kebiasaan mengkonsumsi makanan kudapan (Friedman, 2010). Biasanya keluarga tidak terlalu memperhatikan menu makanan, sumber makanan dan banyak makanan yang tersedia
- 31. 24 d) Peran keluarga dalam praktik keperawatan diri : tindakan yangdilakukan dalam memperbaiki status kesehatan, pencegahan penyakit, perawatn keluarga dirumah dan keyakinan keluarga dalam perawatan dirumah (Friedman, 2010). Biasanya kelurga dengan gizi kurang tidak tau cara pencegahan penyakit dan mengenal pennyakit. e) Tindakan pencegahan secara medis : status imunisasi anak,kebersihan gigi setelah makan, dan pola keluarga dalam mengkonsumsi makanan (Friedman, 2010). Biasanya keluarga tidak membawa anaknya imunisasi ke posyandu. 4) Fungsi sosialisasi Pada kasus penderita gizi kurang, dapat mengalami gangguan fungsi sosial baik didalam keluarga maupun didalam komunitas sekitar keluarga (Padila, 2012). Biasanya keluarga sangat kesulitan untuk bersosialisasi anggota keluarga maupun lingkungan sekitar rumah. 5) Fungsi reproduksi Hal yang perlu dikaji mengenai fungsi reproduksi keluarga adalah : berapa jumlah anak, apa rencana keluarga berkaitan dengan jumlah anggota keluarga, metode yang digunakan keluarga dalam upaya mengendalikan jumlah anggota keluarga (Padila, 2012). Jumlah anak sangat berpengaruh dengan kecukupan gizi yang dikonsumsi anak balita. Biasanya keluarga mempunyai anak lebih dari 2 orang. 6) Fungsi ekonomi Menjelaskan bagaimana upaya keluarga dalam pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan serta pemanfaatan lingkungan rumah untuk meningkatkan penghasilan keluarga (Gusti, 2013). Biasanya keluarga belum bisa memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papa balita.
- 32. 25 e. Pemeriksaan Fisik Pemeriksaan fisik dilakukan pada semua anggota keluarga. Metode yang di gunakan pada pemeriksaan fisik head to toe untuk pemeriksaan fisik untuk gizi kurang adalah sebagai berikut 1) Status kesehatan umum Meliputi keadaan penderita, kesadaran, suara bicara, tinggi badan, berat badan dan tanda - tanda vital. Bisanya balita mempunyai BB rendah. 2) Kepala dan leher Kaji bentuk kepala, keadaan rambut, adakah pembesaran pada leher, telinga kadang-kadang berdenging, adakah gangguan pendengaran, gigi mudah goyah, gusi mudah bengkak dan berdarah. Biasanya balita yang mengalami gizi kurang mempunyai warna rambut yang kecoklatan, pucat dan anemia. 3) Sistem Integumen Biasnya balita mempunyai turgor kulit menurun, kulit tampak kering dan kasar, kelembaban dan suhu kulit meningkat, tekstur rambut dan kuku juga kasar. 4) Sistem Pernafasan Pernafasan balita masih dalam rentang normal karena balita belum jatuh pada gizi buruk. 5) Sistem Kardiovaskuler Perfusi jaringan balita menurun, nadi perifer lemah atau berkurang, takikardi/bradikardi, dan disritmia, pemeriksaan CRT. 6) Sistem Gastrointestinal Bising usus pada balita yang mengalami gizi kurang terdengar jelas, frekuensi > 20 kali/menit, mual, muntah, diare, konstipasi, perubahan berat badan, peningkatan lingkar abdomen.
- 33. 26 7) Sistem Urinary Sistem perkemihan pada klien gizi kurang tidak mengalami gangguan. 8) Sistem Muskuluskletal Penyebaran lemak, penyebaran masa otot, perubahan tinggi badan, cepat lelah, lemah dan nyeri. 9) Sistem Neurologis Pada balita gizi kurang terjadi penurunan sensoris, penurunan kesadaran, reflek lambat, kacau mental dan disorientasi. 3.1.2 Diagnosa Keperawatan Diagnosis keperawatan keluarga dirumuskan berdasarkan data yang didapatkan pada pengkajian, yang terdiri dari masalah keperawatan yang akan berhubungan dengan etiologi yang berasal dari pengkajian fungsi perawatan keluarga. Diagnosa keperawatan mengacu pada rumusan PES (problem, etiologi dan simpton) dimana untuk problem menggunakan rumusan masalah dari NANDA, sedangkan untuk etiologi dapat menggunakan pendekatan lima tugas keluarga atau dengan menggambarkan pohon masalah (Padila, 2012). Tipologi dari diagnosa keperawatan keluarga terdiri dari diagnosa keperawatan keluarga actual (terjadi defisit/gangguan kesehatan), risiko (ancaman kesehatan) dan keadaan sejahtera (wellness) (Padila, 2012). Diagnosa keperawatan keluarga dapat dibagi menjadi 3, yaitu : a. Diagnosa keperawatan keluarga : aktual b. Diagnosa keperawatan keluarga : resiko c. Diagnosa keperawatan keluarga : sejahtera (potensial) Diagnosa keperawatan yang sering muncul pada keluarga dengan gizi kurang menurut problem (NANDA, 2015-2017) dan etiologi (Friedman, 2010) adalah : a) Ketidakseimbangan nurtrisi : kurang dari kebutuhan tubuhberhubungan dengan ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga dengan kekurangan nutrisi. b) Resiko keterlambatan perkembangan berhubungan denganketidakmampuan keluarga dalam melakukan stimulasi pada balita.
- 34. 27 c) Resiko Kerusakan integritas kulit berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga yang sakit. d) Defisit pengetahuan berhubungan dengan ketidakmampuankeluarga dalam mengatasi masalah gizi kurang Tabel 2.4 Skala prioritas masalah keluarga Sumber : Baylon & Maglaya (1978) dalam Padila (2012) Skoring: a. Tentukan skor untuk setiap kriteria b. Skor dibagi dengan angka tertingi dan dikalikan dengan bobot. Skor X Bobot Angka Tertingi c. Jumlahkanlah skor untuk semua kriteria (Susanto, 2012). Kriteria Skor Bobot 1) Sifat masalah : (1) Aktual (tidak/kurang sehat ) (2) Ancaman kesehatan (3) Keadaan sejahtera 3 2 1 1 2) Kemungkinan masalah dapat diubah : a. Mudah b. Sebagian c. Tidak dapat 2 1 0 2 3) Potensi masalah untuk dicegah : a. Tinggi b. Cukup c. Rendah 3 2 1 1
- 35. 39 3.1.3 Rencana Keperawatan Menurut Gusti (2013), rencana keperawatan keluarga adalah sekumpulan tindakan yang ditentukan perawat untuk dilaksanakan dalam memecahkan masalah kesehatan dan keperawatan yang diidentifikasi dari masalah keperawatan yang sering muncul. Dx Keperawatan Tujuan Kriteria Evaluasi Rencana Keperawatan Umum Khusus Kriteria Standar Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan keperawatan keluarga diantaranya : 1. Rencana keperawatan harus didasarkan atas analisis yang menyeluruh tentang masalah atau situasi keluarga 2. Rencana yang baik harus realitas, artinya dapat dilaksanakan dan dapat menghasilkan apa yang diharapkan 3. Rencana keperawatan harus sesuai dengan tujuan dan faslafah instansi kesehatan 4. Rencana keperawatan dibuat Bersama dengan keluarga, hal ini sesuai dengan prinsip bahwa pekerja bekerja Bersama keluarga bukan untuk keluarga 5. Rencana asuhan keperawatan sebaiknya dibuat secara tertulis, hal ini selain berguna untuk perawat juga akan berguna bagi anggota tim kesehatan lainnya, khususnya perencanaan 2.3.4 Implementasi Keperawatan Implementasi keperawatan keluarga adalah suatu proses aktualisasi rencana intervensi memnfaatkan berbagai sumber di dalam keluarga dan memandirikan keluarga dalam bidang kesehatan. Keluarga di didik untuk dapat menilai potensi yang dimiliki mereka dan mengembangkannya melalui implementasi yang bersifat memampukan keluarga untuk mengenal masalah kesehatannya, mengambil keputusan berkaitan dengan persoalan kesehatan yang dihadapi, merawat dan membina anggota keluarga sesuai kondisi kesehatannya, meodifikasi lingkungan yang sehat bagi setiap anggota keluarga, serta memanfaatkan saran pelayanan kesehatan terdekat.
- 36. 40 2.3.5 Evaluasi Keperawatan Evaluasi keperawatan keluarga adalah proses untuk menilai keberhasilan keluarga dalam melaksanakan tugas kesehatan sehingga memiliki produktivitas yang tinggi dalam mengembangkan setiap anggota keluarga. Sebagai komponen kelima dalam proses keperawatan, evaluasi adalah tahap yang menentukan apakah tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan sudah tercapai. Bentuk rumusan tujuan yang ditetapkan dalam perencanaan sudah tercapai. Bentuk rumusan tujuan yang ditetapkan akan menentukan mudah atau sulitnya dalam melaksanakan evaluasi. Evaluasi sebagai suatu proses dapat dipusatkan dalam empat dimensi berikut. a. Dimensi keberhasilan dari tindakan keperawatan, evaluasi ini dikaitkan dengan pencapaian tujuan b. Dimensi ketepatgunaan (efficiency) tindakan keperawatan, evaluasi ini dikaitkan dengan biaya, waktu, tenaga, dan bahan c. Dimensi kecocokan (appropriateness) tindakan keperawatan adalah kesanggupan dari tindakan untuk mengatasi masalah dengan baik dan sesuai pertimbangan professional d. Dimensi keadekuatan (adequacy) tindakan keperawatan yang berhubungan dengan kelengkapan tindakan. Apakah semua tindakan telah dilaksanakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- 37. 41 BAB III ASUHAN KEPERAWATAN KELUARGA Tn S PADA An A DENGAN GIZI KURANG 3.1 Pengkajian b. Data Keluarga 1. Identitas Kepala Keluarga Nama : Tn S Umur : 32 Tahun Agama : Islam Suku : Jawa Pekerjaan : Penjahit Pendidikan : SD Alamat : Jln Bakti Luhur Gg Millenium 2. Komposisi Keluarga No Nama Jenis Kelamin Umur Hubungan dengan keluarga Pendidikan Pekerjaan Agama Suku Status Kesehatan 1 Ny S P 34th Istri SMA IRT Islam Jawa Sehat 2 An. A P 1 th Anak - - Islam Jawa Sakit
- 38. 42 3. Genogram Keluarga Ket : Laki-laki : Menikah : Perempuan : Keturunan : Meninggal : Tinggal Serumah : Pasien
- 39. 43 Tn S Ny S Keluarga Tn S rajin sholat ke masjid Anatara anggota keluarga terbina hubungan baik dan harmonis Keluarga Tn S menggunakan fasilitas Kesehatan yang tersedia untuk berobat Keluarga Tn S tidak sering menghabiskan waktu dengan keluarganya karena pekerjaannya Usaha yang dimiliki oleh keluarga Tn W berjalan dengan baik 4. Ecomap Keluarga Tn W tidak sering mengikuti kegiatan kemasyarakatan seperti rukun tetangga, kerja bakti, maupun pengajian sekitar rumahnya akibat pekerjaannya An. A
- 40. 44 5. Tipe Keluarga Tipe Keluarga Tn W adalah Keluarga Inti tediri dari Tn S. Ny S dan An A 6. Status sosial ekonomi keluarga Penghasilan Tn S rata-rata perbulan Rp 500.000 -nRp 600.000, Tn S bekerja sebagai penjahit. Secara umum penghasilan keluarga Tn S kurang cukup memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dikarenakan hanya Tn S bekerja sedangkan Ny S hanya sebagai Ibu Rumah Tangga 7. Riwayat dan Tahap Perkembangan Keluarga a. Tahap perkembangan keluarga saat ini Keluarga pada tahap perkembangan mengasuh anak dengan umur 1 tahun b. Tahap Perkembangan Keluarga yang belum terpenuhi Tahap perkembangan keluarga yang belum terpenuhi adalah komunikasi antara keluarga belum efektif karena kesibukan Tn S bekerja dari pagi hingga malam hari sehingga tidak ada percakapan lebih mendalam, oleh karena itu ketika anaknya sakit tidak dibawa ke pelayanan kesehatan seperti puskesmas/RS c. Riwayat penyakit keluarga inti 1. Kesehatan Keluarga An A lahir dengan berat 2500gr, saat ini An A berada di garis kuning dilihat melalui KMS Balita, An A berhenti minum ASI sejak usia 2,5 bulan karena ASI Ny S sukar keluar dengan keadaan putting susu lecet, An A kemudian meminum susu formula, sampai saat ini masih diberikan susu formula,tidak ada makanan pendamping ASI tubuh An A terlihat kurus untuk anak usia 1 tahun 2. Kebiasaan minum obat Tidak ada kebiasaan minum obat pada keluarga Tn S karena tidak ada anggota keluarga yang sakit 3. Kebiasaan memeriksakan diri Keluarga Tn S jarang berobat ke pelayanan kesehatan terdekat karena setiap sakit hanya mengandalkan obat yang dibeli di warung 4. Kesehatan Ibu dan Anak
- 41. 45 Tn S memiliki 1 anak, persalinan anaknya dilakukan di rumah dibantu oleh bidan dengan lahir secara normal Ny S sedang tidak hamil Ny S tidak menggunakan kontrasepsi , Tn S masih menginginkan anak 8. Pola Kebiasaan Anggota Keluarga Sehari-hari a. Nutrisi Keluarga Tn S makan sehari 3 kali dengan nasi kadang dengan sayur dan lauk.cara Ny S mengolah makanan itu dimasak di dapur dengan sayuran biasanya dipotong baru dicuci begitu juga dengan ikan, dan air minum dari sumur dan selalu dimasak lebih dahulu, Keluarga Tn S rata-rata minum air putih 6 gelas sehari. An A berusia 1 th, sejak usia 2,5 bulan tidak minum ASI yang cukup karena putting susu ibu lecet dan produksi ASI tidak banyak dan An A tidak makan makanan pendamping ASI b. Pola Istirahat Keluarga Tn S mulai tidur pukul 22.00, Tn S bangun jam 04.00 untuk mempersiapkan pekerjaannya sendangkan Ny S bangun jam 04.30 untuk menyiapkan makanan c. Pola eliminasi Tn S BAB lancer 2 kali sehari, begitu pula dengan Ny S, An A BAB 3 kali sehari dengan konsistensi lunak warna kuning cerah, untuk BAK Tn S dan Ny S rata-rata BAK 3-5 kali sehari, tidak ada masalah BAK/BAB, An A BAK 6 kali sehari, warna urin kuning cerah tidak ada darah d. Pola Kebersihan Keluarga Tn S mandi 2 kali sehari dengan sabun dan juga cuci rambut dengan shampoo, selalu menyikat gigi 2 kali sehari, keramas 2 kali sehari, memotong kuku 1 minggu sekali, pakaian tampak bersih, An A dimandikan oleh NyS pagi dan sore menggunakan sabun bayi e. Pola Aktivitas Tn S sehari-hari beraktivitas bekerja di pasr sebagai penjahit dimulai berangkat pukul 07.00 dan pulang pukul 20.00, sedangkan Ny S di rumah membersihkan rumah serta menyiapkan keubutuhan keluarga, seperti memasak, mencuci dan mengasuh bayi f. Pola Reproduksi
- 42. 46 Kebutuhan pasangan seksual terpenuhi, saat pengkajian Ny S mengatakan bahwa dirinya belum ber KB karena sejak melahirkan anaknya yang pertama belum menstruasi sehingga menurutnya tidak perlu KB 9. Lingkungan a. Karakteristik Rumah Keluarga menempati rumah sendiri, jenis semi-permanen, dinding/tembok terbuat dari papan dan batu bata, lantai diplester semen mempunyai 3 kamar tidur, 1 ruang tamu, dapur, kamar mandi dan WC dengan jenis jamban leher angsa dengan kondisi baik, sedangkan ruang makan tidak ada, ventilasi cukup, ncahayaan baik dan penerangan dengan listrik, sumber air dari sumur gali pembuangan air limbah disalurkan melalui saluran buatan sendiri, dialirkan ke saluran pembuangan parit, halaman rumah tampak bersih, lingkungan rumah cukup bersih, fasilitas yang dekat seperti Klinik Kesehatan yang berjarak 500 meter dari rumah, pasar yang berjarak 950 meter dari rumah, dan fasilitas beribadah seperti masjid hanya berjarak 4 meter dari rumah, Ket 1 : Ruang tamu 2 : Kamar tidur 3 : WC 4 : Dapur II : pintu 2 2 1 4 2 3
- 43. 47 b. Mobilitas geografi keluarga Keluarga Tn S sudah tinggal di daerah tempat tinggalnya sejak tahun 2002 dan setelah itu menetap tidak berpindah-pindah tempat tinggal c. Sistem pendukung Keluarga Keluarga Tn S terlalu sibuk dengan urusan masing-masing dengan Tn W yang sibuk bekerja sebagai penjahit demi mencukupi kebutuhan keluarganya dan Ny S yang mengurus rumah serta anak mereka, sehingga komunikasi tidak terjalin dengan efektif 10. Struktur Keluarga a. Pola komunikasi Keluarga Tn S memiliki pola dan proses komunikasi yang kurang baik antar-anggota keluarga, dimana keluarga Tn. W memiliki kesibukan masing-masing tanpa ada pembicaraan yang mendalam antar anggota keluarga b. Struktur Kekuasaan Keputusan dalam keluarga Tn. S ada pada kepala keluarga, yaitu pada Tn. S sendiri namun tidak dilakukan musyawarah bersama dengan seluruh anggota keluarga. c. Struktur Peran Setiap anggota keluarga menjalankan peran masing-masing dengan baik. Ayah sebagai pencari nafkah utama dan ibu mengurus rumah dan anak d. Nilai-nilai dan norma budaya Keluarga Tn S menerapkan aturan sesuai dengan ajaran islam dengan rajin sholat dan puasa pada bulan puas dan mengharapkan anaknya nantinya menjadi anak yang taat dalam menjalankan agama 11. Fungsi Keluarga a. Fungsi afektif Keluarga Tn. S kurang menunjukkan kasih sayang satu sama lain, ditandai dengan komunikasi tidak berjalan dengan lancer serta terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan kurang
- 44. 48 menghabiskan waktu denga istri dan anaknya sehingga fungsi afektif di keluarga Tn, S tidak tercukupi. b. fungsi sosialisasi keluarga Tn.S kurang bersosialisasi dengan tetangga nya karna selalu pergi pagi dan pulang malam c. fungsi perawatan Kesehatan Perawatan kesehatan dalam keluarga Tn. S tidak baik, karena belum terlalu mengerti akan kesehatan. Anaknya serta solusi untuk menangani anaknya tersebut dengan anaknya An A yang kurang gizi d. fungsi reproduksi Tn. A dan Ny. S sampai saat ini hanya mempunyai seorang anak yaitu An. A dan mengatakan jika mereka sebenarnya ingin memiliki anak lagi, namun tidak terwujud sampai sekarang e. fungsi ekonomi Penghasilan yang didapat Tn. S dalam bekerja belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga selama sebulan 12. Strategi Koping a. Stressor keluarga Jangka Pendek Menurut Tn. S, sejak kemarin ini sering memikirkan keadaan anaknya yang kekurangan gizi Tetapi Tn. S dan Ny. S mengatakan tidak bisa melakukan apa-apa karna kondisi ekonomi b. Strategi koping yang digunakan Tn. S tidak menggunakan cara musyawarah dalam menyelesaikan masalah dalam keluarganya maupun dalam mengambil sebuah keputusan, sehingga beban masalah tidak dapat diatasi oleh keluarga seperti penyakit An A
- 45. 49 13. Pemeriksaan Fisik Head To Toe Pemeriksaan fisik Tn. S Ny. S An. A Kepala TTV BB, TB Mata Hidung Mulut Leher Dada Abdomen Tangan Kaki Simetris, tidak ada luka, rambut bersih, hitam N : 90 x/menit TD : 130/90 mmHg RR : 20 x/menit S : 36 ⁰C BB : 78 kg TB : 170 cm Konjungtiva merah muda, sklera anikterik Tidak bersekret Bersih, tidak bau, gigi dan gusi utuh, mukosa lembab, tidak kesulitan menelan Tidak ada benjolan, tidak ada pembesaran kelenjar limfe Bunyi jantung S1&S2 normal dan paru vesikuler Simetris, peristaltik usus 25x/menit Dalam batas normal Dalam batas normal Simetris, tidak ada luka, rambut: hitam, bersih N : 86 x/menit TD : 120/90 mmHg RR : 20 x/menit S : 36,8 ⁰C BB : 56 kg TB : 150 cm Konjungtiva merah muda, sklera anikterik Tidak bersekret Bersih, tidak bau, gigi dan gusi utuh, mukosa lembab, tidak kesulitan menelan Tidak ada benjolan, tidak ada pembesaran kelenjar limfe Bunyi jantung S1&S2 normal dan paru vesikuler Simetris, peristaltik usus 25x/menit Dalam batas normal Dalam batas normal Simetris, tidak ada luka, rambut : hitam bersih N : 96 x/menit RR : 20 x/menit S : 36,8 ⁰C BB : 7,6 kg TB : 74,5 cm LLA : 7,5 cm Konjungtiva merah muda, sklera anikterik Tidak bersekret Bersih, agak bau, mukosa agak kering, bibir sedikit pucat, tidak kesulitan menelan Tidak ada benjolan, tidak tidak ada pembesaran kelenjar limfe Bunyi jantung S1&S2 normal dan paru vesikuler Simetris, peristaltik usus 20 /menit Dalam batas normal Dalam batas normal
- 46. 50 14. Tugas Keluarga Mengenal masalah kesehatan Keluarga Tn S menyatakan tidak tau bahwa anaknya mengalami gizi kurang, Ny S ditanya mengatakan tidak mengetahui tentang interpretasi garis kuning pada KMS mengambil keputusan masalah kesehatan terhadap keluarganya yang sakit Tn S menyatakan bahwa anaknya perlu dilakukan perawatan agar status gizi nya baik merawat keluarganya yang sakit Ny S mengatakan ketika usia An A 2,5 bulan, ASI nya tidak lancer, kemudian memberikan susu formula sampai sekarang, tanpa ada makanan tambahan, ketika ditanya tidak mengetahui jenis makanan yang tepat untuk anak usia 1 tahun memodifikasi lingkungan dalam dan luar rumah yang berdampak terhadap kesehatan keluarga Lingkungan rumah Tn S tampak bersih, lingkungan tidak ada barang tajam atau membahayakan anak memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan An A selalu dibawa ke posyandu untuk dilakukan pengukuran dan ke puskesmas dilakukan imunisasi 15. Data Tambahan Status Gizi Keluarga Tn S Nama anggota keluarga Hubungan Keluarga Umur Pengukuran status gizi Kategori status gizi BB TB Tn S KK 32 tahun 78 Kg 170 cm Normal Ny S Istri 34 tahun 56 Kg 150 cm Normal An A Anak 1 tahun 7,6 Kg 74,5 cm Kurus 16. Harapan Keluarga Keluarga Tn. S berharap dengan dilakukannya asuhan keperawatan keluarga dapat mensejahterakan keluarganya, terutama dalam hal kesehatan, yang semula tidak paham mengenai kesehatan, memanfaatkan fasilitas Kesehatan yang ada sehingga dapat menjadi
- 47. 51 paham dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari demi tercapainya derajat kesehatan keluarga yang optimal. Analisa Data No Tgl/Waktu Data Fokus Problem Etiologi 1 12-10-2022 15.00 WIB Data Subyektif: a. Ny S mengatakan berat badan anaknya susah naik b. Ny S menyatakan memberi ASI mulai lahir sampai umur 2,5 bulan, ASI berhenti karena keluar sedikit dan puting lecet, kemudian mengganti dengan ASI susu formula sampai sekarang c. Ny S mengatakan tidak memberikan makanan pendamping ASI Data Obyektif: a. Suhu tubuh An. A: 36,8⁰C b. LLA : 7,5 cm c. Status gizi An A pada KMS Balita berada di garis kuning d. Anak tampak kurus Manajemen Kesehatan keluarga tidak efektif ( D. 0115) Ketidakmampuan keluarga merawat An A dengan gizi kurang ( BGM) karena kurangnya pengetahuan keluarga tentang gizi sehat 2 12-10-2022 15.05 WIB Data Subyektif : a. Ny S menyatakan berat badan anaknya sulit naik b. Ny S mengatakan tidak mengetahui makna dari garis kuning pada KMS balita Data Obyektif : a. Ibu tidak tau tentang masalah gizi kurang dan interpretasi garis kuning pada KMS Manajemen Kesehatan keluarga tidak efektif ( D. 0115) Ketidakmampuan keluarga Tn S mengenal masalah kesehatan terhadap makna garis kuning pada KMS balita
- 48. 52 Menentukan Prioritas Masalah 1. Manajemen Kesehatan keluarga tidak efektif ( D. 0115) b/d Ketidakmampuan keluarga merawat An A dengan gizi kurang ( BGM) karena kurangnya pengetahuan keluarga tentang gizi sehat Aktual No Kriteria Hitungan Skor Pembenaran 1 Sifat masalah : Aktual 3/3x1 1 An A sudah berada pada garis kuning dan 2 bulan tidak naik, BB anak tetap 7,6 Kg 2 Kemungkinan masalah dapat diubah : Sebagaian 2/2x2 2 Ny S bertugas mengrus anak sepenuhnya, dengan focus pada mengurus anak diharapkan dapat mengubah kondisi An A 3 Potensi untuk dicegah : Cukup 2/3x1 2/3 Masalah ini dirasakan cukup lama dan sedang dilakukan usaha- usaha untuk meningkatkan status gizi anak 4 Menonjolnya masalah : Masalah berat, harus segera ditangani 1/2x1 1/2 Tn S menyatakan bahwa anaknya harus diarawat agar gizinya Kembali baik Total Skor 4 1/6 2. Ketidakmampuan keluarga Tn S mengenal masalah kesehatan pada Anak An A terhadap makna garis kuning pada KMS balita b/d Manajemen Kesehatan keluarga tidak efektif ( D. 0115) Risiko No Kriteria Hitungan Skor Pembenaran 1 Sifat masalah : Resiko 2/3 x 1 2/3 An A dengan status gizi kurang akan mudah tertular penyakit infeksi 2 Kemungkinan masalah dapat diubah : Sebagian 1/2x2 1 Pendidikan Keluarga ( Ny S) yang cukup, sumber daya keluarga dan masayarakat yang memadai dan adanya fasilitas Kesehatan yang terjangkau 3 Potensial untuk dicegah : Cukup 2/3x1 2/3 Masalah ini dirasakan cukup lama dan sedang dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan status gizi anak 4 Menonjolnya masalah : Tidak dirasakan 0/2x1 0 Keluarga Tn S tidak menyadari bahwa gizi kurang dapat membahayakan Kesehatan dan tumbuh kembang anak Total Skor 2 1/3
- 49. 53 3. 2 Diagnosa Keperawatan 1. Manajemen Kesehatan keluarga tidak efektif ( D. 0115) b/d Ketidakmampuan keluarga merawat An A dengan gizi kurang ( BGM) karena kurangnya pengetahuan keluarga tentang gizi sehat 2. Ketidakmampuan keluarga Tn S mengenal masalah kesehatan pada Anak An A terhadap makna garis kuning pada KMS balita b/d Manajemen Kesehatan keluarga tidak efektif ( D. 0115)
- 50. 54 3.3 Rencana Keperawatan No Diagnosa Keperawatan Keluarga Tujuan Umum ( TUM) Tujuan Khusus ( TUK) Evaluasi Intervensi Keperawatan Kriteria Standar 1 Manajemen Kesehatan keluarga tidak efektif ( D. 0115) b/d Ketidakmampuan keluarga merawat An A dengan gizi kurang ( BGM) karena kurangnya pengetahuan keluarga tentang gizi sehat Setelah diberikan Asuhan keperawatan selama 2 x pertemuan pada An. A di keluarga Tn. S mampu meningkatkan status gizi sehat Setelah dilakukan tindakan kesehatan Selama 1x24 jam keluarga mampu: a. Merawat anggota keluarga yang mengalami kurang gizi Respon Verbal Keluarga dapat menjawab tentang pengertian status gizi sehat Status gizi baik atau status gizi optimal terjadi bila tubuh memperoleh cukup zat-zat gizi yang digunakan secara efisien, sehingga memungkinkan pertumbuhan fisik, perkembangan otak, kemampuan kerja, dan kesehatan secara umum pada tingkat setinggi mungkin. Kaji pengetahuan keluarga tentang status gizi sehat Kaji saat timbul gejala gizi kurang Berikan pengetahuan kepada keluarga tentang memenuhi kebutuhan gizi anak Koordinasi dengan petugas gizi puskesmas tentang pemberian
- 51. 55 makanan tambahan ( PMT- ASI) Anjurkan keluarga untuk terus memantau kenaikan BB setiap bulan 2 Ketidakmampuan keluarga Tn S mengenal masalah kesehatan pada Anak An A terhadap makna garis kuning pada KMS balita b/d Manajemen Kesehatan keluarga tidak efektif ( D. 0115) Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali pertemuan keluarga mampu Memahami tentang makna garis kuning pada KMS balita Setelah dilakukan tindakan kesehatan Selama 1x24 jam keluarga mampu: a) Mengenal masalah tentang status gizi sehat Verbal Keluarga dapat menjawab tentang penjelasan KMS balita Kartu Menuju Sehat (KMS) merupakan kartu yang memuat kurva pertumbuhan normal balita berdasarkan indeks antropometri berat badan menurut umur (BB/U) dan berdasarkan jenis Kaji pengetahuan keluarga tentang KMS balita Berikan pengetahuan kepada keluarga tentang memenuhi kebutuhan gizi anak
- 52. 56 kelamin. Kartu Menuju Sehat memiliki tiga fungsi utama yaitu sebagai alat pemantauan pertumbuhan balita; sebagai catatan pelayanan kesehatan balita terutama penimbangan berat badan, pemberian ASI eksklusif, kejadian sakit, dll; serta sebagai alat edukasi.
- 53. 57 3.4 Implementasi Keperawatan Tanggal/Waktu No. Dx. Implementasi Respon Paraf 12-10-2022 16.25 WIB 1 Memberikan pengetahuan keluarga tentang status gizi sehat S: Keluarga mengatakan sudah mengetahui tentang status gizi sehat O: Keluarga tampak paham terhadap apa penjelasan tentang status gizi sehat 16.30 WIB 1 Berikan pengetahuan kepada keluarga tentang memenuhi kebutuhan gizi anak S: Keluarga mengatakan paham terhadap apa yang dijelaskan O: Keluarga tampak mengerti dengan yang dijelaskan 16.40 WIB 1 Melakukan Koordinasi dengan petugas gizi puskesmas tentang pemberian makanan tambahan ( PMT-ASI) S: Keluarga mengatakan tidak tau jika harus memberikan pemberian makanan tambahan ( PMT -ASI) O: Keluarga tampak memperhatikan perawat pada saat melakukan tentang pemberian makanan tambahan ( PMT- ASI) 16.50 WIB 1 Keluarga memantau kenaikan BB setiap bulan S: Keluarga mengatakan sudah tau memantau kenaikan BB setiap bulan O: Keluarga tampak mengerti dengan yang dijelaskan
- 54. 58 Tanggal/Waktu No. Dx. Implementasi Respon Paraf 13-10-2022 16.00 WIB 1 Kaji pengetahuan keluarga tentang KMS balita S: Keluarga mengatakan sudah mengetahui tentang KMS Balita O: Keluarga tampak paham terhadap apa penjelasan tentang KMS Balita 16.15 WIB 1 Berikan pengetahuan kepada keluarga tentang memenuhi kebutuhan gizi anak S: Keluarga mengatakan paham terhadap apa yang dijelaskan O: Keluarga tampak mengerti dengan yang dijelaskan
- 55. 59 3.5 Evaluasi Keperawatan Tanggal/Wa ktu Diagnosa Keperawatan Keluarga Evaluasi Sumatif Para f 13-10-2022 16.41 WIB Manajemen Kesehatan keluarga tidak efektif ( D. 0115) b/d Ketidakmampuan keluarga merawat An A dengan gizi kurang ( BGM) karena kurangnya pengetahuan keluarga tentang gizi sehat S: Keluarga mengatakan sudah jelas setelah diberikan pendidikan kesehatan tentang status gizi sehat O: An. A sudah mulai mau makan A: Masalah teratasi sebagian P: Lanjutkan intervensi : 1. Anjurkan keluarga untuk memberikan makanan tambahan pada anak 13-10-2018 17.00 WIB Ketidakmampuan keluarga Tn S mengenal masalah kesehatan pada Anak An A terhadap makna garis kuning pada KMS balita b/d Manajemen Kesehatan keluarga tidak efektif ( D. 0115) S: Keluarga mengatakan sudahj jelas setelah diberikan pendidikan kesehatan tentang KMS Balita O: Ny S sudah bisa menjelaskan tentang KMS Balita A: Masalah semuanya P: Pertahankan intervensi: Anjurkan keluarga untuk tetap memberikaan makanan tambahan pada balita
- 56. 60 BAB IV PENUTUP 4.1 Kesimpulan Upaya penanggulangan gizi kurang memerlukan pendekatan dari berbagai segi kehidupan. Pencegahan dan penanggulangan gizi kurang tidak cukup dengan memperbaiki aspek makanan saja, tetapi juga lingkungan kehidupan balita seperti, pola asuh, tersedianya air bersih dan kesehatan lingkungan (Soekirman, 2002). Terkait dengan permasalahan gizi atau penyebaran penyakit berbasis lingkungan sangat diperlukan kesadaran masyarakat maupun rumah tangga dalam berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran setiap anggota keluarga sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri dibidang kesehatan dan dapat berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat (Depkes RI, 2007). 4.2 Saran a. Bagi Institusi Pendidikan Memberikan kemudahan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan ketrampilannya dalam Asuhan Keperawatan Keluarga Dengan Masalah: Kurang gizi b. Bagi Penulis Selanjutnya Diharapkan penulis dapat menggunakan atau memanfaatkan waktu lebih efektif, sehingga dapat memberikan asuhan keperawatan keluarga pada klien secara optimal. c. Bagi Keluarga Diharapkan keluarga dapat merawat anggota keluarga yang menderita penyakit kurang gizi.
- 57. 61 DAFTAR PUSTAKA PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2020. http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK_No__2_Th_2020_ttg_Stand ar_Antropometri_Anak.pdf Pendahuluan B, Belakang A. http://eprints.ums.ac.id/38210/5/BAB%20I.pdf Muhammad. Download Makalah Askep Keluarga Dengan Gizi Buruk. Repronote.com. Published June 25, 2021. Accessed January 31, 2023. https://www.repronote.com/2021/06/download-makalah-askep-keluarga-gizi- buruk.html ASKEP ANAK GIZI BURUK R.S.U.docx. Scribd. Published 2023. Accessed January 31, 2023. https://www.scribd.com/document/358554740/ASKEP-ANAK-GIZI-BURUK- R-S-U-docx POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PADANG. http://pustaka.poltekkes- pdg.ac.id/repository/Putri_Nur_Azizah_D-III_Keperawatan_2017_x.pdf dylla drd. Makalah gizi kurang. Academia.edu. Published 2020. Accessed January 31, 2023. https://www.academia.edu/26497333/Makalah_gizi_kurang Askep Anak Gizi Kurang. Scribd. Published 2023. Accessed January 31, 2023. https://www.scribd.com/document/265632322/Askep-Anak-Gizi-Kurang